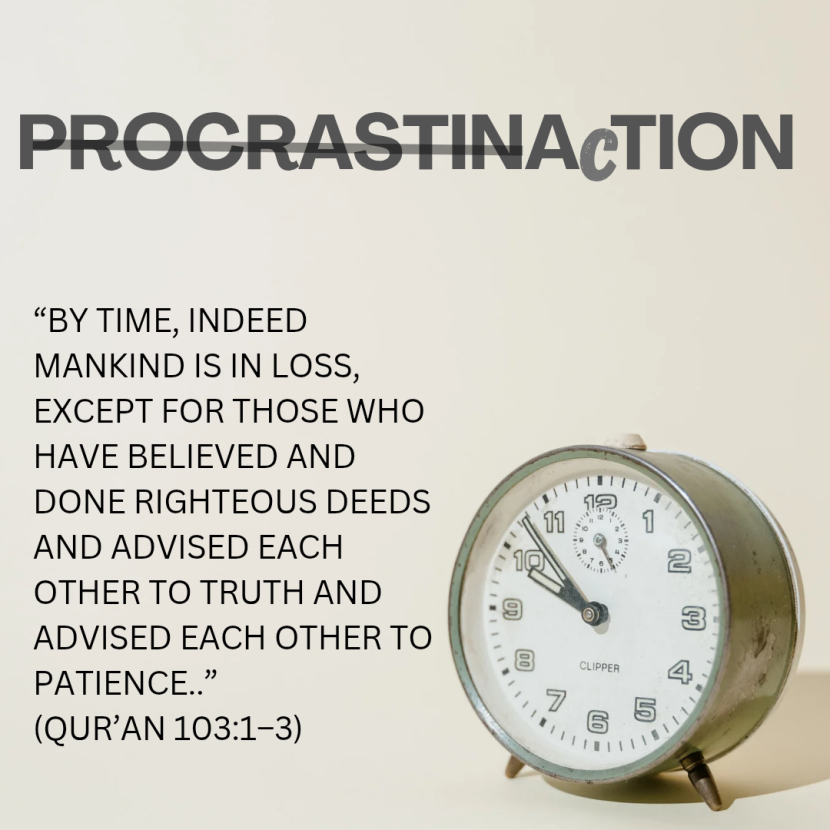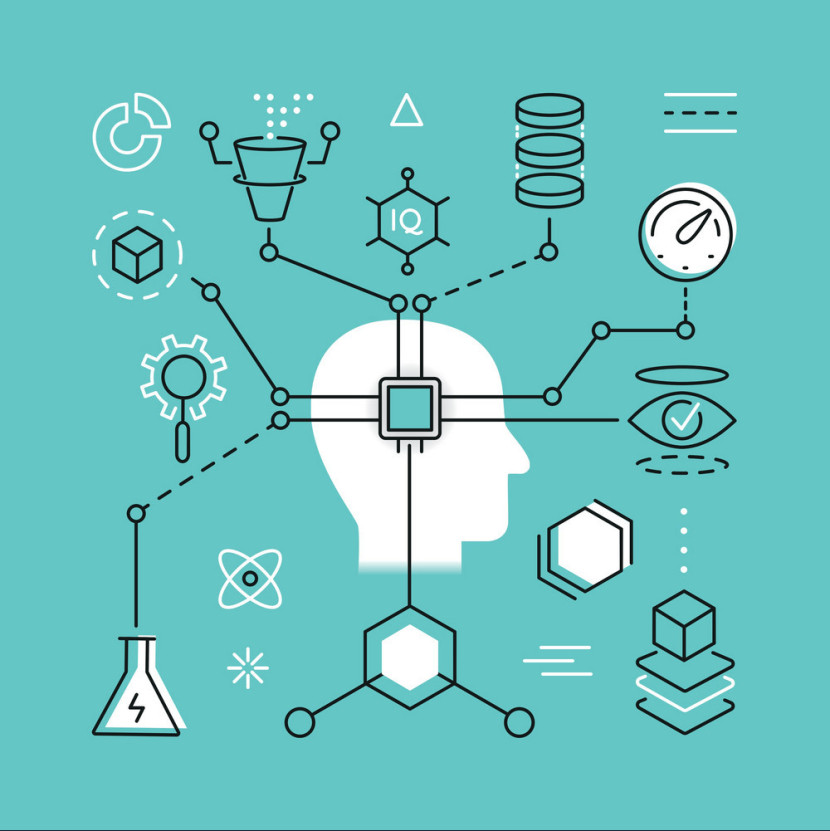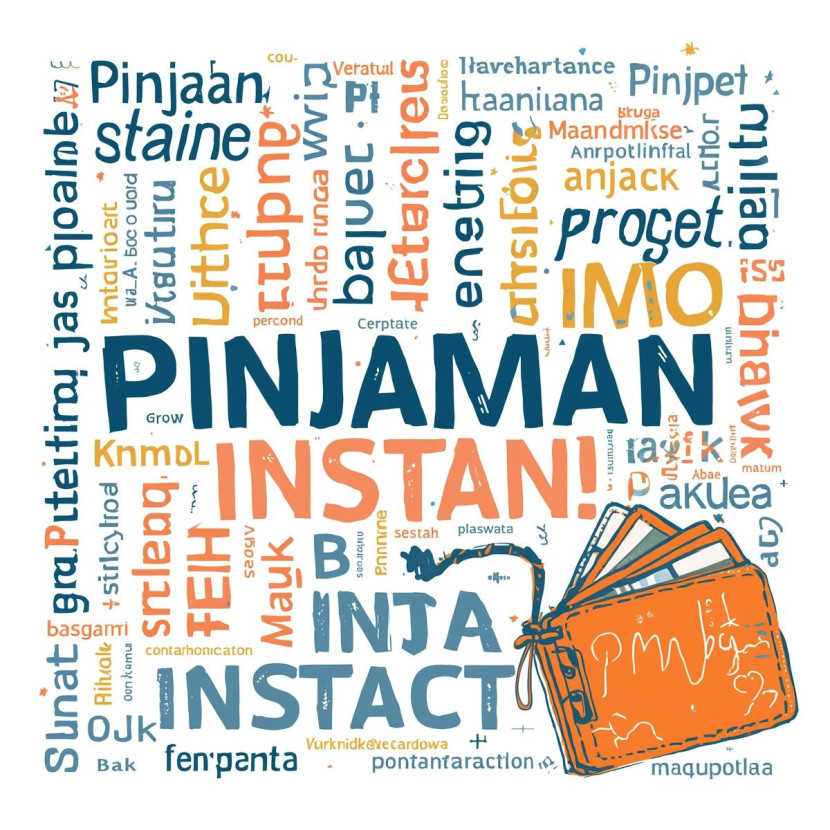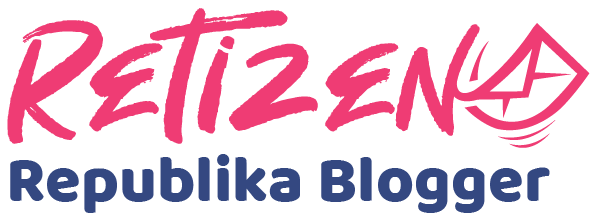Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan
Perkembangan Tasawuf di Nusantara: Peran Spiritualitas Islam dalam Penyebaran dan Kekuatan Politiknya
Dunia islam | 2025-02-24 10:37:42
Pendahuluan
Tasawuf atau sufisme merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ajaran Islam, yang tidak hanya berkembang di Timur Tengah, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Pemikiran tasawuf yang melibatkan upaya pencarian kedekatan dengan Allah melalui pengalaman spiritual dan pengendalian diri telah berperan signifikan dalam proses islamisasi di Indonesia, terutama melalui peran aliran-aliran sufisme atau tarekat di Nusantara.
Salah satu pemikiran penting dalam memahami penyebaran dan pengaruh tasawuf di Nusantara bersumber dari buku Api Sejarah Jilid I karya Ahmad Mansur Suryanegara, yang mengkaji perkembangan tasawuf, terutama melalui pengaruh Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah yang membawa dampak besar dalam proses sejarah Islam di Indonesia.[1]
Definisi Tasawuf dan Kepentingannya dalam Penyebaran Islam
Menurut Sayyid Nur bin Sayyid Ali dikutip dari Kompas.com, tasawuf adalah metode pendidikan spiritual yang dianggap berada dalam derajat temporal-transisional, yang bertujuan untuk memperkokoh keimanan, mencapai derajat ihsan, menyucikan jiwa, dan memperbaiki hati.
Tasawuf, secara ringkas, dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai ridha-Nya. Dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia, tasawuf dipilih sebagai jalur yang mudah diterima oleh masyarakat setempat karena pendekatannya yang lebih bersifat personal dan introspektif. Tasawuf tidak memaksakan perubahan mendasar pada struktur sosial atau budaya yang sudah ada, tetapi mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem keyakinan dan budaya lokal yang telah berkembang.
Tasawuf di Nusantara: Proses Masuk dan Penyebaran
Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, masuknya ajaran tasawuf ke Nusantara sejalan dengan perkembangan Islam antara abad ke-12 M hingga abad ke-17 M di Timur Tengah. Proses penyebaran Islam yang diiringi dengan ajaran tasawuf berlangsung melalui dua jalur utama: jalur dagang dan jalur dakwah para ulama atau sufi.
Ajaran tasawuf sendiri adalah ajaran yang menekankan pada pembentukan akhlak dan pencarian kedekatan kepada Tuhan. Ajaran ini pun sangat menarik bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu, yang masih terpengaruh oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang lebih mengutamakan spiritualitas dan pencarian makna hidup yang mendalam.
Suryanegara juga merujuk pada karya N. A. Baloch yang mengidentifikasi pengaruh kuat tarekat-tarekat besar di dunia Islam pada abad-abad tersebut, yang turut berkembang di Nusantara. Di antara tarekat yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, terdapat dua tarekat utama: Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah.
Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedangkan Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi dari Bukhara pada abad ke-14 sekitar 1390 M. Kedua tarekat ini memiliki pengikut yang luas, baik di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Indonesia
Kedua tarekat ini, Qadiriyah dan Naqsabandiyah, digabungkan dalam bentuk Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah (TQN) yang menjadi aliran tasawuf yang sangat berpengaruh di Indonesia. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, penggabungan kedua tarekat ini dimulai dengan prakarsa Syekh Achmad Chatib Sambas dan Syeklh Abdoel Karim Banten pada abad ke-19. Penggabungan ini bertujuan untuk menyesuaikan ajaran tasawuf dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta menjawab kebutuhan spiritualitas umat Islam yang sedang berkembang pesat pada masa itu.
Penyebaran Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini sangat dipengaruhi oleh peran tokoh-tokoh penting dalam dunia tasawuf di Indonesia, salah satunya adalah K. H. A. Shohibulwafa Tadjul Arifin.
Sebagai seorang pemimpin pesantren di Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Tadjul Arifin mengembangkan dan menguatkan ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah pada abad ke-20. Menurut Suryanegara, kepemimpinan K. H. A. Shohibulwafa Tadjul Arifin menjadikan Pesantren Suryalaya sebagai pusat pengembangan tarekat tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Bahkan, pengaruh TQN dari Suryalaya dapat dilihat melalui penyebaran tarekat ini di berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand.
Peran Tarekat dalam Penyebaran Islam di Indonesia
Suryanegara mengutip pemikiran Dr. A. Mukti Ali, bekas Menteri Agama Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengajaran tasawuf melalui tarekat. Tarekat menjadi salah satu instrumen yang penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia karena melalui tarekat, Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat pribumi, yang memiliki banyak kesamaan dalam hal pengajaran spiritual. Ajaran tasawuf memberikan cara yang lebih “lembut” untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui amalan-amalan dzikir, meditasi, dan pengendalian diri, yang sangat resonan dengan tradisi spiritual masyarakat Indonesia pada waktu itu.
Tarekat-tarekat seperti Qadiriyah dan Naqsabandiyah memiliki pemimpin atau Syekh yang berperan sebagai guru spiritual dan pembimbing umat dalam perjalanan keagamaan mereka. Pada abad ke-16, di mana wilayah Aceh dan Jawa menjadi pusat berkembangnya ajaran tasawuf, beberapa ulama tasawuf terkenal hadir pada masa itu. Di antaranya adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Samatrani, Abdurrauf dari Singkel, Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, dan Sunan Panggung. Dalam hal ini, tasawuf digunakan untuk menggali esensi ajaran Islam yang lebih dalam dan lebih spiritual, yang sesuai dengan keresahan jiwa dan pencarian makna hidup masyarakat lokal.[2]
Nama-nama tersebut tercatat dalam sejarah karena peran mereka dalam mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Selain itu, mereka mendirikan berbagai pusat pengajaran yang berkembang seiring dengan pertumbuhan kesultanan Islam di Nusantara.
Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi
Dalam perkembangannya, tasawuf di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar: tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. K. H. Syaifuddin Amsir dalam NU Online mencatat bahwa tokoh-tokoh besar dari tasawuf sunni di Indonesia antara lain adalah Syekh Nuruddin Arraniri, Syekh Abdu Shomad al-Palembangi, dan Syekh Muhammad Hasyim Asy’ari. Mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh yang membawa ajaran tasawuf yang lebih berlandaskan pada ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali. Ajaran Al-Ghazali ini mengutamakan penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan pencapaian derajat ihsan dalam kehidupan sehari-hari.[3]
Di sisi lain, tasawuf falsafi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari filsuf seperti Al-Hallaj dan Ibnu ‘Arabi yang memiliki pandangan lebih filosofis dan mendalam. Salah satu tokoh yang terkenal dalam kelompok tasawuf falsafi adalah Hamzah Fansuri, yang mengajarkan bahwa Tuhan berada di dalam semua makhluk, sebuah konsep yang sangat mendalam dan kadang sulit diterima oleh kalangan yang lebih konservatif.
Namun, menurut K. H. Syaifuddin Amsir, pemahaman tentang perbedaan antara tasawuf sunni dan tasawuf falsafi tidaklah sederhana. Misalnya, meskipun K. H. Hasyim Asy’ari dikenal sebagai tokoh yang mendalami tasawuf sunni, beberapa doktrin yang dianutnya, seperti doktrin tahallul (penempatan diri pada makhluk lain), sebenarnya lebih dekat dengan ajaran tasawuf falsafi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, batas antara kedua aliran tasawuf tersebut tidak selalu jelas, dan banyak tokoh yang mungkin mengadopsi unsur-unsur dari kedua tradisi tersebut.[4]
Tarekat dan Kekuatan Politik Islam
Penting untuk dicatat bahwa penyebaran tasawuf melalui tarekat sering kali berkaitan dengan perkembangan kekuasaan politik Islam di Nusantara, terutama pada masa pertumbuhan kesultanan. Nama-nama para guru tarekat ini sering tercatat bersamaan dengan nama-nama sultan dan penguasa Islam di Indonesia, mengingat kedekatan antara gerakan tarekat dan kekuasaan politik yang mendukungnya.
Suryanegara menyebutkan bahwa pengaruh tarekat dalam penyebaran Islam sangat berkaitan dengan kekuatan politik Islam pada waktu itu. Para syekh-syekh tarekat tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penasihat politik yang berpengaruh di kalangan penguasa.
Sebagai contoh, banyak sultan di Nusantara yang mendirikan pusat-pusat pengajaran tarekat di wilayah kekuasaannya, yang membantu memperkuat posisi mereka di mata rakyat dan memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tarekat dan tasawuf sering kali berfungsi sebagai instrumen yang mendukung proses politik dan sosial, tidak hanya dalam konteks spiritual tetapi juga dalam penguatan identitas Islam di dunia politik.
Di Aceh, ajaran-ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dan Syamsuddin mendapat perlindungan dari Sultan Iskandar Muda. Berkat dukungan dari penguasa Aceh, karya-karya mereka banyak beredar di kalangan masyarakat dan menjadi bagian dari proses islamisasi di wilayah tersebut.
Selain itu, ajaran tasawuf juga menyebar ke Jawa melalui peran para wali, terutama Sunan Bonang. Sunan Bonang, seperti halnya wali-wali lainnya, menyebarkan ajaran Islam melalui metode yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa, dengan menggunakan media budaya lokal seperti tembang dan suluk.
Suluk sebagai Metode Tasawuf dalam Dakwah Islam
Salah satu metode yang digunakan dalam penyebaran tasawuf di Indonesia adalah suluk. Suluk merupakan perjalanan mistik atau spiritual menuju Tuhan yang dilakukan dengan bimbingan seorang guru (syekh).
Dalam tradisi tasawuf, suluk adalah proses yang sangat pribadi, di mana seorang murid akan melakukan berbagai amalan dzikir dan meditasi untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Suluk menjadi salah satu alat untuk memfasilitasi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan jiwa dan hati.
Suluk juga sering dihubungkan dengan karya-karya mistik dalam bentuk tembang atau puisi, yang menggambarkan perjalanan spiritual seseorang menuju Tuhan. Dalam konteks budaya Jawa, pengajaran tasawuf melalui suluk sangat resonan dengan tradisi lokal yang sudah ada.
Konsep seperti kawula gusti (hamba dan Tuhan) yang diajarkan dalam tasawuf mirip dengan konsep yang sudah ada dalam tradisi Jawa dan Hindu-Buddha, seperti dalam kitab Kunjarakarna. Oleh karena itu, ajaran tasawuf dengan konsep kawula gusti sangat mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang sudah terbiasa dengan pandangan mistik semacam itu.
Tasawuf dan Peranannya dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Peran tasawuf dalam Indonesia tidak hanya terbatas pada dimensi spiritual, tetapi juga berpengaruh besar pada kehidupan sosial dan politik masyarakat. Ajaran tasawuf memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia, yang kemudian membentuk pola pikir dalam menghadapi tantangan sosial dan politik di tengah penjajahan.
Tasawuf mengajarkan pentingnya ketulusan, keikhlasan, dan kesadaran spiritual dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sangat relevan dengan situasi Indonesia pada masa penjajahan, di mana banyak masyarakat yang terjajah merasa tertindas baik secara politik maupun sosial. Dalam hal ini, tasawuf memberikan pencerahan bahwa perjuangan sejati adalah perjuangan untuk mencapai kedamaian batin dan kebenaran spiritual, yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan bermartabat.
K. H. Syaifuddin Amsir juga mengaitkan ajaran tasawuf dengan proses kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, kesadaran spiritual yang dibangun melalui tasawuf telah memberi kekuatan batin bagi para pejuang kemerdekaan.
Ajaran tasawuf yang mengutamakan sikap tawakal, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian menjadi landasan moral yang kokoh dalam perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu, tasawuf memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dengan faktor-faktor lain dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Referensi
[1] Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ed. oleh Nia Kurniawati, Anni Rosmayani, dan Rakhmat Gumilar, Rev., Api Sejarah (Bandung: Suryadinasti, 2014), https://books.google.co.id/books?id=0AMxDwAAQBAJ.
[2] Widya Lestari Ningsih, “Strategi Penyebaran Agama Islam Melalui Jalur Tasawuf,” Kompas.com, 30 Agustus 2022, https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/190000479/strategi-penyebaran-agama-islam-melalui-jalur-tasawuf.
[3] Syaifuddin Amsir, “Peran Tasawuf Dalam Kemerdekaan Indonesia,” NU Online, 21 Februari 2011, https://www.nu.or.id/opini/peran-tasawuf-dalam-kemerdekaan-indonesia-ijS9a.
[4] Sofyan An-Nasyr, “Peran Tasawuf dalam Perkembangan Islam di Indonesia,” PCNU Pati, 8 Agustus 2019, https://pcnupati.or.id/peran-tasawuf-dalam-perkembangan-islam-di-indonesia/.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.