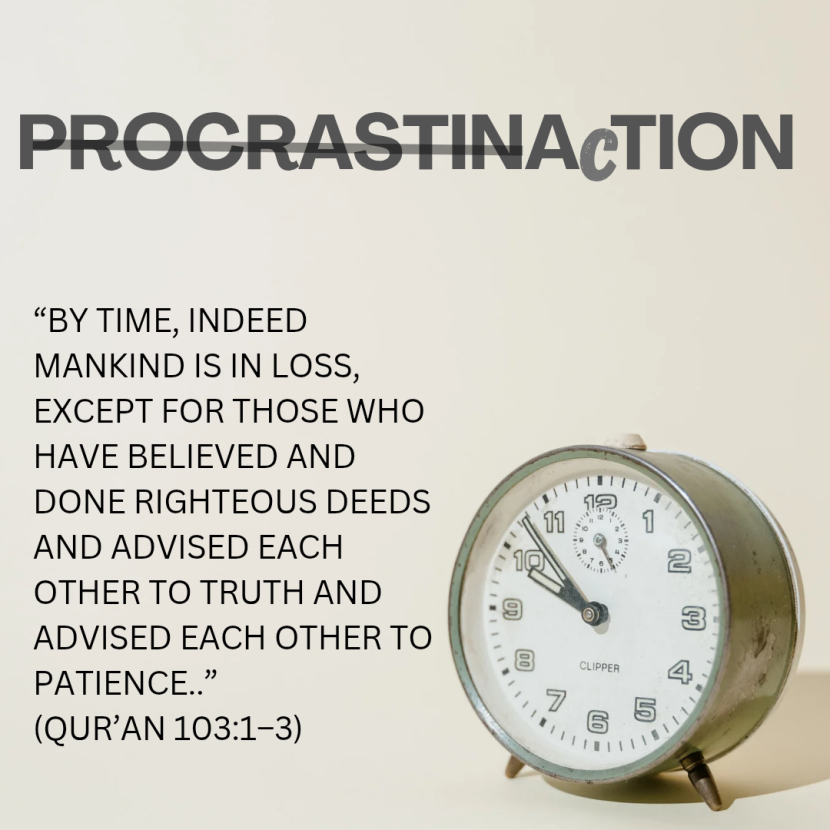Sarkawi B. Husain
Sarkawi B. Husain
Kerajaan Bungku, Islam, dan Perspektif Baru
Sejarah | 2024-11-23 21:00:16
KERAJAAN BUNGKU, ISLAM, & PERSPEKTIF BARU
Oleh Sarkawi B. Husain (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unair)
Sejak berlangsungnya Konferensi Nasional Sejarah yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1957, perkembangan historiografi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Menariknya adalah, secara spasial perkembangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup nasional atau regional, tetapi juga mengalami kemajuan di tingkat lokal. Dengan kata lain, ‘genre’ sejarah lokal berkembang pesat bersamaan dengan perkembangan tema-tema lain dalam sejarah Indonesia. Tahun 1980an adalah periode di mana perkembangan sejarah lokal dapat dikatakan mulai menunjukkan geliatnya. Hal tersebut ditandai dengan diadakannya Seminar Sejarah Lokal, 17-20 September 1984 di Medan. Dalam seminar tersebut, terdapat lima aspek atau tema pokok yang dibahas, yakni: (1) Dinamika masyarakat pedesaan, (2) Pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan integrasi sosial, (3) Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk, (4) Revolusi nasional di tingkat lokal, dan (5) Biografi tokoh lokal (Kuntowijoyo, 1994).
Dalam perkembangan kemudian, sejarah lokal memiliki aspek kajian yang lebih luas dan beragam. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) Sejarah umum, yakni sejarah yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal; (2) Sejarah tematis, yaitu sejarah lokal dengan tema khusus, antara lain: Sosial dan kemasyarakatan yang mencakup sejarah kelas dan golongan sosial, demografi dan kekerabatan, kajian sejarah masyarakat perkotaan, kajian masyarakat pedesaan, perubahan sosial dan tranformasi sosial, masalah sosial seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kriminalitas, prostitusi, kemerosotan sosial, keterbelakangan demoralisasi, kesehatan, gizi, penyakit, gerakan dan protes sosial, olah raga, hiburan, dan rekreasi; (3) Politik, adalah sejarah yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, kenegaraan, dan sejarah kekuasaan; (4) Ekonomi, yakni sejarah yang mempelajari aktivitas manusia dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi pada tingkat lokal; (5) Kebudayaan yg mencakup kreativitas manusia dan bentuk cara berfikir, nilai-nilai, kepercayaan, ideologi, kearifan dan tradisi lokal; (6) Hubungan antar etnis sebagai bagian dari dinamika lokal; (7) Perjuangan dan kepahlawanan lokal, merupakan sebuah sejarah peranan tokoh-tokoh yang dipandang berjasa oleh masyarakat lokal; dan (8) Kegiatan maritim pada tingkat lokal.
Melihat luasnya aspek yang dikaji dalam sejarah lokal, maka studi ini tidak hanya memberi kontribusi bagi perkembagan historiografi, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan birokrat, politisi, dan terutama bagi para pengambil kebijakan dalam upaya memahami masalah-masaah lokal. Seringkali sebuah kebijakan terlepas atau tidak memperhatikan aspek sejarah dan kebudayaan masyarakat dan lokasi setempat, sehingga tidak jarang kebijakan tersebut memicu kerusuhan. Kerusuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat, 24 Desember 2011 berupa pemblokiran Pelabuhan Sape, pembakaran kantor camat, polsek, DPRD Bima, dan kantor PLN Lambu yang berlanjut pada pembakaran kantor bupati pada 26 Januari 2011 adalah contoh yang terang benderang betapa pengambil kebijakan mengabaikan sejarah dari wilayah tersebut. Bagi masyarakat Tanah Sape dan sekitarnya, apa yang mereka lakukan adalah upaya memperjuangkan dan mempertahankan tanah warisan leluhur. Tanah Sape, Lambu, dan sekitarnya merupakan titik awal masuknya Islam ke Bima dan di sana terdapat sejumlah peninggalan sejarah yang dihormati oleh masyarakat. Warga Lambu, Sape, dan sekitarnya sebagai pelaku dan pencetus kerusuhan tersebut memiliki ikatan sejarah masuknya agama Islam di Bima pada 1300-an. Tanah seluas 24.980 hektar yang dieksplorasi PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) adalah tempat di mana para saudagar Islam pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Bima. Dalam areal itu terdapat makam leluhur, termasuk makam para saudagar dan penyiar agama Islam pertama. Pelabuhan Sape dan sekitarnya diyakini sebagai titik awal penyebaran Islam di Bima (Kompas, 9 Febuari 2012).
Bertitik tolak dari kasus Bima, maka membaca buku “Sejarah Kerajaan Bungku” yang ditulis oleh Syakir Mahid, Haliadi-Sadi, dan Wilman Darsono merupakan upaya yang sangat baik untuk memberi pemahaman kepada siapapun, terutama para pengambil kebijakan tentang sejarah dan aspek-aspek yang berhubungan dengan wilayah Bungku. Dengan meminjam berbagai konsep sosilogi dan antropologi, para penulis buku ini mampu menunjukkan bagaimana dinamika Kerajaan Bungku terus berlangsung dari periode ke periode. Kajian yang mengandalkan banyak sumber asing, terutama hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang berbahasa Belanda ini tidak hanya berhasil menyajikan aspek diakronik dari kerajaan ini, tetapi juga aspek sinkronisnya.
Dengan perspektif long dure, Syakir Mahid dan kawan-kawan sukses melakukan elaborasi tentang aspek ke-bagaimana-an dan ke-mengapa-an salah satu kerajan di Sulawesi Tengah yang berdiri pada abad ke-17. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, para penulisnya menunjukkan dengan jelas kondisi daerah Bungku dalam wilayah Kabupaten Morowali sebagai satu kesatuan unit historis. Kedua, penulis berhasil merekonstruksi sekaligus menggambarkan aspek prosesual Kerajaan Bungku hingga terbentuknya Kabupaten Morowali mulai dari pra-sejarah hingga sejarah kontemporer terbentuknya kabupaten. Ketiga, penulis menganalisis dan sekaligus mengembangkan aspek-aspek hidup dan kehidupan masyarakat Bungku baik bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan agama sebagal modal dasar dari proses kesejarahan untuk kepentingan pengembangan Kabupaten Morowali ke depan.
Dalam aspek yang pertama, para penulis tidak hanya menunjukkan kesatuan unit historis tersebut, tetapi juga berhasil ‘membongkar’ pengetahuan kita selama ini tentang awal mula berdirinya kerajaan Bungku. Berbeda dengan informasi yang terdapat dalam buku ‘Sejarah Daerah Sulawesi Tengah’ yang menyebut kerajaan ini berdiri menjelang akhir abad ke-19 sebagai pecahan kerajaan Mori (Adjud, 1996), para penulis menunjukkan hasil penelitian Ester J. Velthoen (seorang peneliti Belanda) yang menyebutkan bahwa masyarakat Tambuku atau Bungku sejak pertengahan abad ke-18 telah memiliki jaringan perdagangan regional sendiri. Dalam La Kartographie Neerlandaise de la Celebesyang dilansir oleh Hessel Gerrits (seorang Portugis) dan terbit pada tahun 1622, keberadaan Bungku disebutkan pertama kali dengan kata “Tobuquo”.
Dalam aspek yang kedua, Syakir Mahid dan kawan-kawan menunjukkan perubahan pemerintahan dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Menurut penulis buku ini, Kerajaan Bungku berdiri pada tahun 1672 oleh Mokole Lamboja yang menjadi Peapua atau Raja Bungku yang berasal dari suku To Routa dan berasal dari peradaban “Wawa Inia Rahampu'u Matano”. Raja yang terakhir memerintah wilayah ini adalah Peapua Abdurabbie (1941-1950) di mana beliau sekaligus menjadi Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Setelah melewati proses yang panjang, pada tanggal 2 Mei 2006, Bungku ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Morowali. Dengan demikian, sejak berbentuk kerajaan hingga sebagai ibu kota kabupaten, Bungku sudah melaksanakan fungsi pemerintahan selama tiga abad lebih, sebuah perjalanan sejarah yang tidaklah pendek.
Pada aspek yang ketiga, para penulis sekali lagi menekankan bahwa untuk kepentingan pengembangan Kabupaten Morowali ke depan, aspek historis dari wilayah ini merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana diketahui, wilayah yang sekarang menjadi ibu kota kabupaten ini, bukanlah wilayah kosong, tetapi tiga abad sebelumnya telah dihuni oleh masyarakat yang memiliki sejarah dan kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, membangun Morowali ke depan berarti membangun masyarakat dengan segenap aspek sejarah dan kebudayaannya. Hal ini kata Syakir Mahid dan kawan-kawan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 1 dan 2, dan pasal 28I ayat 3, yang berbunyi: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (pasal 18 B ayat 1). (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (pasal 18 B ayat 2). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman (pasal 18 B ayat 3).
Sebagai sebuah kerajaan yang telah berusia lebih dari tiga abad, tentu masih banyak hal yang perlu dielaborasi lebih jauh dan lebih dalam. Salah satu aspek tersebut misalnya bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam berserta aspek-aspeknya di wilayah ini. Hal ini menarik dan penting karena di banyak tempat, Islam menjadi salah satu dinamisator dan katalisator dari berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, persoalan agama dan kultural tidak jarang menjadi salah satu aspek yang “memaksa” masyarakat untuk melakukan perlawanan bila kebijakan pemerintah mengabaikan faktor ini, seperti yang ditunjukkan dalam kerusuhan di Bima dan Tanjung Periok beberapa waktu yang lalu. Mengingat banyaknya sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan di wilayah ini, tentu kita tidak berharap niat untuk menyejahterahkan rakyat lewat tambang atau usaha ekonomi lainnya, menjadikan Morowali sebagai Tanjung Periok atau Bima yang kedua hanya karena aspek historis dan kulturalnya terabaikan.◘
Surabaya, November 2024
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.