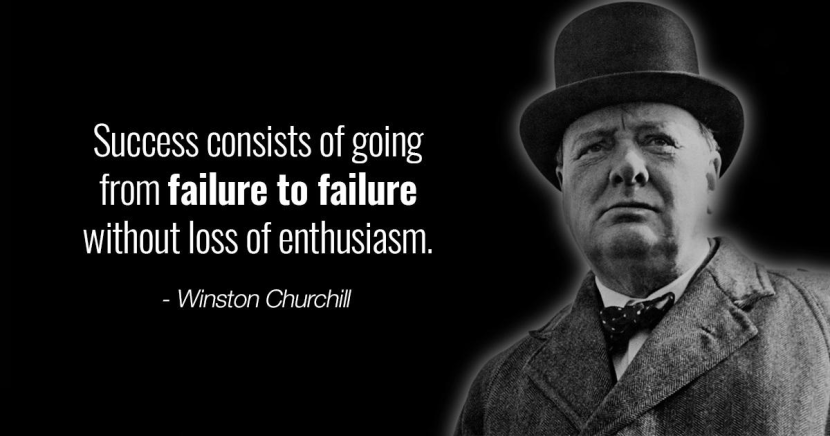Syahrial, S.T
Syahrial, S.T
Langkah Pertama
Sastra | 2024-11-14 21:02:20
Langit Jakarta menggelap pekat sore itu, seolah ikut larut dalam kesedihan yang menyelimuti hati Dinda. Rintik hujan yang semula gerimis kini berubah menjadi tirai air yang membungkus gedung-gedung pencakar langit. Dari balik jendela kantornya di lantai 15, Dinda menatap kosong ke arah titik-titik air yang berlomba turun, membasahi kaca yang dingin dan berkabut. Setiap tetesnya seakan mengingatkannya pada air mata yang telah dia tumpahkan setahun belakangan.
Kesunyian ruangannya yang remang dipecahkan oleh getaran ponsel yang tak henti-hentinya bergetar, menampilkan nama yang sama berulang kali: Mama. Dengan berat hati, Dinda mengangkat telepon itu.
"Sampai kapan kamu mau begini terus, Dinda?" Suara Mama terdengar parau dan letih, menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. "Sudah setahun sejak Reza pergi. Mama nggak sanggup lihat kamu terus-terusan tenggelam dalam kesedihan seperti ini."
Dinda menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang kembali meluap. "Ma, aku lagi kerja. Nanti aja ya kita ngobrolnya." Suaranya bergetar menahan tangis.
"Kerja? Mama tau kamu cuma duduk melamun di kantor. Pak Bambang udah cerita ke Mama kalau kinerja kamu menurun drastis. Dinda, kamu nggak bisa terus-terus mengubur dirimu dalam kesedihan begini..."
Tanpa menunggu Mama menyelesaikan kalimatnya, Dinda memutus sambungan telepon. Air matanya mengalir deras, secepat hujan yang mengguyur di luar. Bayangan setahun lalu kembali menghantui - saat Reza, tunangannya, dengan tatapan sendu memilih untuk mengakhiri lima tahun hubungan mereka dan menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Sejak saat itu, dunia Dinda seakan runtuh, meninggalkan puing-puing kenangan yang menyesakkan.
Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Dinda akhirnya membereskan mejanya yang berantakan. Hujan masih turun rintik-rintik, menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak. Di lobby kantor yang mulai sepi, langkahnya yang gontai terhenti saat berpapasan dengan Pak Bambang, direkturnya.
"Dinda," panggil Pak Bambang dengan suara tegas namun terselip nada kepedulian yang dalam. "Besok pagi ke ruangan saya ya."
Dinda hanya mengangguk lemah, sementara jantungnya berdegup kencang. Dia tahu persis apa yang akan dibicarakan.
Malam merangkak lambat di kamar kosnya yang pengap. Dinda terbaring menatap langit-langit, sementara pikirannya berkelana ke masa-masa indah bersama Reza. Kenangan akan tawa riang mereka di kafe favorit, rencana-rencana masa depan yang telah mereka rajut bersama, kini hancur berantakan bagai kepingan puzzle yang tak bisa disatukan kembali. Dinda selalu bergantung pada Reza untuk segala hal - dari keputusan besar hingga hal-hal kecil dalam hidupnya. Tanpa Reza, dia merasa seperti daun kering yang terombang-ambing, kehilangan arah dan tujuan.
Pagi menjelang dengan awan kelabu yang masih setia menggantung di langit Jakarta. Dengan langkah berat dan jantung yang berdebar, Dinda duduk di hadapan Pak Bambang dalam ruangan yang terasa mencekam.
"Dinda," Pak Bambang memulai, matanya memancarkan ketegasan sekaligus kebijaksanaan, "saya tau setahun terakhir ini berat buat kamu. Tapi kamu harus bangkit. Potensi besar yang kamu miliki terbuang sia-sia karena kamu membiarkan masalah pribadi menghancurkan karirmu."
"Maaf, Pak..." suara Dinda nyaris tak terdengar, tenggelam dalam rasa bersalah.
"Saya tidak bermaksud menekan kamu. Tapi hidup harus terus berjalan, seperti awan yang tetap bergerak meski badai menghadang. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Lihat Ibu Ratna, dia single parent dengan tiga anak, tapi dia tetap berdiri tegak sebagai manager terbaik kita. Atau Mas Adi, yang tetap profesional meski sedang menghadapi badai rumah tangga."
Kata-kata Pak Bambang menohok tepat ke ulu hati Dinda. Selama ini dia terlalu tenggelam dalam kubangan kesedihannya sendiri, lupa bahwa di luar sana, orang lain juga memikul beban yang tidak kalah berat.
"Saya kasih kamu kesempatan," lanjut Pak Bambang, matanya menatap lurus ke arah Dinda. "Ada proyek baru di Surabaya. Tiga bulan. Mungkin ini bisa jadi titik balik buat kamu. Kamu mau ambil?"
Dinda terdiam, meresapi tawaran itu dalam-dalam. Surabaya. Kota yang jauh dari bayangan Reza. Jauh dari tatapan khawatir Mama yang seakan menghantui setiap langkahnya. Mungkin ini kesempatan yang dikirim semesta untuk memulai lembaran baru.
"Saya... saya mau, Pak." Ada getaran keyakinan dalam suaranya yang sudah lama hilang.
Tiga bulan di Surabaya mengubah Dinda seperti kepompong yang perlahan bermetamorfosis. Di kota ini, dia belajar hidup mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan yang terpenting - menghadapi setiap masalah dengan keberanian yang dia temukan perlahan-lahan. Tanpa dia sadari, senyum yang dulu hilang mulai kembali menghiasi wajahnya. Dia menemukan kembali gairah dalam bekerja, seperti menemukan oasis di tengah gurun.
Di minggu terakhir proyeknya, Dinda duduk di sebuah kafe yang menghadap ke laut Kenjeran. Aroma kopi mengepul hangat, menemani jemarinya yang menari di atas keyboard laptop, menulis email untuk Mama:
"Ma, besok Dinda pulang ke Jakarta. Tiga bulan ini mengajarkan banyak hal ke Dinda. Seperti ombak yang tetap bergulung meski diterjang badai, Dinda akhirnya sadar kalau selama ini Dinda terlalu bergantung sama orang lain. Sama Reza, sama Mama. Dinda lupa cara berdiri dengan kaki sendiri. Tapi sekarang Dinda udah lebih kuat, Ma. Dinda udah belajar kalau masalah itu datang ke semua orang, seperti hujan yang turun tanpa memilih, dan kita nggak bisa berharap orang lain yang menyelesaikannya. Kita harus hadapi sendiri, dengan kepala tegak dan hati yang tabah.
Makasih ya Ma, udah sabar ngadepin Dinda selama ini. Dinda sayang Mama."
Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langit Jakarta tampak cerah, secerah hati Dinda yang kini dipenuhi keyakinan baru. Ya, dia pernah jatuh. Tapi seperti matahari yang selalu terbit setelah malam yang paling gelap, dia sudah belajar untuk bangkit dengan kakinya sendiri. Dan kali ini, dia yakin bisa melangkah lebih jauh, lebih kuat dari sebelumnya.
Di ruang kedatangan yang riuh, Mama sudah menunggu dengan senyum bangga terkembang. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, Dinda bisa membalas senyum itu dengan ketulusan yang memancar dari dalam hatinya. Dia bukan lagi Dinda yang rapuh seperti daun kering. Dia adalah Dinda yang telah menemukan kekuatannya sendiri, seperti pohon yang akarnya menancap kuat ke bumi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.