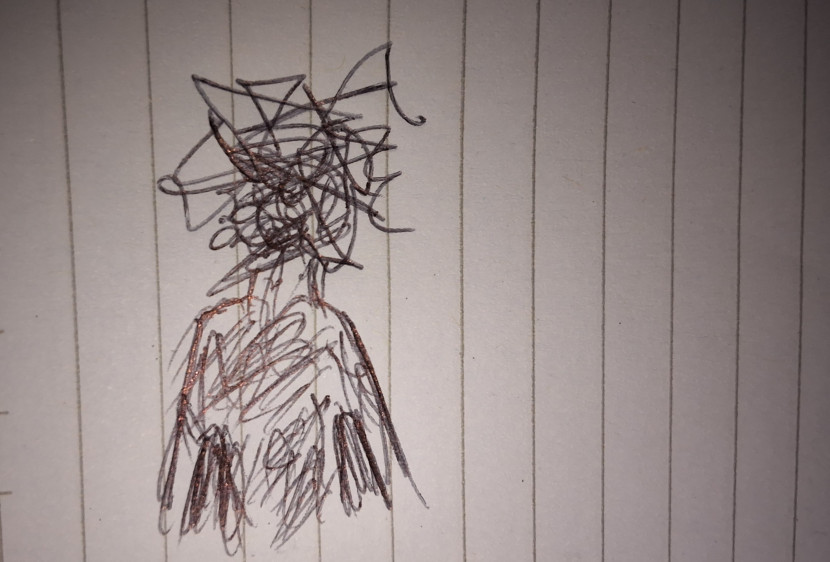Syahrial, S.T
Syahrial, S.T
Halte Terakhir
Sastra | 2024-11-14 12:38:35
Hujan deras mengguyur kota sore itu. Dinda berdiri ragu di depan halte bus, matanya menatap jauh ke arah jalanan yang mulai tergenang. Tetes-tetes air hujan menari-nari di atas permukaan genangan, menciptakan riak-riak kecil yang seolah mengejek kebimbangannya. Payung biru pemberian ibunya masih terlipat rapi dalam tas, sama rapinya dengan segala rencana masa depan yang kini mulai goyah dalam benaknya. Ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk pulang, seolah takdir sedang bermain-main dengan pikirannya.
Langit kelabu di atas kepalanya seakan merefleksikan kemelut dalam hatinya. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi khas hujan kota - aspal basah dan dedaunan yang tertiup angin - menciptakan atmosfer yang entah mengapa terasa begitu sendu. Di kejauhan, petir sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang pucat dengan kilatan singkat.
"Bus terakhir akan datang 15 menit lagi," gumamnya sambil melirik jam tangan. Waktu terasa begitu lambat ketika kita sedang menunggu, pikirnya, tapi mengapa terasa begitu cepat ketika kita harus membuat keputusan besar?
Di saku jasnya, ponsel bergetar untuk kesekian kalinya. Getarannya terasa seperti dentuman kecil yang mengguncang hatinya. Nama "Raka" muncul di layar, disertai 12 panggilan tak terjawab sebelumnya. Setiap notifikasi panggilan tak terjawab itu bagaikan jarum kecil yang menusuk nuraninya. Dinda menghela napas panjang, menghembuskan segala keraguan yang berkecamuk dalam dadanya.
Matanya terpejam sejenak, membiarkan pikiran melayang ke lima tahun yang telah ia lalui bersama Raka. Setiap tawa yang mereka bagi, setiap air mata yang mereka hapus bersama, setiap mimpi yang mereka rajut dalam diam - semua berkelebat dalam benaknya seperti film yang diputar terlalu cepat. Kenangan-kenangan itu terasa begitu manis, namun kini meninggalkan rasa pahit di tenggorokannya.
"Sampai kapan kamu mau menghindar?" Suara Raka terdengar lelah ketika Dinda akhirnya mengangkat telepon. Ada nada putus asa yang tersembunyi di balik suaranya yang berat - nada yang membuat hati Dinda terasa diremas.
"Aku tidak menghindar," jawab Dinda pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Bahkan ke telinganya sendiri, alasan itu terdengar lemah.
"Tawaran beasiswa S2 di Jerman tidak akan menunggu selamanya, Din. Deadline-nya tinggal dua hari lagi."
Dinda memejamkan mata, membiarkan dinginnya angin hujan membelai wajahnya. Beasiswa itu - mimpi yang selama ini ia kejar dengan segenap jiwa raganya. Tiga tahun ia habiskan untuk memperbaiki kemampuan bahasa Jermannya, menghabiskan malam-malam panjang dengan buku dan kamus, mengumpulkan sertifikat demi sertifikat, dan membangun portfolio yang sempurna.
Setiap detik dari usaha itu terukir dalam ingatannya - air mata frustasi saat gagal dalam ujian pertama, senyum bahagia saat akhirnya berhasil menguasai tata bahasa yang rumit, dan tentu saja, dukungan tak henti dari Raka di setiap langkahnya. Sekarang, ketika kesempatan itu akhirnya ada di depan mata, mengapa ia justru ragu?
"Bagaimana dengan kita?" tanya Raka lagi, suaranya kini lebih lembut, menyentuh sudut hati Dinda yang paling dalam. "Bagaimana dengan rencana pernikahan kita tahun depan?"
Pertanyaan yang sama yang terus berputar dalam benaknya seperti kaset rusak. Raka, kekasihnya selama lima tahun terakhir, baru saja dipromosikan sebagai kepala cabang di bank tempatnya bekerja. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak setahun lalu, membangun istana pasir mimpi mereka dengan penuh harap. Orangtua kedua belah pihak bahkan sudah mulai membicarakan tanggal yang tepat, berbagi senyum dan harapan akan masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka.
Dinda bisa membayangkan wajah ibunya yang berbinar setiap kali membahas persiapan pernikahan, atau senyum hangat ayahnya setiap kali Raka berkunjung. Bagaimana mungkin ia tega menghancurkan harapan mereka? Namun di sisi lain, bukankah orangtuanya juga yang selalu mengajarkan untuk mengejar mimpi setinggi langit?
"Kamu tahu kan ini kesempatan sekali seumur hidup?" Dinda mencoba menjelaskan, suaranya bergetar menahan emosi. "Aku sudah bermimpi tentang ini sejak lama."
"Dan aku? Apa aku bukan bagian dari mimpimu?"
Pertanyaan itu menohok tepat di dada Dinda, meninggalkan luka yang tak kasat mata. Air matanya mulai menggenang, bercampur dengan tetes hujan yang sesekali membasahi wajahnya. Tentu saja Raka adalah bagian dari mimpinya. Pria itu telah menjadi konstanta dalam hidupnya selama lima tahun terakhir - tempat bersandar ketika lelah, tempat berbagi ketika bahagia. Tapi haruskah ia mengorbankan kesempatan ini demi cinta? Atau justru mengorbankan cinta demi karir?
Bus terakhir mulai terlihat di kejauhan, lampu-lampunya menembus kabut hujan seperti mercusuar di tengah badai. Dinda masih terpaku di tempatnya, kakinya seakan terpaku pada lantai halte yang dingin.
"Din?" suara Raka membuyarkan lamunannya.
"Ya?" jawabnya lirih, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru hujan.
"Kalau kamu memilih beasiswa itu... aku tidak bisa menunggu."
Kalimat itu terasa seperti tamparan telak di wajahnya, menghempaskan segala harapan yang masih tersisa. Dadanya sesak, seakan seluruh udara tiba-tiba tersedot keluar dari paru-parunya. Dinda tahu Raka tidak bermaksud mengancam - pria itu hanya jujur, seperti yang selalu ia lakukan. Mereka berdua tahu hubungan jarak jauh selama dua tahun bukanlah hal mudah, apalagi dengan perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing. Tapi mengapa kejujuran itu terasa begitu menyakitkan?
Bus sudah berhenti di depannya. Pintu terbuka dengan suara desisan pelan, menunggu dengan sabar, seolah memberikan Dinda waktu untuk menimbang sekali lagi keputusannya. Suara mesin bus yang menderu pelan berpadu dengan gemuruh hujan, menciptakan melodi pengiring bagi momen yang akan mengubah hidupnya selamanya.
"Aku harus memutuskan sekarang?" tanya Dinda lirih, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri.
"Tidak. Tapi ingat, kadang tidak memutuskan adalah sebuah keputusan juga."
Dinda menatap bus di depannya, merasakan hembusan angin dingin dari pintunya yang terbuka. Jika ia naik bus ini, ia akan pulang ke rumah, ke zona amannya, ke pelukan Raka dan keluarga yang mendukungnya. Kehangatan dan kepastian menunggunya di sana. Tapi jika ia memilih untuk tidak naik... ia akan melangkah ke teritoru tak dikenal, mengejar mimpi yang mungkin saja akan membawanya ke puncak tertinggi, atau justru menghempaskannya ke jurang terdalam.
"Maaf, Pak," kata Dinda pada sopir bus yang menunggunya dengan sabar. Suaranya kini lebih tegas, seakan seluruh keraguannya telah luruh bersama air hujan. "Saya tidak jadi naik."
Pintu bus menutup dengan desisan pelan, membawa pergi kesempatan terakhirnya untuk kembali ke kehidupan yang telah ia rencanakan. Hujan mulai mereda, menyisakan rintik-rintik halus yang memantulkan cahaya lampu jalan.
"Raka," katanya ke telepon, jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah membuat keputusan."
"Dan?"
"Aku akan mengambil beasiswa itu." Suaranya bergetar tapi tegas, seperti dawai gitar yang dipetik terlalu keras. "Aku mencintaimu, sangat. Setiap kenangan bersamamu akan selalu kujaga dalam hatiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku bertanya-tanya 'bagaimana jika' seumur hidupku. Aku perlu mengejar mimpiku ini."
Hening sejenak di seberang sana. Dinda bisa membayangkan Raka duduk di kursi kerjanya, memandang ke luar jendela kantornya yang menghadap ke kota, mungkin juga sedang diguyur hujan yang sama.
"Aku mengerti," jawab Raka akhirnya, suaranya tenang namun Dinda bisa mendengar getaran emosi di dalamnya. "Mungkin memang ini yang terbaik."
"Maafkan aku." Air mata Dinda kini mengalir bebas, bercampur dengan tetes hujan yang membasahi wajahnya.
"Jangan minta maaf karena mengejar mimpimu, Din. Kamu selalu bilang takdir bukan sesuatu yang terjadi begitu saja - tapi hasil dari pilihan yang kita buat. Ini pilihanmu. Jalani dengan sepenuh hati."
Air mata Dinda menetes semakin deras, namun ada senyum tipis yang mulai terbentuk di bibirnya. "Terima kasih sudah mengerti."
Telepon ditutup, menyisakan dengung sunyi yang memekakkan telinga. Dinda mengeluarkan payung birunya dan mulai berjalan. Langkahnya kali ini pasti, tanpa keraguan, meski hatinya terasa berat. Di atas kepalanya, awan-awan mulai bergeser, membiarkan secercah cahaya matahari senja menembus kelabu.
Ya, mungkin ini bukan ending bahagia yang selama ini ia bayangkan. Mungkin ini akan menjadi awal dari rangkaian hari-hari sulit yang harus ia hadapi sendiri. Tapi ini adalah pilihannya - pilihan yang ia buat dengan kesadaran penuh bahwa setiap keputusan membawa konsekuensinya masing-masing.
Takdir memang bukan tentang kebetulan. Takdir adalah tentang keberanian untuk memilih, dan keikhlasan untuk menerima segala konsekuensi dari pilihan tersebut. Dan Dinda, di bawah langit yang mulai cerah sehabis hujan, telah memilih untuk menulis takdirnya sendiri.
Ia tersenyum kecil, menggenggam erat payung pemberian ibunya, merasakan tekstur pegangannya yang sudah aus dimakan waktu - seperti cintanya yang mungkin akan memudar seiring berjalannya waktu. Perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya kini ia tahu ke mana arah yang akan ia tuju. Karena terkadang, melepaskan sesuatu yang berharga adalah harga yang harus dibayar untuk meraih mimpi yang lebih besar. Dan Dinda siap membayar harga itu, dengan segenap keberanian dan keteguhan hati yang ia miliki.
Di belakangnya, kota mulai menyalakan lampu-lampunya, menciptakan panorama senja yang memukau - seperti lembaran baru yang siap ia tulisi dengan kisah-kisah baru, mimpi-mimpi baru, dan mungkin suatu hari nanti, cinta yang baru.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.