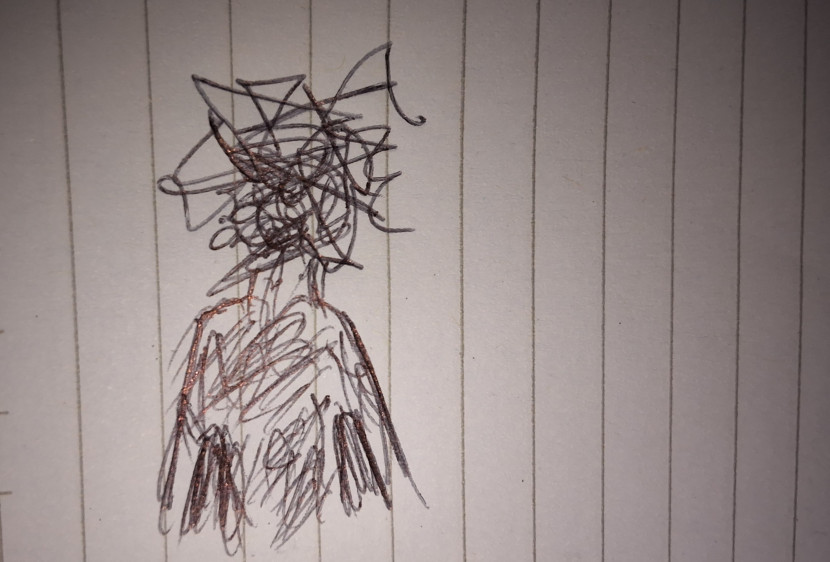Syahrial, S.T
Syahrial, S.T
Perjalanan Menuju Cahaya
Sastra | 2024-10-29 15:34:08
Fajar belum juga menyingsing ketika Pak Rahmat memulai harinya. Dengan langkah gontai, ia menyusuri jalanan kampung yang masih sepi. Ransel usang tersampir di bahunya, berisi beberapa buku bekas dan setumpuk kertas ulangan yang belum ia periksa. Dua puluh lima tahun mengajar di sekolah dasar pelosok desa tidak membuatnya lelah, meski gajinya tak seberapa.
"Pak Guru! Tunggu, Pak!"
Suara cempreng itu membuat langkahnya terhenti. Dewi, salah satu muridnya yang paling cerdas, berlari-lari kecil menghampirinya dengan nafas terengah-engah.
"Ada apa, Dewi? Kok pagi-pagi sudah berkeliaran?"
"Pak, saya mau kasih ini." Dewi menyodorkan sebuah amplop putih lusuh. "Dari Ibu buat Bapak."
Pak Rahmat membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas berisi tulisan tangan yang agak berantakan:
Mohon maaf Pak Guru, saya belum bisa bayar uang sekolah Dewi bulan ini. Suami saya masih sakit, penghasilan dari jualan sayur belum cukup. Tapi saya janji akan melunasi segera begitu ada rezeki. Tolong jangan keluarkan Dewi dari sekolah.
Pak Rahmat menghela nafas panjang. Ini bukan kali pertama ia menerima surat semacam ini. Sebagai kepala sekolah, seharusnya ia bisa tegas. Tapi hatinya selalu luluh melihat semangat belajar anak-anak seperti Dewi.
"Sampaikan pada ibumu, tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap rajin belajar."
Mata Dewi berbinar-binar. "Terima kasih, Pak! Saya janji akan dapat nilai bagus!"
Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Mengajar di kelas yang atapnya bocor saat hujan, menulis di papan tulis yang sudah kusam, hingga rapat dengan komite sekolah yang selalu membahas masalah yang sama: kekurangan dana.
"Pak Rahmat, sampai kapan kita harus begini?" keluh Bu Siti, guru senior yang sudah seperti kakaknya sendiri. "Bapak sudah terlalu baik membiarkan banyak murid nunggak bayaran. Sekolah kita bisa tutup kalau begini terus."
"Lantas kita harus bagaimana, Bu? Mengeluarkan mereka? Membiarkan mereka putus sekolah?"
"Tapi gaji guru-guru juga sering telat. Bapak sendiri sudah berapa bulan tidak mengambil gaji? Semua Bapak pakai untuk menutupi operasional sekolah."
Pak Rahmat terdiam. Memang benar, sudah tiga bulan ia tidak mengambil gajinya. Istrinya di rumah harus ekstra hemat mengatur pengeluaran. Kadang ia merasa bersalah melihat istrinya harus berjualan kue keliling untuk membantu ekonomi keluarga.
Suatu hari, sebuah tawaran menggiurkan datang. Sekolah swasta elit di kota menawarkan posisi wakil kepala sekolah dengan gaji tiga kali lipat dari yang ia terima sekarang. Godaan itu begitu besar, apalagi putrinya akan segera masuk kuliah.
"Ayah, terima saja tawaran itu," bujuk putrinya suatu malam. "Ayah sudah terlalu lama berkorban untuk sekolah ini. Sekarang waktunya memikirkan masa depan kita."
Pak Rahmat memandang foto-foto di dinding rumahnya. Foto wisuda angkatan pertama yang ia didik, yang kini sudah menjadi dokter, insinyur, dan guru. Foto Dewi yang memenangkan olimpiade matematika tingkat provinsi. Foto anak-anak yang tersenyum lebar saat menerima bantuan buku dari hasil ia menyisihkan gajinya.
Pagi itu, Pak Rahmat menulis surat penolakan untuk tawaran menggiurkan tersebut. Hatinya sudah mantap. Ia memilih bertahan, meski itu berarti harus terus berjuang dengan segala keterbatasan.
Lima tahun berlalu. Sekolah yang hampir tutup itu kini mulai bangkit. Beberapa alumni yang sudah sukses memberikan bantuan dana. Bangunan sekolah diperbaiki, fasilitas ditambah. Yang lebih membanggakan, prestasi akademik sekolah terus meningkat.
Dewi, si murid cerdas itu, kini sudah menjadi mahasiswa kedokteran dengan beasiswa penuh. Ia sering berkunjung ke sekolah, berbagi cerita dan motivasi dengan adik-adik kelasnya.
"Pak Rahmat yang mengajarkan saya arti kesabaran dan perjuangan," kata Dewi dalam pidatonya saat acara ulang tahun sekolah. "Beliau tidak pernah menyerah pada keadaan, tidak pernah mengeluh meski gajinya sering telat. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tidak peduli dari keluarga mampu atau tidak."
Air mata Pak Rahmat menetes mendengar kata-kata itu. Ia teringat masa-masa sulit yang telah dilalui. Semua pengorbanan, semua kesabaran dalam menghadapi situasi yang kadang membuatnya frustrasi, kini membuahkan hasil yang manis.
"Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita memang harus mampu bersabar dengan apa yang kita benci," bisiknya pelan. "Tapi kesabaran itu akan berbuah manis pada waktunya."
Di usianya yang sudah kepala enam, Pak Rahmat masih tetap mengajar dengan semangat. Meski sudah ada tawaran pensiun dengan pesangon besar, ia memilih bertahan. Baginya, melihat anak-anak didiknya berhasil adalah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Kisah Pak Rahmat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari materi, tapi dari seberapa banyak kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bahwa kesabaran dalam menghadapi kesulitan akan membuahkan kebahagiaan yang lebih besar. Dan yang terpenting, bahwa cinta pada pendidikan dan masa depan anak bangsa lebih berharga dari segala kemewahan dunia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.