 Widyastuti, S.S.
Widyastuti, S.S.
Aku Hanya Ingin Pulang
Sastra | 2022-12-31 13:02:05
Aku hanya bisa terpaku menatap sungai di depanku, tak terasa air mataku mengalir deras. Seakan ada sesuatu yang hilang dari tubuhku, seakan separuh jiwaku melayang. Rasa bimbang dalam diri kembali hadir menyeruak di sebongkah hati yang tadinya sudah bulat kini mengendur. Seakan tidak kuat menahan beban rasa tidak percaya membuatku berjongkok di pinggir sungai, krisis kepercayaanku ini sepertinya sama dengan ketidakpercayaanku terhadap sungai ini.
Mampukah sungai itu mengantarkan perahu yang nanti akan kutumpangi menyusuri hingga ke tempat tujuan. Aliran sungai yang mungkin aku berdiri tidak akan tenggelam dapatkah dilewati oleh sebuah perahu dengan membawa beberapa penumpang, belum lagi barang-barangnya. Sepertinya aku ingin kembali berlari ke tempat semula, dan membatalkan kepulanganku.
“Sudahlah, jangan kau sesali apa yang sudah kau putuskan. Kalau kau ingin menangis, menangislah sepuasmu. Tapi kau tidak mungkin kembali, kalau kau ingin kembali harus menunggu ada mobil dan entah kapan akan datang.” Kata seseorang yang tiba-tiba berdiri di sampingku. Aku tidak tahu mengapa dia bisa tahu apa yang aku rasakan dan aku pikirkan. Apakah dia bisa membaca hati dan pikiranku? Aku hanya menoleh sekilas kepadanya. Entahlah perasaan yang sesak terasa menghimpitku tanpa sadar aku menangis sesenggukan, seakan ingin kutumpahkan semua apa yang ada di dalam hatiku, ingin kukeluarkan semua bebanku. Namun aku tak mampu berkata, hanya air mataku yang bisa meringankan bebanku. Laki-laki itu ikut jongkok di sampingku.
“Kau ingin pulang, kan?” tanyanya
Aku hanya bisa mengangguk, tanpa bisa bicara. Seakan bibirku berat untuk berkata-kata. Apa yang kurasakan di dalam hatiku seakan mengikat kuat-kuat mulutku.
“Kapal sudah hampir sampai, tunggulah sebentar. Setelah kau meninggalkan tempat ini kau akan segera melupakan semua yang terjadi di sini. Setelah sampai lautan lepas kau akan bebas seperti burung yang bebas terbang. Kita ibarat burung yang dilepas namun kita akan tetap pulang ke sarang kita.” Katanya dengan menepuk pundakku seakan ingin menguatkan keputusanku.
Aku hanya terdiam mendengar semua omongannya. Sedikit demi sedikit bebanku terasa ringan. Aku tidak percaya anak semuda itu sudah mempunyai pikiran untuk menasehatiku yang lebih tua. Mungkin anak itu usianya lebih muda dari adikku yang kecil. Kuusap air mataku, aku berdiri dan berjalan ke bibir sungai. Kulihat di ujung tebing ada satu keluarga yang berdiri disamping barang bawaan yang lumayan banyak. Sang ibu menggendong anak laki-laki kecil yang usianya mungkin baru sekitar dua tahun. Di depan ibunya berdiri anak perempuan yang usianya sekitar enam tahun. Anak perempuan itu memandang diriku tanpa berkedip, mungkin dia heran mengapa aku menangis. Aku membetulkan jilbabku dan kututupi wajahku. Laki-laki itupun mengikuti langkahku dan berjalan di sampingku.
“Lihatlah, anak kecil itu saja tidak menangis malah menanti penuh harap akan kedatangan perahu. Dia merasa yakin bahwa perahu pasti akan datang, dan akan membawa dia pulang.” Kata laki-laki itu seakan tahu kemana arah mataku tertuju.
Langkahku terhenti dan memandang anak perempuan itu. Seakan kekuatanku kembali datang, segala keraguan seakan hilang. Keinginan kembali ke Batu Lima menjadi surut. Aku membayangkan kembali ke sana dengan naik mobil hardtop terbuka melewati hutan dan perkebunan sawit rasanya ngeri. Melewati hutan yang telah ditebangi menjadi lahan luas tanpa pepohonan dengan tanah merahnya membuatku miris. Sepertinya orang-orang itu tidak merasa sayang terhadap hutan lindung, mereka menebang pohon seenaknya sendiri. Mejadikan hutan sebagai perkebunan sawit yang lebih menggiurkan hasilnya. Aku bertanya pada diriku sendiri milik siapakah hutan ini? Hutan yang begitu luas di pedalaman ditebang secara liar. Kayunya mereka masukkan ke pabrik-pabrik plywood. Mungkin juga kayu itu ada juga yang di bawa ke kilang tempatku bekerja. Mungkinkah uangnya masuk kas negara? Ataukah ada orang yang mempunyai hutan luas di daerah terpencil dan dekat perbatasan ini. Lalu siapa yang mau bekerja di perkebunan sawit di daerah terpencil jauh dari suasana desa. Mampukah mereka bertahan hidup dan membeli makanan karena akses ke jalan raya sangat jauh sekali. Sejauh mata memandang hanya hutan sawit dan lahan kosong yang belum di tanami. Aku jadi teringat seseorang zero-zero dari Filiphina yang sering aku panggil Pak Cik. Dia melarikan diri dari perkebunan sawit karena tidak kuat dengan pekerjaannya. Setiap hari dia harus berjalan berkilo-kilo meter untuk memetik sawit. Hasil petikannya harus dia bawa ke tempat yang bisa di jangkau kendaraan yang jaraknya juga lumayan jauh. Apabila musim panen dia bisa dua-tiga hari tidak pulang dan membuat gubuk di hutan, karena kalau pulang sangat capek dan tidak ada hasilnya. Akhirnya Pak Cik dan keluarganya pergi meninggalkan kebun kelapa sawit karena hasilnya tidak sepadan dengan kerja kerasnya. Pak Cik kemudian bekerja di kilang kayu dengan Id card zero-zero. Membeli Id card palsu agar bisa bekerja di pabrik, namun apabila ada pemeriksaan polisi dia akan ijin tidak bekerja berhari-hari sampai suasana aman. Dia dan keluarganya akan pergi masuk hutan untuk bersembunyi.
Akupun seakan tidak percaya bisa berdiri di sini, dan heran bagaimana sopir hardtop itu tahu bahwa disinilah ada jalan tikus tempat para imigran gelap pulang ke tanah airnya. Di pinggir sungai ada satu rumah kecil, aku tidak tahu apakah ada penghuninya atau tidak. Rumah itu mungkin hanya sekedar tempat singgah. Salah satu teman rombonganku bertanya kepada seorang laki-laki yang kemungkinan ayah dari anak perempuan.
“Adakah penghuni rumah itu?” tanya Sakdiyah salah satu temanku yang juga akan pulang ke Indonesia.
“Oh, itu hanya tempat singgah apabila kapal tak kunjung tiba sampai malam kita bisa beristirahat dulu di rumah itu.” Jelasnya.
“Apakah anda sering pulang lewat jalan ini?” tanya Sakdiyah lebih lanjut.
“Yah, kadang dua atau tiga tahun sekali kami pulang.”
“Tidak pernah ketahuan?”
“Belum pernah, seandainya ketahuan, kalau kita bilang akan pulang biasanya dibiarkan.”
Aku mendengarkan saja percakapan Sakdiyah dan ayah anak perempuan itu yang sepertinya sudah terbiasa melewati jalan ini. Aku tidak habis pikir apa enaknya lewat jalan tikus seperti ini. Ada rasa was-was dalam hatiku bagaimana kalau sampai sore kapal tidak muncul, berarti harus menginap di rumah kayu itu. Di dalam rumah yang sepertinya gelap, entah ada kamar tempat tidur atau tidak. Hampir dua jam kita menunggu kapal yang tak kunjung tiba. Sedangkan mobil yang mengangkut rombonganku sudah pergi dari tadi. Sopir hanya menurunkan kami langsung pergi dan hanya berkata kapal akan datang sebentar lagi. Tunggu saja kapal sedang dalam perjalanan ke sini. Kami berdelapan hanya mengucapkan terima kasih kepada sopir yang telah mengantar kami sampai disini. Kami sudah membayar semua biaya agar sampai di Jawa, lewat seorang kenalan orang Kalimantan yang sering membantu para imigran gelap pulang ke Tanah Air. Rombonganku berdelapan akan pulang ke Jawa semua, empat orang ke Jawa Tengah dan empat orang ke Jawa Timur. Tidak berapa lama dari rimbunan pepohononan di ujung sungai muncul sebuah perahu kecil. Aku tidak percaya bahwa kita kan naik ke kapal kecil itu, aku membayangkan kapal yang kita tumpangi seperti kapal yang kita naiki dari Nunukan ke Tawau. Tapi kapal ini terlalu kecil buat kami yang berdelapan ditambah satu keluarga. Belum lagi barang-barang kami dan barang-barang keluarga itu.
Tukang perahu itu seakan menyakinkan kami, bahwa dia sudah biasa membawa beban lebih banyak dari ini. Barang-barang di masukkan dulu, baru kami masuk satu-persatu. Aku sempat cemas karena belum sampai semua naik perahu sempat oleng seakan mau terbalik, akhirnya perahu dibunyikan mungkin untuk menjaga keseimbangan. Ketika semua sudah terangkut, perahu perlahan-lahan berjalan menyusuri sungai. Aku kembali menitikkan air mata, lak-laki yang tadi menemaniku berdiri pinggir sungai ternyata dia duduk didepanku. Aku tidak terlalu memperhatikan ketika naik tadi. “Sekarang bukan waktunya menangis, berdoalah semoga kita selamat sampai rumah kita dan bertemu dengan keluarga kita.” Katanya kembali menghiburku. Aku menuruti perkataannya, sepanjang perjalanan menyusuri sungai aku berdoa. Kanan-kiri hutan banyak pohon-pohon yang masih besar. Dipinggir sungai sesekali terlihat ada ular menjalar dipinggir tebing. Beberapa bekantan kecil memanjat pohon, terjun ke sungai dan berenang ke pinggir. Mereka sepertinya sedang asyik bermain dengan teman-temannya. Kulihat induk bekantan sedang di atas pohon melihat anak-anaknya bermain loncat-loncatan dari atas pohon. Ada yang beberapa kali terjun ke sungai, berenang, naik lagi ke pohon dan terjun lagi. Pemandangan sepanjang perjalanan di sungai yang lama-kelamaan sepertinya dalam, dahan pohon dari pinggiran sungai bertautan antara tebing satu dengan tebing lainnya menambah suasana menjadi teduh, sinar matahari siang tidak kami rasakan. Kami tidak berani bercanda maupun berbicara terhanyut oleh suasana sungai yang membelah hutan. Hanya ada suara burung dan suara deru mesin kapal. Kami terus berdzikir dan berdoa memohon keselamatan. Hingga kami menjerit mengucap “astaghfirullah” bersama ketika di hutan bakau tiba-tiba perahu oleng dan hampir terbalik untungnya menabrak rimbunnya bakau sehingga tersangkut di tengah-tengah pohon bakau. Tidak ada daratan yang terlihat mata kami terhalang oleh rimbunnya hutan bakau, tidak tahu dimana ada daratan. Sepertinya kami sudah keluar dari alur sungai dan sudah masuk lautan. Aku sudah tidak tahu arah dimana timur dan selatan. Hanya air yang ada di sekitar hutan bakau. Diatas tampak langit putih seputih kapas, namun hatiku terasa kelabu.
Nyawa kami serasa sudah diujung tanduk, hanyalah keajaiban kami bisa selamat. Mungkin Tuhan mendengar doa kami sepanjang perjanan ini. Entahlah apabila tidak ada hutan bakau mungkin perahu sudah terbalik dan kita akan tenggelam. Mungkin nama tinggallah nama, tidak ada yang tahu kita semua tenggelam di lautan ini. Orang tua di rumah tahunya kita masih di negeri sebrang dan tak mau pulang. Tentang keadaanya juga tak ada ujung kabar beritanya. Hanya penantian dan penantian yang penuh harap karena tidak ada yang memberitahunya. Teman-teman yang masih di Batu Lima mungkin juga tahunya kita sudah pulang sudah bahagia bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman.
Sopir perahu itu kemudian menambatkan perahu pada sebuah pohon bakau dan mengambil ponsel. Dia menghubungi temannya agar memberikan bantuan, sang sopir sudah hafal daerah itu mungkin sering membawa penumpang gelap lewat jalan tikus, dia memberitahu posisinya. Kulihat anak perempuan itu sepertinya ketakutan dia didekap ayahnya, sepertinya sedang dihibur ayahnya. Sang ibu memeluk anak laki-lakinya yang sepanjang perjalanan tertidur dan terkejut ketika kita menjerit. Sejenak anak laki-laki itu menangis namun akhirnya diam ketika melihat kakaknya juga diam disamping ayahnya. Aku mencoba tegar, aku malu dengan anak kecil itu yang begitu tabah. Teman-temanku masih berdoa sebisanya dan memohon agar perahu pertolongan segera tiba. Meskipun sopir perahu mengatakan sebentar lagi perahu tiba, tetap saja rasa cemas tetap menyelimuti hati kami, bagaimana seandainya perahu pertolongan belum datang kami semua sudah terbalik. Beberapa anak laki-laki berpegangan pada kayu bakau, supaya perahu tidak oleng dan mencoba menstabilkannya.
Setelah hampir setengah jam kita dicekam ketakutan, perahu pertolonganpun datang. Perahunya lebih besar dari yang kita tumpangi, untunglah perahu itu cepat menemukan posisi kami, kalau sampai gelap kita tidak ditemukan bisa-bisa kita bermalam ditengah hutan bakau. Perut yang lapar sudah tidak kami hiraukan, kami makan baru satu kali pagi ketika masih di mess. Teman-temanku sudah sempat memasakkan untukku sarapan, sebagai perpisahan mereka masak ayam bumbu kari. Bumbu yang pertama kali menginjakkan tanah di Batu Lima sebagai bumbu yang asing di lidah kami. Namun lama kelamaan menjadi terbiasa dan lezat ketika dinikmati. Orang-orang Bugis yang pandai memasak itu mengajari bumbu-bumbu pelengkap supaya bisa dinikmati oleh lidah kita. Sayur singkong tumbuk yang lezat punya Bibi Rosma pasti akan aku rindukan. Oseng pakis dan jantung pisang masakan sahabatku Uus dari Madiun tidak akan pernah kudapati lagi. Kangen juga mengenang mereka, tapi aku harus pulang. Aku tidak tega melihat ayahku sakit dirumah dan menginginkanku cepat pulang. Orang tuaku pasti punya ikatan batin yang kuat terhadap anaknya. Bahwa aku tidak merasa nyaman kerja di pabrik yang mengharuskan pergi jam setengah tujuh pagi dan pulang setengah delapan malam bila masuk siang, begitu sebaliknya kalau masuk malam berangkat setengah tujuh malam dan pulang setengah delapan pagi. Tempatku bekerja mengharuskan bekerja seven-seven. Bila terlambat sedikit saja gaji akan kena potong, memang menyedihkan bekerja di negara asing yang jauh dari sanak saudara. Aku harus bekerja selama satu bulan penuh dan over time agar aku mendapatkan bonus. Bila ingat kerasnya pekerjaan dan menghadapi galaknya para tokek-tokek rasanya malas untuk kembali lagi kesana. Entahlah kenapa Mbak Parti yang asli Ngawi, Bibi Rosma asli Makasar dan Bibi Fatma yang asli toraja dan Mami Marta yang asli Singkawang sangat betah di sana. Mereka sudah sepuluh tahun lebih bekerja di kilang kayu itu. Mereka memang perempuan tipe-tipe pekerja keras yang memburu ringgit demi anak-anaknya di kampung halaman. Bahkan mereka belum pernah pulang kampung. Aku yang usianya pantas jadi anaknya sudah menyerah menghadapi kerja yang seperti itu, aku sudah tidak sanggup lagi. Setiap pagi kaki serasa sakit bila bangun tidur, kamarku di lantai dua dan kamar mandi di lantai satu. Serasa mau terjatuh apabila menuruni tangga, kakiku seperti kesemutan dan mati rasa. Menapaki turun tangga harus hati-hati kalau tidak bisa terjatuh terguling. Aku hanya bisa bertahan satu tahun bekerja di tempat itu. Akhirnya aku memutuskan pulang begitu mendapat surat yang mengabarkan tentang sakitnya ayahku.
Rasa lega tak terkira di hati kami semua, semua barang kita pindahkan ke kapal penolong. Kami akhirnya berlayar dengan tenang dengan kapal kedua ini. Kapalnya lebih besar dan lebih nyaman dibandingkan kapal yang pertama. Melintasi lautan perbatasan rasa cemas, was-was dan takut. Ketika melewati pos penjaga ada beberapa tantara yang menjaga pos perbatasan mereka menyuruh kapal berhenti. Kami dilihat satu-satu terus ditanya mau kemana. Kami menjawab mau pulang, sebenarnya kami semua sangat cemas apabila ditanya tentang paspor karena semua paspor masih ditahan di pabrik. Paspor belum bisa diberikan kalau kontrak kerja belum selesai. Nafas seakan berhenti, jantung terasa tak berdetak ketika tantara itu melongok ke dalam kapal dan menghitung jumlah orang. Namun untunglah tidak berapa lama setelah kami dipandangi satu-satu kami diperbolehkan jalan lagi. Rasanya lega sekali, sudah bisa melewati perbatasan dan sudah berlayar diperairan negara sendiri. Kami sudah mulai bisa bercakap-cakap, suasana mencekam seakan sirna. Sebelum sampai di perbatasan aku selalu diwarnai kecemasan setiap kali dari kejauhan nampak kapal, takut kalau itu kapal patroli polisi Malaysia. Seandainya ketahuan kita bisa dikejar dan bisa di sel semalaman di kantor polisi. Ngeri rasanya membayangkan kejadian itu. Meskipun kata teman-teman yang pernah di tangkap Polisi Malaysia dan di sel mereka mengatakan enak tidak harus kerja makanan disediakan. Pagi sudah disiapkan nasi goreng dan malam disediakan kopi. Menurutku hal itu tidak mungkin yang namanya penjara tetaplah tidak nyaman. Teman-temanku satu pabrik pernah di tangkap ketika jalan-jalan hanya membawa Id Card pengganti paspor. Kemudian mereka mengatakan bekerja di perusahaan di Batu Lima. Akhirnya mereka dilepas setelah ada perwakilan dari kantor perusahaan menjemput mereka.
Pada sore hari kapal akhirnya berlabuh disebuah panggung kayu yang dibangun menjorok kelautan dipinggiran laut, Disitu banyak sekali anak-anak muda yang sedang duduk-duduk dipanggung kayu sambil melihat sunset. Sepertinya mereka sedang merayau atau sekedar bersantai-santai di sore hari. Begitu kita berlabuh kita mengucap rasa syukur telah sampai di tanah Nunukan dengan selamat. Kami saling bersalaman, aku dan teman-teman perempuan berpelukan dengan tersenyum, seakan sudah terbebas dari maut.
Randi nama anak laki-laki yang kuketahui namanya selama perjalanan di perahu itu tersenyum ketika melihat aku tertawa.
“Kamu sudah tidak sedih lagi kan?” tanya Randi mencoba membantu membawakan tasku. Aku hanya tersenyum mendengar pertanyaannya karena memang aku tidak tahu apa yang harus aku jawab. Aku merasa hatiku sudah lebih baik, mungkin karena aku sudah berada di negeriku hatiku sudah berubah lebih mencintai tanah ini.
“Rin, ayo cepat kita sudah ditunggu!” Panggil Sakdiyah dari kejauhan. Tanpa aku sadari ternyata teman-temanku sudah beranjak jauh dari tempatku. Kulihat tadi mereka masih asyik duduk-duduk dan sekedar merebahkan diri di panggung pinggiran pantai ini. Aku dan Randi langsung berjalan menjauhi pinggiran pantai menyusul mereka.
“Namamu Rini kan?”
“Dari mana kamu tahu?”
“Kita kan satu shift.”
“Kamu mau pulang, kemana?”
“Aku akan ke Sidoarjo, aku tidak akan pulang. Aku akan mencari kerja disana.”
“Memang rumahmu mana?”
“Ngawi.”
Aku tidak bertanya lebih lanjut, aku pikir itu bukan urusanku. Meskipun ada rasa heran di hatiku tapi aku memakluminya. Mungkin dia malu pulang kampung karena dia tidak berhasil mengadu nasib di negeri sebrang.
Kami dijemput oleh orang dan diantar ke sebuah rumah singgah. Rumah itu lumayan besar dan bersih untuk beristirahat, kami kemudian diajak ke sebuah rumah bagus untuk makan. Rumah itu ternyata milik seorang nakhoda kapal yang juga pemilik rumah singgah. Kami semua dipersilakan makan, makannya menurut kami lumayan enak karena ada beberapa macam lauk dan sayur. Nakodha itu mengatakan kalau Kapal yang ke Jawa baru tiba satu hari lagi maka kita harus menginap dua malam di Nunukan. Beliau juga mengatakan sudah sering membantu orang yang akan pulang Sulawesi, Kalimantan atau Jawa jadi tidak usah sungkan, apabila butuh bantuan tinggal bilang saja. Untuk pembelian tiket nanti akan dibantu, kita tinggal datang saja ke pelabuhan Nunukan. Kami makan ternyata tidak ditarik, aku sudah membayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar penginapan dan makan di Nunukan ini. Ternyata semua sudah di urus teman yang membantu pelarian kami. Kami membayar sejumlah uang sudah diuruskan semua sampai pembelian tiket ke tanah Jawa. Aku dikenalkan dengan Bang Abas oleh seorang teman ketika aku memutuskan akan pulang. Dia ternyata tidak minta tarif lebih dia menghitungkan biaya transport dari Batu Lima sampai ke naik kapal ke tanah Jawa. Sungguh aku ucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah dengan rela membantu para imigran yang ingin pulang lewat pintu belakang dikarenakan terhalang oleh paspor yang tidak bisa diambil.
Aku dan teman-temanku ternyata harus menginap dua malam di rumah singgah. Karena kapal yang ke Jawa baru akan datang keesokan harinya. Malam kedua di rumah singgah aku sudah tidak melihat Randi, entah dia pergi kemana. Pagi harinya aku tanya sama Sakdiyah.
“Eh, kamu tahu tidak anak yang membantu membawakan tasku kemarin?”
“Oh, Randi? Dia lagi mau buat paspor lagi disini katanya mau ke KL.”
“Apa? Tidak salah, kamu kata siapa?”
“Aku dengar rencana Randi dan Kliman ketika habis makan siang mereka berencana membuat paspor disini”
“Kenapa tidak di Surabaya saja buatnya sambil pulang kampung?”
“Dari sini mereka akan langsung ke KL. Mereka tidak jadi pulang kampung.”
“Mereka yakin, tidak akan tertipu.”
“Tidak tahu, yang aku tahu nakhoda kapal itu yang akan membantu pembuatannya.”
“Trus, kita pulang hanya berenam?”
Sakdiyah hanya mengangguk mendengar pertanyaanku sambil terus menata bajunya dalam tas. Aku menghela napas panjang tidak mengerti dengan pola pikir Randi. Katanya dia akan ke Sidoarjo mencari kerja disana, eh ini malah mau Kuala Lumpur. Mungkin dia berpikir ke Kuala Lumpur akan lebih mudah mencari pekerjaan. Entah rayuan dari mana yang mengubah pikirannya. Mungkin sebagai anak laki-laki dia suka berpetualang mumpung masih muda.
Akhirnya keinginan pulang bisa terkabulkan, memang jalan kadang tidak semulus yang kita harapkan tetap ada aral halangan di jalan. Tidak semua orang baik yang kita temui, kadang menemui orang yang bermaksud tidak baik terhadap kita. Kita sudah berprasangka buruk ternyata dia malah baik hati. Sudah menyangka dia baik ternyata dia menipu kita. Di tanah seberang kita menemukan orang-orang baik yang menolong kita, namun ketika di tanah Jawa yang serasa sudah sampai di rumah kita, ada saja orang yang berniat memalak. Sepertinya mereka tahu kalau kita berasal dari tanah sebrang dan membawa uang. Padahal pakaian kita saja hanya memakai kaos, celana jeans dan tas yang kita bawa juga cuma satu tas jinjing itupun tidak baru. Mereka pura-pura baik menawarkan angkutan ke terminal dengan harga hanya RP. 15.000 kami menawar karena terlalu mahal dia menyetujui ketika kita minta harga Rp. 10.000. Tetapi sungguh tidak diduga di tengah jalan dia menghentikan mobilnya disebuah agen bis dia menyuruh turun dari mobil kita disuruh naik bis jurusan Jakarta. Tentu saja kami menolak karena jurusan kami bukan ke Jakarta melainkan ke Semarang. Kami meminta diantar ke terminal sesuai perjanjian di awal. Kami dipaksa membayar uang perorang Rp.50.000 kalau tidak mau kami diancam akan dipanggilkan teman-temannya. Dengan terpaksa kami menyetujuinya dari pada nanti urusannya menjadi panjang. Akhirnya kami diantar ke terminal dan untungnya sore itu masih ada bis yang kearah Semarang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

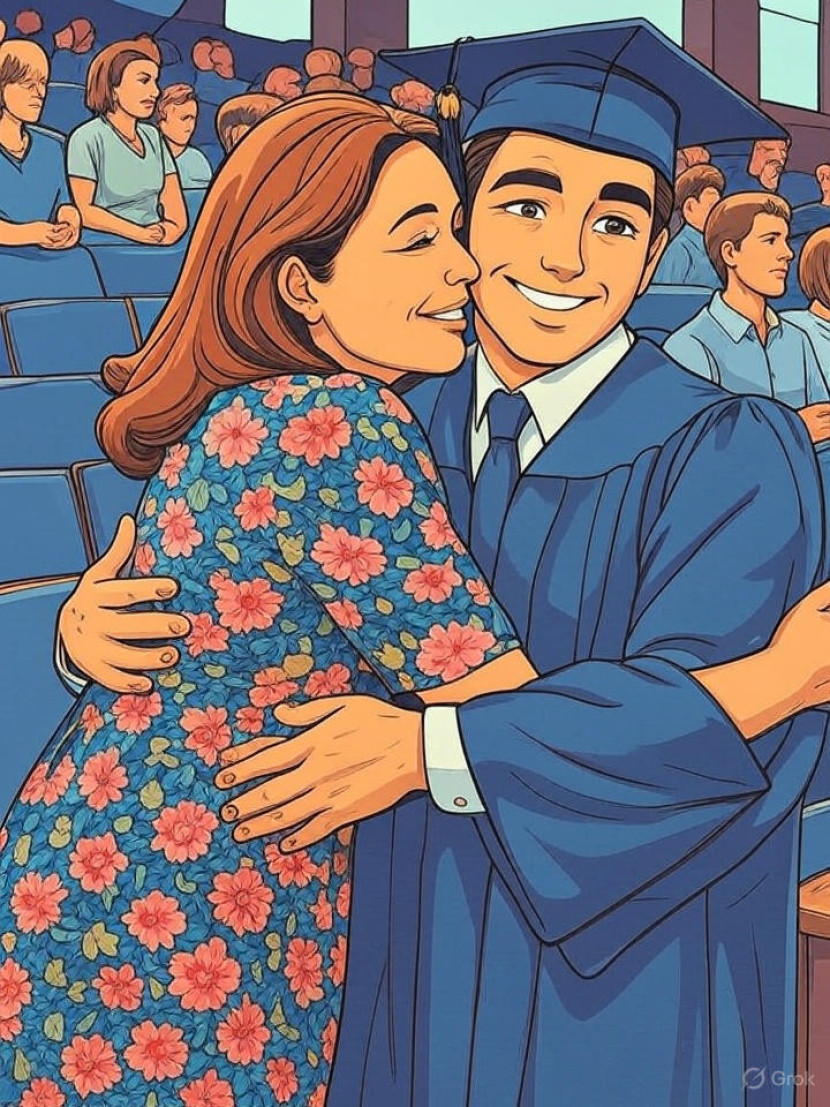
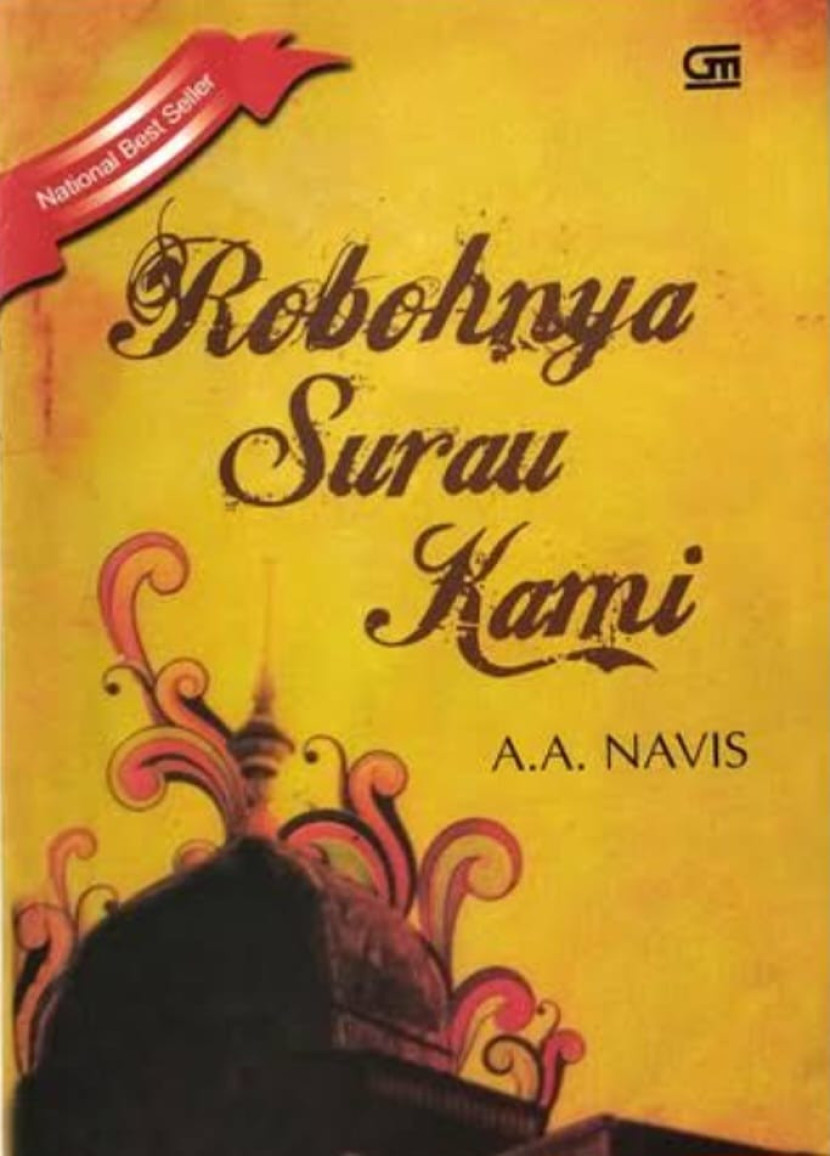









Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook