 Gilang Ramadhan
Gilang Ramadhan
Yang Penting Sehat, Supaya Kita Bisa Kembali Lagi Mengobati Nasib yang Sakit
Lomba | 2021-09-17 01:48:56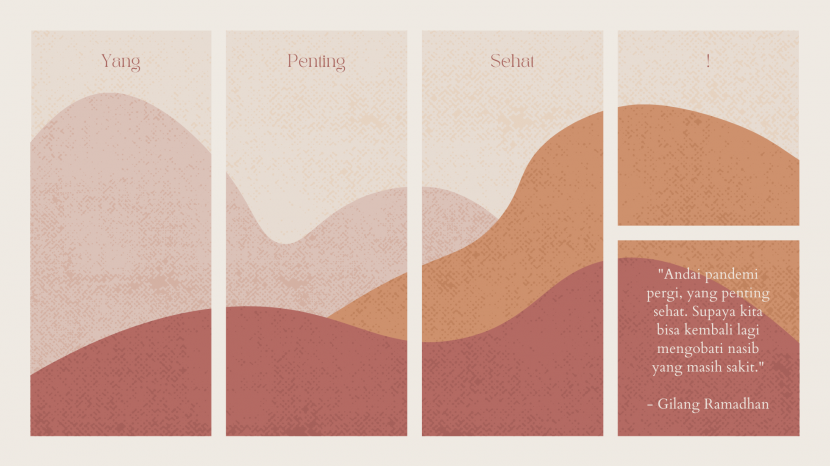
Judul tulisan ini merupakan jawaban dari seorang lelaki tua ketika saya mengajukan pertanyaan perihal apa yang akan ia lakukan seandainya pandemi pergi. Itu sebuah jawaban yang kelewat wajar, bahkan menurut saya yang paling masuk akal. Seperti yang kita semua tahu, pandemi membuat nasib sebagian besar orang semakin terpuruk. Sebelum munculnya pagebluk saja, nasib sudah sakit.
Sekarang, hampir dua tahun nasib diterjang badai virus. Tentu, nasib tambah terombang-ambing, kemualannya berlipat ganda dibarengi pula nyeri kepala, dan rasanya semakin sakit saja.
Dampak pandemi terhadap perekonomian rasanya tak perlu diukur-ukur lagi. Beberapa bulan setelah virus mulai menjalari Jakarta saja, banyak di antara kawan-kawan saya yang terpaksa dirumahkan. Mereka pada akhirnya dipecat juga, sialnya termasuk saya dan istri yang waktu itu sedang mengandung anak pertama.
Pada akhir tahun 2020 saja, berdasarkan data BPS ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Kata Menaker Ida, jumlah pengangguran naik menjadi 9,7 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 persen di Indonesia.
Memang, seluruh negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Tetapi melihat negara lain dengan kondisi yang sama malah membikin mumet kepala saja. Buat apa memikirkan nasib orang lain di seluruh negara di dunia, sementara kepada siapapun penderitaan menimpa hari ini, rasanya selalu sama. Itu ukuran yang paling masuk akal.
Sekarang ini sederhana saja, semua orang butuh uang. Salah seorang kawan saya di grup Pengacara (baca: Pengangguran Banyak Acara) Miskin Kota, seringkali membagikan kutipan dari Albert Camus ini sebagai siasat halus meminjam uang, âSalah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang.â
Saya rasa, itulah kenyataan hari ini. Meski masih bisa dihadapi dengan ketenangan yang agak ganjil. Jangan tanya betapa kita harus bersyukur menikmati hari-hari buruk sepanjang pandemi karena paru-paru masih bekerja secara normal. Tetangga saya, lelaki tua yang jawabannya secara khusus saya jadikan judul tulisan ini, bahkan masih dapat tersenyum lebar di bawah pancaran sinar matahari pagi yang menghangatkan tubuh kerempengnya.
Meski jauh di kedalaman matanya, bayang-bayang hidupnya menari-nari di tengah kegelapan diiringi suara sumbang istrinya yang menyanyikan lagu tentang nasib pahit keluarganya.
Suatu hari saya pernah memperhatikan tetangga saya itu sedang sibuk membuat gerobak. Ukurannya tidak begitu besar, tidak juga kecil. Disebut gerobak berukuran sedang pun tampak tidak memenuhi standar. Yang penting baginya adalah gerobak itu cukup memuat sebuah akuarium buah beserta bumbu rujaknya. Ia membuat gerobak itu selama tiga hari.
Ia orang yang berprinsip bahwa pengangguran bukan berarti tunakarya. Jadi, di masa paceklik di tengah pagebluk ini, ia memutuskan untuk berdagang rujak. Beberapa hari kemudian, setelah ia mendapatkan modal dan membeli buah-buahan, ia pun menjajakan dagangannya. Rujak segar, sepuluh ribu rupiah harganya. Kebetulan waktu itu sedang ramai-ramainya vaksin di lapangan desa.
Saya ingat malam hari sebelum esok harinya ia berjualan. Istrinya sibuk mengulek sambal rujak. Anak perempuannya memotong beberapa bagian buah-buahan dan mengemasnya. Ia bersama saya minum kopi sambil mengobrol di halaman rumahnya. Keesokannya, tepatnya siang hari, ia pergi jihad mendorong gerobak nasibnya. Namun, tiga atau empat hari kemudian, ia memutuskan untuk pensiun dini berjualan.
Ia bilang, tak ada untungnya sama sekali.
Ia bukan orang yang gampang menyerah. Setelah mengetahui kabar bahwa sekolah di wilayah kami mulai boleh melakukan kegiatan belajar tatap muka, ia mulai lagi berjualan. Tapi bukan rujak, melainkan es. Ia pun memutuskan untuk memenuhi dahaga anak-anak harapan bangsa di musim panas ini dengan segelas es aneka rasa.
Beberapa kali ia berjualan, meski kelihatan lesu saat melihatnya kembali pulang ke rumah, ia tahu bahwa penghasilannya tak sebesar uang boleh mengutip bansos secara nasional. Tetapi, minimal ampuh menyumbat sebelah telinganya dari suara sumbang istrinya.
Berhari-hari kemudian, kami ngobrol dan saling melontarkan kelakar gelap soal kehidupan. Di tengah percakapan, saya iseng bertanya, apa yang Aki lakukan seandainya pandemi pergi? Ia menjawabnya dengan enteng, âYang penting sehat, supaya kita bisa kembali lagi mengobati nasib yang masih sakit.â
Saya tak menduganya kalau ia bakal menjawabnya seperti itu. Saya tahu, sehat menurut orang-orang seperti dirinya adalah mampu bergerak mencari uang meskipun tubuhnya sebetulnya sedang sakit. Hanya saja ia menyembunyikan kesakitannya.
Semangatnya mengingatkan saya akan sebuah wejangan klasik dari Camus ini, âMarilah kita mengetahui tujuan kita, berpegang teguh pada pikiran, bahkan jika kekerasan menunjukkan wajah yang bijaksana atau menenangkan untuk merayu kita. Hal pertama adalah jangan putus asa. Jangan terlalu banyak mendengarkan mereka yang menyatakan bahwa dunia sudah kiamat.â
Tetangga saya sadar akan penderitaan-penderitaannya. Ia tahu bedanya tragedi dan putus asa. Ia menjadikan tragedi sebagai pecut bagi penderitaan. Bahkan begitu ia mengetahui bahwa Presiden Jokowi menyatakan COVID-19 tidak akan hilang, dan meminta kita agar menyesuaikan diri hidup bersama dengan COVID-19, dengan enteng lelaki tua ini menanggapi sambil menyesap kopi, âItu bisa diatur. Yang sulit itu menyesuaikan diri tanpa uang.â
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.











