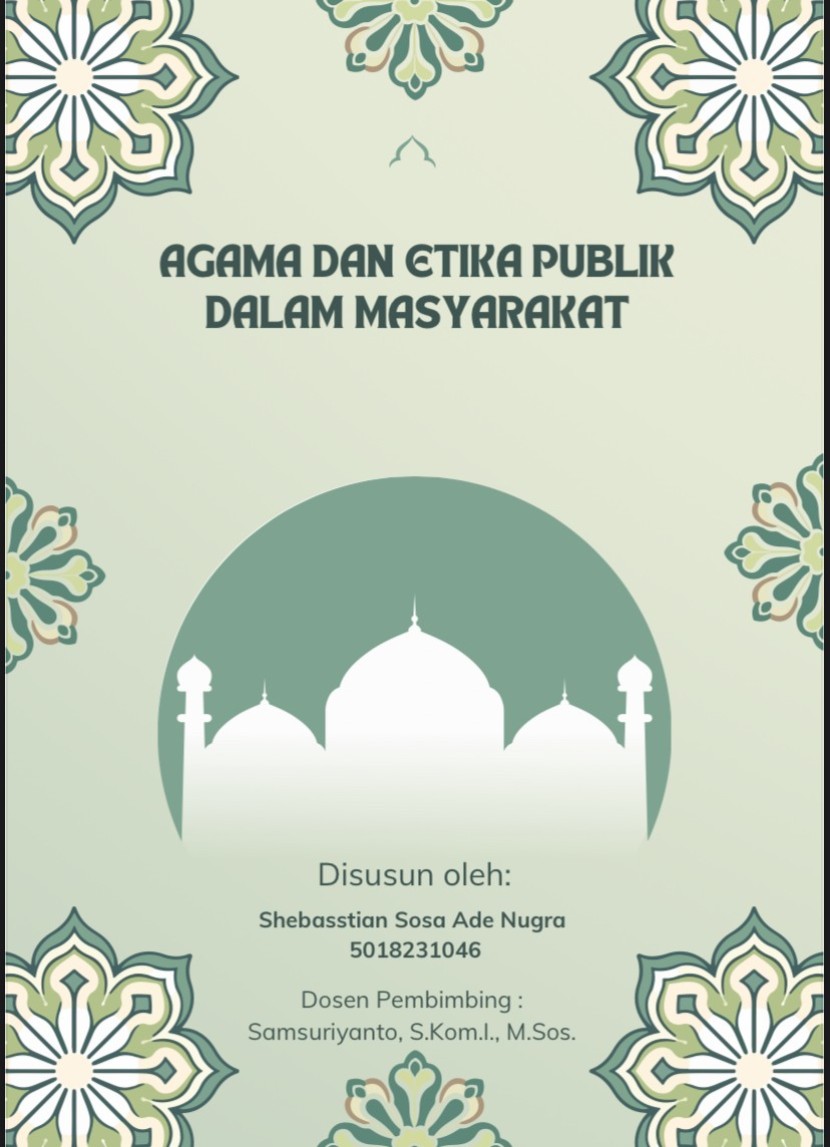Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto
Mural, Moral dan Semiotika
Politik | 2021-08-25 16:41:39
...Kalau rakyat bersembunyi
Dan berbisik-bisik
Ketika membicarakan masalahnya sendiri
Penguasa harus waspada dan belajar mendengar...
Bait puisi Peringatan dari Wiji Thukul, di tahun 1986 itu, masih relevan dalam kondisi kebaruan sosial politik kita saat ini.
Mural kini menjelma seolah menjadi pokok masalah baru. Dinding tembok pagar menjadi ruang ekspresi publik untuk menyampaikan pendapat.
Ruang publik yang kian terbuka, rupanya menjadi sebuah persoalan. Persis sebagaimana larik puisi di atas, sudah semestinya pemangku kuasa membangun sensitivitas untuk mampu merasakan masalah publik -sense of crisis.
Titik tekan masalah bisa semakin membesar bila pembungkaman terjadi, alih-alih menciptakan ruang dialog serta menangkap makna tersembunyi dibalik mural yang ditampilkan.
Bila pemberangusan dan perburuan justru dilakukan, atas nama ketertiban dan keteraturan, maka persepsi publik bisa berbalik. Terkonstruksi kuasa yang anti kritik.
Sebagai bentuk seni jalanan -street art, mural mengambil wilayah berbeda dari graffiti maupun vandalisme. Konsep mural mengkombinasikan seni dengan abstraksi pendapat publik.
Di posisi yang berbeda, mural menjadi indikasi tindak laku moral sosial. Pandemi memang menghadirkan situasi nestapa, baik di bidang ekonomi ataupun masalah kesehatan publik.
Keselarasan arah gerak kebijakan sebagai domain kekuasaan, harus dibarengi dengan partisipasi publik. Untuk itu perlu dibentuk rasa saling percaya.
Bukan masanya lagi, ada kesenjangan antara keputusan dan kebijakan di tingkat atas dengan implementasi lapangan. Kekuasaan harus masuk wilayah substansi, bukan sekedar kulit luar.
Produk mural menjadi sebuah karya sosial, dibentuk dari pemahaman publik atas situasi yang melingkupinya. Dalam ilmu komunikasi mural dapat didekati dengan kajian semiotika.
Menggunakan perspektif de Saussure, semiotika adalah kaidah pemaknaan tanda dan simbol beserta tafsirnya.
Mural bukan hanya penanda dalam konsep citra bunyi, sekaligus petanda sebagai pemahaman, bahwa ada kegelisahan publik yang mengemuka.
Manakala ruang publik menyempit, suara-suara publik diredam, pemikiran berbeda di sensor, maka hanya tersisa puja-puji yang mengemuka.
Padahal kritik serta umpan balik -feedback dalam ilmu komunikasi dimaknai sebagai cara menghidupkan dinamika dan dialektika, agar kekuasaan tidak terjatuh pada format kebenaran tunggal -monolitik.
Di alam demokrasi, kita berharap untuk menghirup udara kebebasan, merasakan keadilan, serta menghidupkan partisipasi publik sebagai langkah emansipatoris menjadi tulang pokoknya.
Kita justru harus merawat terjaganya ruang publik yang setara dalam dialog, sebagaimana gambaran Habermas, mengenai tindakan komunikatif yang mengurai kemacetan dialog.
Di dalamnya, sebut Habermas, ruang publik mengharuskan sifat yang bebas, terbuka, transparan dan otonom.
Mural itu telah bertransformasi menjadi sebuah ruang publik baru, sebagai sarana kontemplatif untuk melakukan koreksi bersama. Jangan direpresi, justru mendengarlah.
Di bait lain dalam puisi Peringatan, Wiji Thukul juga mengingatkan:
...Bila rakyat berani mengeluh
Itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa
Tidak boleh dibantah
Kebenaran pasti terancam..
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.