 Farras Muthiah
Farras Muthiah
Masa Depan Anak Perempuan Bukan di Tangan Laki-Laki!
Eduaksi | 2021-06-07 00:13:13
Keluar mulut harimau, masuk mulut buayaâsebuah peribahasa yang sempurna untuk menggambarkan nasib anak perempuan yang dinikahkan ketika masih belia.
Problematika pernikahan anak di Indonesia akhirnya kembali menjadi topik pembahasan selepas sinetron yang tayang di salah satu televisi nasional dianggap telah mengglorifikasi pernikahan anak. Pasalnya, serial televisi tersebut mendapuk perempuan berusia lima belas tahun untuk memainkan peran sebagai istri ketiga dari laki-laki berumur 39 tahun. Selain karena adegan-adegannya yang dinilai kurang pantas, masalah utama dari sinetron ini adalah penulisnya yang seakan-akan ingin mengajak penonton untuk terbawa suasana dan mewajarkan hubungan pernikahan di bawa umur tersebut.
Mulai dari tokoh-tokoh di industri perfilman seperti Ernest Prakasa dan Zaskia Adya Mecca hingga Kak Seto turut mengungkapkan kekhawatirannya tentang bahaya dari penayangan sinetron tersebut. Banyaknya tokoh publik dan masyarakat yang kini menaruh perhatian terhadap masalah pernikahan anak memang merupakan hal baik, namun kenyataannya, problematika ini sudah terjadi jauh sebelum sinetron tersebut viral.
Nyatanya, mengubah pemikiran masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di perdesaan, adalah sebuah pertarungan sepi yang sudah dimulai sejak lama. Mulai dari alasan keagamaan, budaya, hingga ekonomi, pernikahan dianggap bisa menjadi penyelamat hidup anak, terlebih bagi anak perempuan. Buktinya, dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi kasus pernikahan anak hanya menurun sebanyak 3,5 persen. Sangat lambat. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) saja, ada 1,2 juta anak perempuan yang mengalami pernikahan pertamanya di usia kurang dari 18 tahun. Angka tersebut setara dengan satu dari sembilan perempuan di Indonesia.
Meski anak laki-laki juga mengalami pernikahan anak, fakta bahwa perempuan lebih rentan terhadap masalah ini adalah rahasia umum. Orang tua seringkali berpikiran bahwa laki-laki yang sudah berpenghasilan bisa menjamin hidup putrinya, meski putrinya bukan sebagai istri pertama. Toh perempuan akan berakhir di dapur dan hidup perempuan bisa dijamin laki-lakiâadalah pemikiran umum yang dimiliki oleh mereka yang rela menukar pendidikan putrinya dengan âjaminanâ yang sebenarnya fana. Mengapa fana? Berikut adalah alasannya:
Kehamilan di Bawah Dua Puluh Tahun Lebih Berisiko Dua Kali Lipat
Menurut Child Marriage Report yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), perempuan yang hamil di umur lima belas hingga sembilan belas tahun memiliki risiko komplikasi kehamilan dan persalinan hingga dua kali lipat dari perempuan yang hamil di atas umur dua puluh tahun.
Sementara itu, 63,08 persen perempuan yang menikah sebelum umur delapan belas tahun telah mengalami kehamilan pertamanya sebelum usia delapan belas tahun. Artinya, dua dari tiga perempuan yang melakukan pernikahan anak sudah hamil ketika ia masih berada pada batas usia anak menurut undang-undang perlindungan anak. Fakta ini patut menjadi perhatian mengingat tubuh anak yang belum berkembang sempurna tentu saja belum siap jika harus menanggung satu lagi kehidupan di dalam tubuhnya.
Tubuh perempuan yang masih dalam pertumbuhan bisa menimbulkan kondisi cephalopelvic disproportion (CPD), yaitu keadaan kepala bayi yang lebih besar dari panggul ibu. Kondisi ini menyebabkan tengkorak bayi tertekan sehingga dapat menyebabkan pendarahan otak yang mengancam nyawa bayi. Sementara itu, ibu juga berisiko mengalami pendarahan hebat dan cedera pada rahim. Selain CPD, kehamilan di usia anak membuat ibu dan bayi lebih berisiko mengalami kekurangan gizi dan komplikasi kehamilan lainnya. Salah satu komplikasi paling berisiko adalah preeklampsia. Pasalnya, jika tidak ditangani dengan baik, preeklampsia dapat berkembang menjadi eklampsia dengan cepat dan mengancam nyawa ibu dan bayi. Terakhir, ada baby blues atau depresi pasca melahirkan yang dampaknya lebih sering dirasakan oleh ibu berusia di bawah dua puluh tahun. Kondisi ini biasanya disebabkan karena perempuan di umur tersebut terkejut dan kewalahan dengan tanggung jawab baru yang harus dipikulnya.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Meski perempuan seharusnya memiliki kedudukan yang setara dalam rumah tangga, konsep ini masih banyak tidak diketahui dan dianggap tidak penting bahkan bagi rumah tangga yang terbentuk di atas usia dua puluh tahun, apalagi bagi anak-anak. Ego yang dimiliki anak berusia di bawah dua puluh tahun tentu masih labil dan naik turun, sehingga mudah saja bagi pihak yang lebih kuat (dalam hal ini secara fisik, yaitu tentu saja laki-laki) untuk bisa bersikap seenaknya, termasuk melakukan kekerasan.
Apalagi jika perempuan seutuhnya bergantung secara finansial kepada pihak laki-laki. Kondisi ini biasanya dijadikan validasi oleh pihak laki-laki bahwa mereka adalah pihak yang berkuasa dan bisa bertindak seenaknya. Oleh karena itu, pernikahan tidak akan menyelesaikan ketidakberdayaan, melainkan hanya menyebabkan penderitaan yang berbedaâyang bahkan bisa jadi lebih sakit dan berbahaya.
. . .
Untuk mencegah lebih banyak lagi anak perempuan yang harus menghadapi risiko dari pernikahan anak, pemerintah sudah mengubah batas usia pernikahan yang semula enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, pencegahan tersebut seakan sia-sia. Undang-undang yang sudah dianggap seperti angin lalu dan situasi tidak terduga yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 membuat penurunan angka pernikahan anak menjadi seperti sebuah keniscayaan. Masalah ini terlihat dari data yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu enam bulan (Januari hingga Juni 2020), ada 34.000 kasus pengajuan dispensasi kepada pengadilan agama dengan perihal pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang. Parahnya lagi, 97 persen dari kasus tersebut dikabulkan!
Meski pertarungan untuk menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup panjang, pertarungan ini tidak harus sepi. Mari kita sama-sama bertarung meski dengan cara sederhana. Kita semua bisa mulai dengan menggunakan media sosial kita untuk terus menyebarkan kesadaran dan mengedukasi orang-orang disekitar kita tentang bahaya dari pernikahan anak. Jangan jadikan pertarungan ini menjadi pertarungan sepi lagi.
Sumber:
Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. 2020. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1-16.
Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. Jurnal Bidan âMidwife Journalâ Volume, 1(1), 46-53.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.








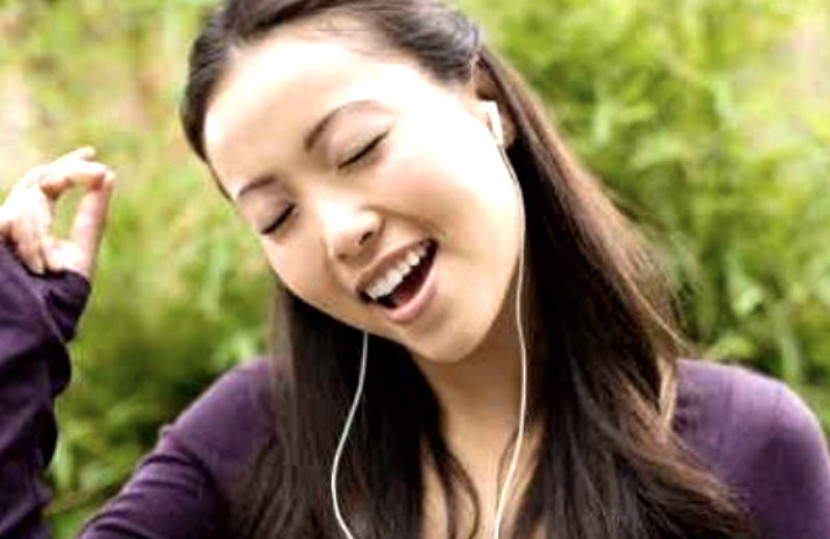


Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook