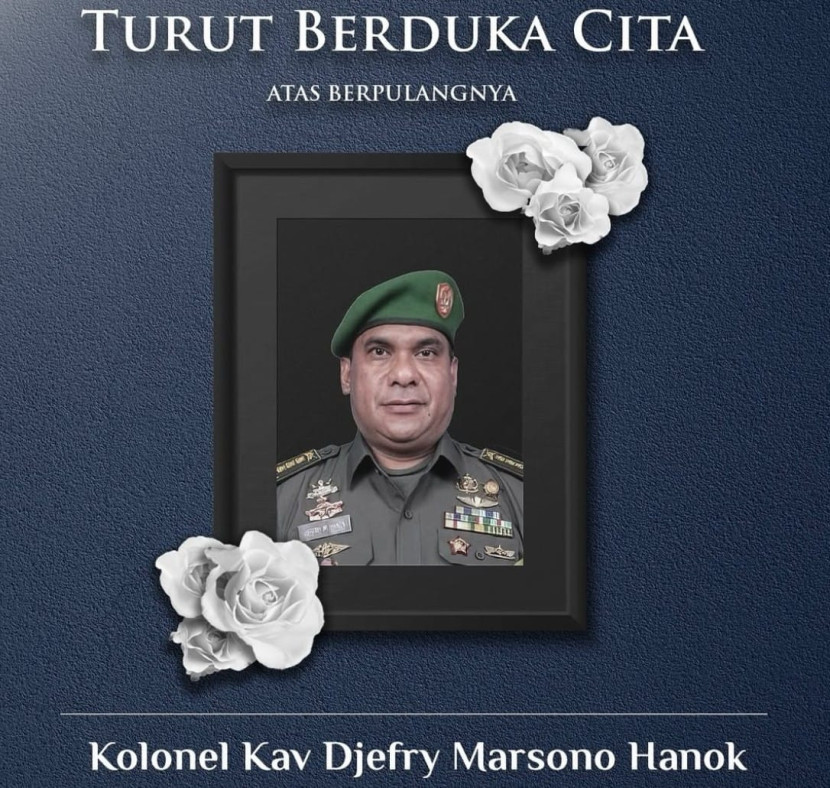Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto
Kultus dan Reorientasi Kekuasaan
Curhat | 2022-04-12 15:06:55
Hitung ulang kekuasaan! Aksi unjuk rasa mahasiswa kemarin, menjadi satu sinyal penting untuk dapat dimaknai secara utuh oleh para penguasa. Fokus isu yang dibawa, mulai dari soal politik masa jabatan, merambah hingga urusan hajat keseharian publik.
Apakah aspirasi ini ditunggangi? Mungkinkah suara yang disampaikan merupakan elaborasi pemikiran kritis mahasiswa? Kita bisa berasumsi dan memakai perspektif apapun mengenai demonstrasi itu, satu yang pasti ekspresi tidak bisa disumbat.
Bagi para pengasong ide kekuasaan, usulan untuk melakukan penundaan, perpanjangan, atau bahkan memberi ruang tambahan waktu berkuasa menjadi tiga periode, seharusnya diakomodir sebagai sebuah bentuk aspirasi (?)
Argumentasi tersebut jelas keliru, bahkan keluar konteks. Kebebasan berpendapat dalam menyampaikan ide dan gagasan jelas dilindungi konstitusi, sementara perihal utak-utik masa kekuasaan dengan tegas dibatasi juga dalam konstitusi.
Dengan begitu, ide dan ekspresi berpendapat tentang durasi masa hidup berkuasa, menjadi sebuah tindakan bersyarat yang diperbolehkan, bila aturan terkaitnya mengalami perubahan terlebih dahulu, melalui amandemen konstitusi.
Pendapat itu sepintas tampak setengah benar -half truth, tetapi ahistorik. Mengapa begitu? Berdasarkan sejarah lintasan kekuasaan negeri ini di masa lalu, menyadarkan kita bila kursi kuasa cenderung untuk digenggam berlama-lama, selama mungkin.
Konsekuensi dari kekuasaan yang terkonsolidasi untuk waktu yang lama, dan tersentral pada satu figure adalah perubahannya menjadi bercorak otoriter, mewujud sebagaimana Thomas Hobbes menyebut Leviathan -monster beringas.
Kekuasaan adalah godaan. Saat ada digenggaman, kekuasaan memiliki kemampuan untuk memerintah, lebih dari sekedar membujuk, hingga memaksa. Hegemoni, mengutip Gramsci, adalah kerja kekuasaan dalam format terselubung, tidak frontal.
Jelujur tangan kuasa hadir dalam berbagai bentuk -omnipresent, dan terdispersi ke dalam banyak lembaga sosial yang juga dikontrol oleh kekuasaan, seperti formulasi Michael Foucault. Sulit dihindarkan, kekuasaan berpotensi membunuh demokrasi.
Dalam rumus kekuasaan, anything goes -apa saja boleh. Namun kekuasaan kerap lupa, hal utama dalam demokrasi dimana esensi dasarnya membatasi kekuasaan, harus terjadinya sirkulasi, menghindari konsentrasi kuasa secara mutlak.
Meski terdengar menyakitkan, bagi para pendukung tokoh maupun figur, tetapi realitas ini harus menjadi sandaran kesadaran. Bila tidak, maka kita secara tidak sadar telah membangun konstruksi kultus individu. Pemujaan berlebihan akan kekuasaan.
Kultus kekuasaan cum penguasa, membuat kita “mengabaikan gajah di pelupuk mata”, tanpa dibatasi maka kekuasaan cenderung korup, ungkap Lord Acton. Para pemuja menciptakan pemimpin kharismatik, tidak pernah salah, tanpa cela dan terus dibela.
Situasi ini rentan untuk diambil alih dan dibajak untuk kepentingan sepihak, karena itu upaya membangun kejernihan berpikir kritis membawa kita untuk memahami aspirasi mahasiswa yang melihat bencana di ujung cerita tentang ide masa kekuasaan.
Catatan menarik disampaikan R William Liddle (Kompas, 4/4) tentang Sesepuh Bangsa berisi wawancaranya dengan BJ Habibie, tentang tradisi peralihan kekuasaan yang tidak tragis, mengandaikan kebesaran pemimpin untuk rela berpisah dari kursi kuasa, tanpa kehendak untuk mempertahankan privilege tersebut.
Lebih jauh lagi, Haryatmoko (Kompas, 5/4) melalui Fatamorgana Kekuasaan, menyebut narasi “dikehendaki rakyat” seolah terlihat demokratis, bisa jadi merupakan bentuk rekayasa, karena kedaulatan publik telah disita para elit kepentingan oligark.
Skema oligarki, sebut Jeffrey Winters, dimaknai sebagai wealth defense mechanism, dimana segelintir pihak mempertahankan kekayaan secara terbatas, politik adalah manifestasi sekaligus representasi dari jumlah kekuatan kapital yang dimiliki.
Celakanya, oligarki kemudian menggunakan instrumen demokrasi untuk terpilih melalui jalur elektoral, menjadi “wakil publik”. Mata rantai yang seolah tidak putus ini hanya akan mengalami perubahan, ketika publik tercerahkan.
Disitulah keberadaan elemen mahasiswa memiliki peran untuk mendorong suara yang terbungkam, kelompok marjinal dalam pengambilan kebijakan.
Tidak sendirian, keberadaan intelektual, sesuai Julien Benda, juga memiliki pengaruh, mereka yang mengabdi pada nilai keadilan, moralitas dan rasio, serta terlepas dari keuntungan praktis.
Para intelektual, Edward Shils menyebut, memiliki kontribusi untuk memainkan peran politik dan mempengaruhi perubahan sosial, sebagai agent of change. Termasuk diantaranya agamawan, seniman, tokoh budayawan, hingga jurnalis dan media.
Kekuatan ini, sebut Olle Tornquist, harus memadukan gerak langkah bersama serta berkolaborasi dengan masyarakat sipil lainnya dan publik itu sendiri, tidak terpisah.
Mencermati Wiranto (Kompas, 8/4) dalam Bersitegang Mempersoalkan Peristiwa yang Tak Mungkin Terjadi, menyebut bahwa hingar-bingar publik tentang masa jabatan adalah sia-sia waktu dan tenaga karena sesungguhnya tidak pernah ada dan terjadi.
Politik sesungguhnya merupakan dunia tentang segala hal yang mungkin -the art of the possible, hari ini bisa jadi berbeda dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, segalanya serba mungkin dalam kerangka pertemuan kepentingan kekuasaan.
Dramaturgi kekuasaan, seperti Erving Goffman, menempatkan panggung depan berbeda dari panggung belakang. Apa yang tampil ke publik belum tentu yang sebenarnya terjadi, karena kita tidak pernah bisa menebak di belakang layar.
Karena itu, gerakan mahasiswa menjadi sebuah pertanda yang harus diperhatikan, sebagai upaya koreksi atas penyimpangan. Kekuasaan harus direorientasi bagi kepentingan khalayak publik secara luas, sebagai pemilik kedaulatan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.