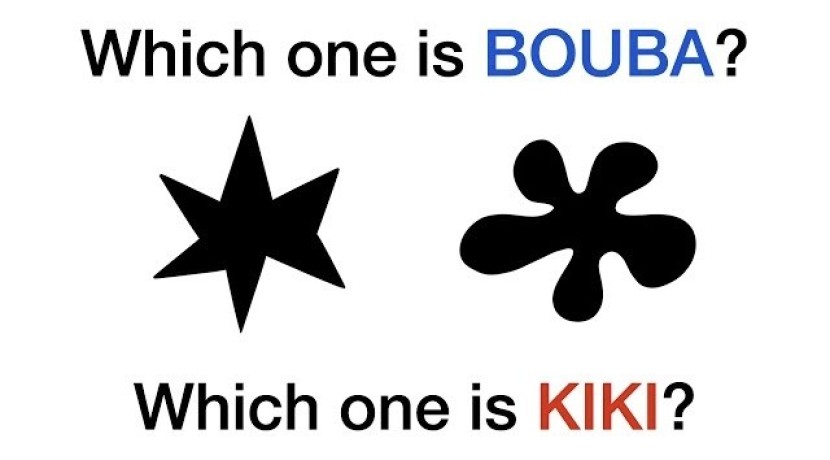Muhammad Nazriel Elyan Rangga
Muhammad Nazriel Elyan Rangga
Seni Bahasa di Ujung Stetoskop
Hospitality | 2025-12-11 10:49:52
Jika kita bertanya kepada masyarakat awam tentang apa yang membuat seorang dokter disebut "hebat", jawaban yang muncul biasanya berkisar pada kecerdasan akademis: diagnosa yang jitu, lulusan universitas ternama, atau kemampuan memberikan resep obat yang manjur. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Sebagai mahasiswa kedokteran tahun pertama, hari-hari saya pun dipenuhi dengan buku tebal anatomi, histologi, dan hafalan patofisiologi yang seolah tiada habisnya. Kami dididik untuk menjadi saintis yang presisi.
Namun, sebuah pengamatan lapangan yang saya lakukan baru-baru ini di sebuah Rumah Sakit di Sidoarjo mengubah perspektif saya. Saya menyadari ada satu "kurikulum" tak tertulis yang tidak diajarkan secara eksplisit di buku teks, namun menjadi penentu utama keberhasilan pengobatan: seni komunikasi.
Siang itu, suasana rumah sakit cukup padat. Aroma khas antiseptik bercampur dengan keriuhan langkah kaki perawat dan pasien yang lalu-lalang. Di tengah kesibukan itu, saya duduk di sudut ruang praktik, mengamati seorang dokter senior yang sedang bertugas.
Tugas saya sederhana: mengamati bagaimana beliau berkomunikasi. Awalnya, saya pikir ini akan membosankan. "Paling-paling hanya tanya sakit apa, lalu tulis resep," pikir saya. Tapi ternyata saya salah besar.
Seorang pasien muda, laki-laki usia 20-an, masuk dengan keluhan demam dan nyeri sendi. Sang dokter menyambutnya dengan sigap. Tubuhnya tegak, tatapan matanya fokus namun bersahabat. Beliau menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, lugas, dan logis.
"Sudah berapa hari demamnya, Mas? Apakah ada nyeri di bagian belakang mata?" tanyanya dengan tempo yang cukup cepat, menyesuaikan dengan ritme anak muda yang dinamis.
Dialog berjalan efektif, seperti diskusi antar-mitra. Pasien muda itu tampak puas dengan penjelasan medis yang rasional dan to-the-point.
Suasana berubah drastis ketika pasien berikutnya masuk. Seorang nenek, mungkin berusia 70an tahun, dituntun masuk oleh anaknya. Wajahnya tampak tegang, matanya menyiratkan kebingungan melihat alat-alat medis di sekelilingnya.
Di sinilah momen magis itu terjadi. Sang dokter yang tadi tampak tegas dan cepat, tiba-tiba berubah. Beliau menurunkan nada bicaranya menjadi jauh lebih lembut. Postur tubuhnya yang tadi tegak, kini sedikit membungkuk dan condong ke depan—sebuah gestur non-verbal yang menunjukkan keinginan untuk mendengar lebih dekat.
Dan yang paling mengejutkan, bahasa persatuan (Bahasa Indonesia) ditanggalkan. Beliau beralih menggunakan Basa Jowo Krama Inggil (Bahasa Jawa tingkat paling halus).
"Pripun Mbah, napa ingkang dipun raosaken sakit sakmenika?" (Bagaimana Mbah, apa yang dirasakan sakit saat ini?) tanyanya halus.
Efeknya instan dan luar biasa. Saya melihat bahu sang nenek yang tadinya kaku perlahan turun. Wajah cemasnya berganti menjadi senyum tipis. Beliau mulai bercerita, bukan hanya soal sakit fisiknya, tapi juga kecemasannya, dengan bahasa Jawa yang tak kalah fasih.
"Nggih niki Dok, boyok kula rasane kados ditusuk-tusuk..." (Iya ini Dok, pinggang saya rasanya seperti ditusuk-tusuk).
Apa yang dilakukan dokter tersebut dalam dunia medis dikenal sebagai code-switching atau alih kode. Namun dalam konteks pelayanan kesehatan, ini bukan sekadar sopan santun atau basa-basi budaya. Ini adalah strategi klinis yang krusial.
Dalam pemeriksaan medis, ada tahap yang disebut anamnesis (wawancara medis). Tahap ini menyumbang sekitar 70-80% data untuk penegakan diagnosis. Jika pasien tidak nyaman, takut, atau tidak paham bahasa dokternya, mereka cenderung menutup diri atau memberikan jawaban pendek-pendek. Akibatnya? Diagnosis bisa meleset.
Dengan menggunakan Bahasa Jawa halus kepada pasien lansia, dokter tersebut sedang melakukan tiga hal sekaligus:
- Membangun Rapport (Hubungan): Beliau memosisikan diri bukan sebagai "pejabat medis" yang berjarak, melainkan seperti anak atau cucu yang sedang berbakti (ngabekti).
- Menghilangkan Barier Psikologis: Rumah sakit adalah tempat yang mengintimidasi bagi banyak lansia. Bahasa ibu adalah tempat perlindungan yang membuat mereka merasa aman.
- Memastikan Pemahaman: Menjelaskan aturan minum obat dengan bahasa yang paling dimengerti pasien akan meningkatkan kepatuhan (compliance) pengobatan.
Bayangkan jika dokter tetap bersikukuh menggunakan istilah medis rumit atau Bahasa Indonesia formal pada nenek tersebut. Mungkin beliau hanya akan mengangguk sopan, tapi pulang dengan kebingungan dan rasa takut.
Pengalaman ini menampar kesadaran saya sebagai mahasiswa. Di era modern ini, teknologi kedokteran berkembang pesat. Artificial Intelligence (AI) mungkin sebentar lagi bisa mendiagnosis penyakit lebih cepat dari manusia. Robot mungkin bisa mengoperasi lebih presisi dari tangan ahli bedah.
Namun, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin tercanggih sekalipun: merasakan kegelisahan seorang nenek lewat getaran suaranya, dan memilih kata yang tepat untuk menenangkan hatinya. Mesin tidak bisa bicara Krama Inggil dengan rasa hormat yang tulus.
Dokter yang saya amati mengajarkan bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang mengobati organ yang rusak (curing), tetapi merawat manusia yang memiliki jiwa dan latar belakang budaya (caring). Kemampuan komunikasi terapeutik—kemampuan untuk menjadi "bunglon" yang menyesuaikan diri dengan siapa ia bicara—adalah jembatan yang menghubungkan ilmu kedokteran yang dingin dengan kemanusiaan yang hangat.
Kelak, perjalanan saya untuk mengenakan jas putih itu masih panjang. Masih banyak ujian anatomi dan patologi yang harus saya lalui. Namun, pengamatan hari itu memberikan saya bekal yang tak ternilai.
Saya belajar bahwa stetoskop memang alat untuk mendengar detak jantung, tapi empati dan komunikasi adalah alat untuk mendengar isi hati. Menjadi dokter yang baik berarti siap menjadi pendengar yang baik, yang mampu berbicara dalam "bahasa" pasiennya—baik secara harfiah maupun maknawi. Karena pada akhirnya, pasien tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kita peduli.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.