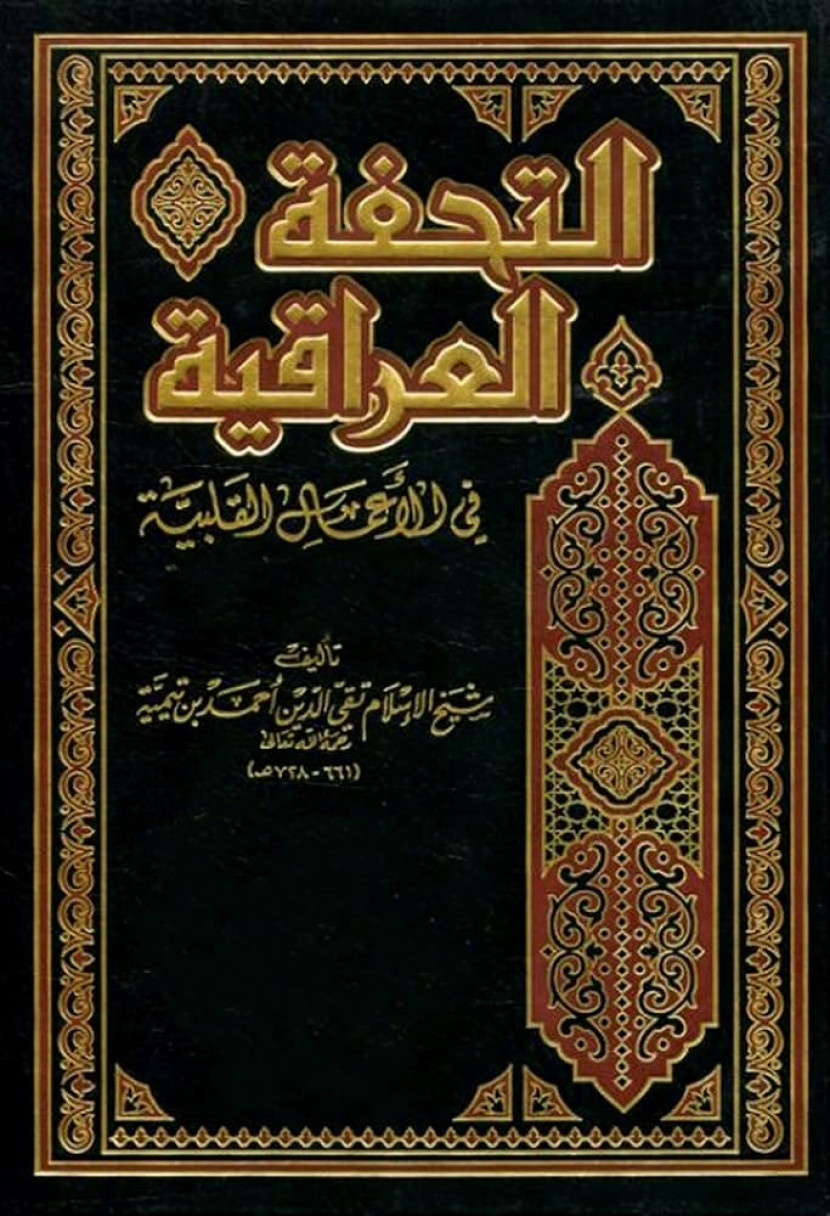Kaha Anwar
Kaha Anwar
Lebih Dekat dari Urat Leher
Agama | 2025-11-22 20:03:31Ada ayat yang tak pernah benar-benar selesai dibaca: “Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” Ayat pendek yang terasa seperti bisikan—bukan dari langit yang jauh, melainkan dari kedalaman yang tak kita kenal dalam diri sendiri.

Para sufi membacanya bukan sebagai pernyataan jarak, tapi pembatalan jarak. Tuhan tidak mendekat dengan langkah; Ia hadir dengan keberadaan. Seperti cahaya yang tak pernah berpisah dari bayangannya, kehidupan manusia tak pernah berpisah dari Sumber yang membuatnya hidup. Kita sering membayangkan Tuhan sebagai puncak yang harus dituju. Tapi ayat itu menampik pendakian: yang jauh bukan Tuhan—melainkan kesadaran kita.
Psikologi modern menyebutnya sense of presence—rasa ditemani oleh sesuatu yang melampaui nalar. Namun, bahasa keilmuan terlalu dingin untuk menggambarkan hangatnya kedekatan yang membuat manusia tiba-tiba tenang, padahal hidup baru saja mengguncangnya. Kedekatan itu bukan konsep; ia terasa pada nadi: saat kecemasan surut, saat tubuh percaya bahwa ada yang memegangnya dari dalam.
Urat leher—gerbang rapuh antara hidup dan mati—dipilih bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan titik paling intim dari manusia. Di sanalah aliran darah menegakkan kehidupan, dan di sanalah ayat itu ingin menempatkan kehadiran ilahi: setipis sehelai denyut, setenang jeda antara dua napas.
Kedekatan yang seperti itu tidak menuntut doa panjang, tidak meminta ritual rumit. Ia hanya menuntut keterjagaan: bahwa manusia sering merasa sendiri bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena manusia terlalu ramai untuk mendengar kehadiran-Nya.
Dan mungkin, dalam hidup yang makin riuh—di mana sunyi menjadi barang langka—ayat itu justru semakin relevan. Ia mengingatkan bahwa di dalam hiruk pikuk, ada sesuatu yang tidak ikut bising: kehadiran yang memeluk, tanpa suara, tanpa jarak.
Di sanalah paradoks itu berdiam: Tuhan lebih dekat dari urat leher, namun manusia selalu merasa jauh. Mungkin karena kita sibuk mencari Tuhan di luar, padahal Ia menghirupkan napas-Nya melalui hidup kita sendiri.
Ayat itu akhirnya bukan tentang Tuhan. Ia tentang manusia—tentang bagaimana kita lupa bahwa kita tidak pernah sendirian, bahkan ketika seluruh dunia terasa menjauh. Tuhan tidak menunggu kita datang. Ia sudah berada di tempat yang paling sulit kita jangkau: bagian terdalam diri, tempat segala kerinduan bermula.
Dan di titik itu, kedekatan ilahi berubah menjadi cermin: bahwa hidup, betapapun rapuh, selalu berada dalam genggaman Yang Maha Dekat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.