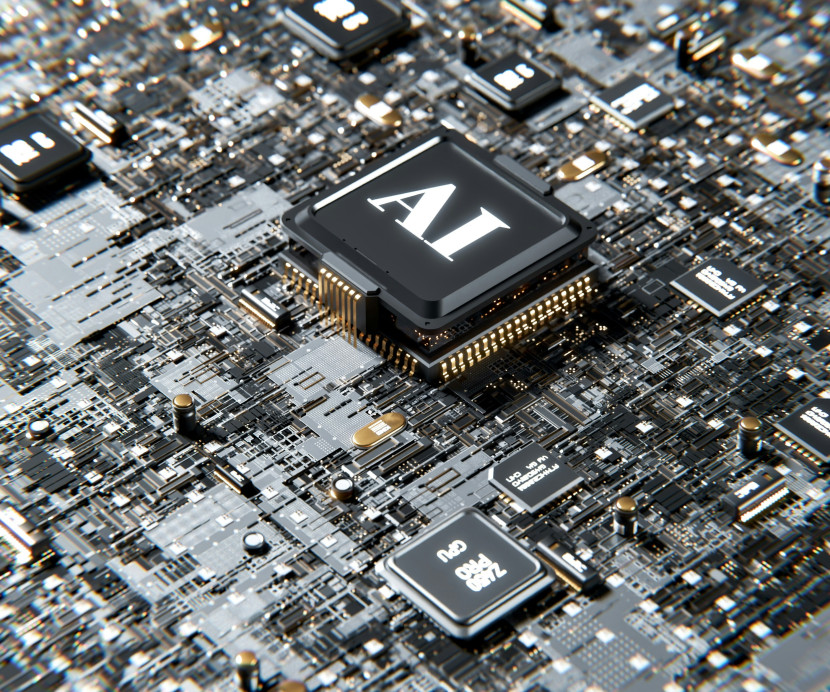Dr.-phil. Ir. Arinafril
Dr.-phil. Ir. Arinafril
Menyoal Ketika Ijazah Tak Lagi Jadi Jaminan Keberhasilan Masa Depan
Pendidikan dan Literasi | 2025-11-03 08:22:41Bayangkan sebuah ironi: jutaan anak muda Indonesia menghabiskan waktu bertahun-tahun di bangku kuliah, mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah, hanya untuk mendapatkan satu lembar kertas yang disebut ijazah. Namun sangat menyedihkan karena banyak kejadian, ijazah yang mereka genggam ternyata bukannya kunci pintu kesuksesan, karena tidak mampu membuka pintu pekerjaan yang mereka dambakan untuk dimasuki.
Data BPS Februari 2025 mencatat lebih dari 1 juta sarjana menganggur, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Dari 7,28 juta pengangguran nasional, 13,89% adalah lulusan perguruan tinggi. Bahkan ada pejabat yang mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa ada ketidaksesuaian (mismatch) antara keterampilan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana, yaitu tidak sesuainya antara kompetensi sarjana atau keterampilan yang dimiliki lulusan kampus dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah mayoritas pekerja di Indonesia justru diisi oleh lulusan SMP ke bawah, sementara pengangguran banyak berasal dari lulusan pendidikan tinggi, menunjukkan adanya tantangan dalam relevansi pendidikan dengan pasar kerja.Di era digital saat ini, ada pandangan bahwa relevansi pendidikan tinggi kian memudar jika tidak dibarengi dengan kesiapan industri atau keterampilan tambahan yang relevan, terutama dengan maraknya kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI).
Secara ringkas, pernyataan tersebut lebih menekankan pada tantangan nyata dalam penyerapan tenaga kerja terdidik dan perlunya perbaikan dalam tautan antara dunia pendidikan dan industri untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tersebut. Pernyataan ini bukan sekadar retorika; ia mencerminkan realitas pahit bahwa pendidikan tinggi kita sedang kehilangan relevansi.
Paradoks Pendidikan Tinggi
Pemerintah menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) 60% pada 2045, tetapi untuk apa menaikkan angka partisipasi jika lulusan tetap menganggur? Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura sudah jauh di depan, tetapi mereka mengaitkan pendidikan dengan kebutuhan industri. Kita? Masih sibuk mengejar kuantitas, bukan kualitas.

Ironisnya, di tengah upaya menaikkan APK, survei Deloitte Global (2025) menunjukkan 31% Generasi Z memilih tidak kuliah. Alasannya jelas: biaya tinggi (39%) dan kurikulum yang dianggap tidak relevan (16%). Mereka beralih ke jalur alternatif: bootcamp, kursus daring, dan magang berbasis proyek. Banyak platform menawarkan program 12–24 minggu dengan biaya yang sangat terjangkau masyarakat, jauh lebih murah dibanding kuliah konvensional, dan langsung terhubung dengan industri. Bandingkan dengan kuliah yang menguras waktu bertahun-tahun dan biaya belasan juta rupiah, tetapi sering gagal memberi keterampilan yang dibutuhkan pasar.
Mengapa Ijazah Kehilangan Nilai?
Masalah utama ada pada kesenjangan antara kurikulum dan dunia kerja. Banyak kampus masih terjebak pada metode lama: transfer pengetahuan, minim praktik, dan jarang mengadopsi pendekatan inovatif seperti refutational teaching—metode yang membongkar miskonsepsi dan melatih berpikir kritis. Padahal, keterampilan ini sangat dibutuhkan di era disrupsi. Program magang yang sempat menjembatani mahasiswa dengan industri, seperti MSIB, kini berubah menjadi Magang Berdampak, memunculkan kekhawatiran soal efektivitas. Sementara itu,menurut investasi besar yang mampu menyerap sarjana masih minim. Serapan tenaga kerja malah melemah ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.
Ijazah kehilangan nilai bukan semata karena perubahan pasar kerja, melainkan karena hilangnya makna pendidikan sebagai proses pembentukan manusia utuh. Ketika pendidikan tinggi hanya menjadi pabrik gelar, bukan ruang pembentukan karakter, nalar, dan kepekaan sosial, maka ijazah tak lebih dari simbol administratif.
Filosofi pendidikan yang seharusnya membebaskan dan memberdayakan justru tereduksi menjadi rutinitas akademik yang steril dari realitas. Mahasiswa tidak dilatih untuk bertanya, meragukan, dan mengonstruksi pengetahuan secara kontekstual, melainkan diarahkan untuk menghafal dan mengikuti pola pikir lama yang tidak relevan dengan tantangan zaman. Dalam kondisi ini, ijazah gagal menjadi representasi kompetensi dan integritas intelektual.
Lebih jauh, nilai ijazah merosot karena sistem pendidikan gagal menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa dan untuk apa pendidikan itu? Ketika orientasi pendidikan lebih condong pada akumulasi angka kredit dan pencapaian administratif, bukan pada pemecahan masalah nyata di masyarakat, maka lulusan kehilangan daya saing dan daya guna.
Dunia kerja membutuhkan pemikir adaptif, bukan sekadar penghafal teori. Tanpa reformasi kurikulum yang berakar pada kebutuhan lokal dan global, serta tanpa keberanian institusi untuk mendobrak pakem lama, maka ijazah akan terus menjadi artefak masa lalu yang tidak mampu menjamin masa depan. Pendidikan harus kembali pada esensinya: membentuk manusia yang mampu berpikir, berempati, dan bertindak secara transformatif.

Era Baru: Intellectual Age
Dr. Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, mengingatkan: “The Fourth Industrial Revolution is not about technology. It is about the people who will create and shape it.” Pendidikan tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana membentuk masyarakat yang inovatif dan inklusif. Kita memasuki Intellectual Age, di mana daya cipta, kolaborasi, dan literasi digital menjadi mata uang utama. Jika perguruan tinggi gagal menyiapkan lulusan dengan keterampilan ini, maka ijazah akan semakin kehilangan makna.
Dalam Intellectual Age, nilai manusia tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang ia simpan, melainkan oleh kemampuannya mengolah, mengkritisi, dan mencipta dari informasi tersebut.
Pendidikan tinggi harus bertransformasi dari sekadar institusi pengajaran menjadi ekosistem pembelajaran yang dinamis, transdisipliner, dan berbasis tantangan nyata. Filosofinya bukan lagi “mengisi gelas kosong,” melainkan “menyalakan api intelektual” yang mendorong mahasiswa menjadi produsen pengetahuan, bukan hanya konsumen. Di sinilah pentingnya pendekatan pedagogis yang menumbuhkan curiosity, epistemic humility, dan kemampuan berpikir sistemik—karakteristik utama manusia abad intelektual.
Lebih jauh, Intellectual Age menuntut redefinisi makna kecerdasan. Bukan hanya IQ atau kemampuan analitis, tetapi juga kecerdasan sosial, emosional, dan ekologis. Perguruan tinggi harus menjadi ruang pembentukan manusia yang mampu hidup dalam kompleksitas, berempati dalam keberagaman, dan bertindak secara berkelanjutan.
Jika pendidikan gagal menanamkan nilai-nilai ini, maka lulusan akan menjadi “cerdas secara teknis” tetapi miskin makna dan arah. Dalam konteks ini, ijazah bukan hanya kehilangan nilai ekonomi, tetapi juga nilai eksistensial. Pendidikan harus kembali menjadi proses pembebasan dan pemberdayaan, bukan sekadar jalur menuju pekerjaan. Sebab, di era intelektual, yang dibutuhkan bukan hanya pekerja, tetapi pemikir dan pembaru.
Ketrampilan Masa Depan: Bekal yang Terlupakan
Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers dan Dr. Laura Eigbrecht (2024) pakar manajemen pendidikan terkemuka dari Baden-Württemberg Cooperative State University, Stuttgart, Jerman, menekankan pentingnya Ketrampilan Masa Depan atau Future Skills: sense-making, innovation literacy, self-organization, dan resilience. Ini bukan jargon akademik, melainkan kompetensi inti agar lulusan mampu beradaptasi di dunia kerja yang dinamis. Sayangnya, sebagian besar kurikulum kita masih berorientasi pada hafalan, bukan pemecahan masalah. Padahal, dunia kerja menuntut kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi lintas disiplin.
Kegagalan sistem pendidikan mencerminkan krisis epistemologis yang lebih dalam: pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai proses pembentukan makna, melainkan sekadar transmisi informasi. Sense-making menuntut kemampuan untuk memahami kompleksitas, mengaitkan pengetahuan dengan konteks, dan merumuskan solusi yang relevan. Tanpa ini, lulusan akan terjebak dalam pola pikir linier yang tidak mampu menjawab tantangan dunia kerja yang bersifat non-linear dan disruptif. Pendidikan harus berani meninggalkan paradigma “satu jawaban benar” dan beralih ke pendekatan yang menghargai ambiguitas, dialog, dan eksplorasi makna.
Lebih jauh, self-organization dan resilience bukan hanya keterampilan teknis, tetapi refleksi dari kematangan eksistensial. Di tengah dunia kerja yang tidak pasti dan terus berubah, individu dituntut untuk mampu mengelola diri, menetapkan arah, dan bangkit dari kegagalan. Ini menuntut pendidikan yang tidak hanya mengasah kognisi, tetapi juga membentuk karakter dan ketangguhan batin. Jika kurikulum terus mengabaikan dimensi ini, maka lulusan akan menjadi rentan: cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara mental dan sosial. Maka, pendidikan masa depan harus berpijak pada filosofi humanistik—membentuk manusia yang utuh, adaptif, dan bermakna dalam perannya sebagai agen perubahan.
Banyak kurikulum perguruan tinggi masih terjebak pada metode transfer pengetahuan konvensional, minim praktik laboratorium, dan jarang mengintegrasikan pengajaran refutasi (refutational teaching)—pendekatan pedagogis yang membongkar miskonsepsi melalui konfrontasi langsung dengan bukti ilmiah. Guru-guru jarang dilatih mengenali miskonsepsi secara sistematis. Padahal, pendekatan ini telah terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi, keterampilan inti yang dibutuhkan dunia kerja modern.
Suara Hati dan Makna Pendidikan
Seorang filsuf besar dunia, Jalaluddin Rumi, pernah berkata: “Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai.” Pendidikan sejati bukan sekadar mengejar gelar, melainkan perjalanan menemukan makna dan membentuk karakter. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, yaitu suara panggilan untuk belajar, berinovasi, dan memberi manfaat. Selayaknya didengar oleh setiap orang. Jika pendidikan hanya menjadi ritual administratif, kita kehilangan esensi yang paling mendalam.
Pendidikan yang berakar pada cinta dan panggilan batin melampaui sekadar transfer pengetahuan; ia menjadi proses transformatif yang membentuk identitas dan arah hidup. Dalam pandangan eksistensial, manusia bukan hanya makhluk yang belajar, tetapi makhluk yang mencari makna.
Ketika mahasiswa diarahkan untuk mengikuti suara panggilan yang otentik, tidak hanya sekadar tuntutan pasar atau tekanan sosial, maka proses belajar menjadi tindakan spiritual dan intelektual sekaligus. Di sinilah pendidikan menemukan ruhnya: bukan pada kurikulum yang kaku, tetapi pada ruang yang memungkinkan pertumbuhan, pencarian, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri yang bermakna.
Namun, sistem pendidikan modern sering kali mematikan suara panggilan itu dengan birokrasi, standar yang seragam, dan obsesi terhadap angka. Ketika cinta terhadap ilmu, keingintahuan, dan semangat memberi manfaat digantikan oleh ketakutan akan kegagalan akademik atau tuntutan administratif, maka pendidikan kehilangan daya hidupnya.
Filosofi Rumi mengingatkan bahwa transformasi sejati hanya terjadi ketika manusia bergerak menuju apa yang ia cintai. Maka, tugas pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membangkitkan jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mencipta, menyembuhkan, dan memperbaiki dunia. Tanpa itu, ijazah hanyalah kertas; bukan cermin dari perjalanan jiwa dan intelektual
Transformasi Mendesak: Dari Institusi ke Ekosistem Inovasi
Solusinya bukan sekadar menaikkan APK atau menambah beasiswa. Transformasi harus mendasar dan komprehensif:
Pertama, kurikulum harus fleksibel dan berbasis kompetensi adaptif. Pendidikan vokasi dan tinggi harus mengintegrasikan future skills seperti sense making, innovation literacy, resilience, dan self-organization—keterampilan esensial di era disrupsi. Program magang harus dirancang ulang untuk menuntut mahasiswa berkolaborasi, berinovasi, dan memecahkan masalah riil.
Kedua, perguruan tinggi harus bertransformasi dari institusi birokratis menjadi ekosistem pembelajaran kolaboratif. Paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu diperluas: pengajaran harus berbasis masalah (Problem-based Learning), penelitian harus terapan dan berorientasi solusi, serta pengabdian masyarakat harus terintegrasi dengan pembangunan sosio-ekologis.
Ketiga, kemitraan strategis dengan industri bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Perguruan Tinggi harus melibatkan praktisi dalam perancangan kurikulum, menyediakan proyek kolaboratif, dan membangun jalur rekrutmen langsung. Career Center harus dioptimalkan sebagai jembatan konkret, bukan sekadar formalitas administratif.
Keempat, pelatihan dosen harus fokus pada substansi mengenali miskonsepsi siswa, bukan hanya pembuatan media pembelajaran. Dosen harus menjadi mentor dan fasilitator yang mendorong eksplorasi, eksperimen, dan refleksi kritis.
Para pakar manajemen pendidikan menegaskan bahwa relevansi pendidikan tinggi harus diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan industri dan masyarakat, bukan sekadar akreditasi formal. Integrasi teknologi dalam manajemen pendidikan adalah katalis untuk menciptakan pembelajaran adaptif dan inklusif.
Momentum yang Tak Boleh Hilang
Visi baru pemerintah saat ini adalah membuka seluas-luasnya aksed pendidikan bagi masyarakat dan membuka lapangan atau peluang kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat di usia produktif kerja. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemerintah atau kampus, melainkan seluruh ekosistem: industri, praktisi, dan mahasiswa. Kita harus beralih dari mengejar kuantitas ijazah menuju kualitas kompetensi. Jika tidak, Indonesia berisiko terjebak selamanya sebagai negara berpendapatan menengah dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak siap menghadapi tantangan global.
Pendidikan tinggi harus kembali menjadi investasi masa depan, bukan sekadar ritual tanpa makna. Seperti kata Rumi, biarkan tarikan kuat dari sesuatu yang kita cintai membentuk kita. Dan seperti pesan Dr. Klaus Schwab, revolusi ini bukan tentang teknologi, melainkan tentang manusia yang mampu mencipta dan beradaptasi.
Target APK 60% di 2045 hanya bermakna jika disertai transformasi kualitas. Kondisi hari ini, lebih dari satu juta sarjana menganggur dan sepertiga Gen Z menolak kuliah, adalah peringatan keras bahwa sistem pendidikan tinggi kita kehilangan relevansi. Tanpa reformasi radikal, Indonesia berisiko terjebak selamanya sebagai negara berpendapatan menengah dengan SDM yang tidak siap menghadapi tantangan global.
Sudah layak pemerintah membuka jendela kesempatan untuk transformasi. Dengan visi baru yang diusung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Menteri Prof. Dr. Brian Yuliarto berharap ada kesinambungan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan industri. Namun transformasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perguruan tinggi, melainkan seluruh ekosistem, baik industri, praktisi, bahkan mahasiswa sendiri.
Saatnya kita beralih dari mengejar kuantitas ijazah menuju membangun kualitas kompetensi. Hanya dengan begitu, pendidikan tinggi akan kembali menjadi investasi yang menjanjikan, bukan sekadar ritual tanpa makna. Saatnya kita menjadikan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan, bukan sekadar menara gading yang kehilangan pijakan.
(Penulis adalah Pemerhati Pendidikan Tinggi, Doktor Biogeografi lulusan Universität des Saarlandes, Jerman; Fulbright Visiting Fellow di Clemson University, AS; Dosen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia; dan Dosen Tamu di Dai hoc Nong Lam, Thai Nguyen, Vietnam)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.