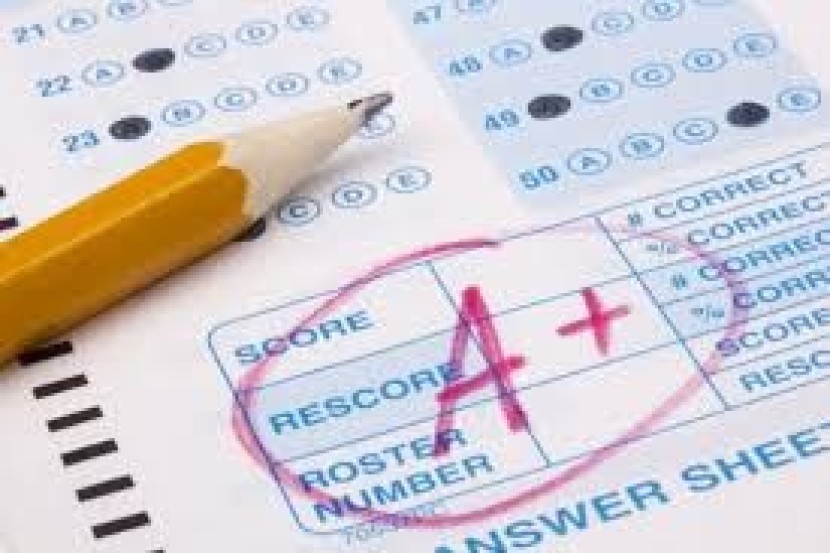Firly Eka Zuhrina
Firly Eka Zuhrina
Ironi Pendidikan Moral: Bullying yang Masih Hidup di Pesantren
Adab | 2025-10-27 21:08:10
Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat bagi para siswa untuk mengembangkan diri, menuntut ilmu, memperluas relasi, dan meningkatkan keterampilan. Idealnya, lingkungan pendidikan mencerminkan suasana yang sehat, saling mendukung, dan penuh rasa kebersamaan antar teman. Namun, kenyataannya justru berbeda. Perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan, khususnya di pondok pesantren, masih menjadi persoalan serius yang berdampak besar pada korban.
Sejak dulu, kasus bullying, perundungan, hingga pelecehan kerap terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Bahkan, tak sedikit korban yang sampai mengalami tekanan mental berat hingga berujung pada tindakan bunuh diri.
Menurut data yang dikutip dari website Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bintan, H. Erman Zaruddin menyatakan bahwa tingkat bullying di pondok pesantren dan madrasah justru tercatat paling rendah dibanding lembaga pendidikan lainnya. Data menunjukkan angka bullying di madrasah dan pondok pesantren sama-sama 6,25%. Sedangkan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) angkanya mencapai 25%, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di angka 18,75%. Menurut Erman, hal ini menunjukkan bahwa siswa di lembaga pendidikan agama lebih aman dari tindakan bullying.
Namun, kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dan survei dari beberapa narasumber yang memiliki latar belakang pondok pesantren mengatakan bahwa tak sedikit dari mereka masih menemukan kasus perundungan di lingkungan pesantren, baik oleh senior maupun dari teman sebaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut.
1. Sistem Senioritas yang Terlalu Kuat
Budaya senioritas menjadi salah satu penyebab paling umum munculnya bullying di pesantren. Santri senior sering kali merasa memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap santri junior, terutama di lingkungan asrama. Awalnya, tradisi ini bertujuan menanamkan disiplin dan rasa hormat, namun dalam praktiknya justru sering melampaui batas. Hukuman fisik, pemalakan, perintah kasar, bahkan bentuk ejekan sering dianggap hal biasa dan seringkali dianggap “pelajaran kedewasaan dan melatih mental”, padahal sebenarnya hak merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis.
2. Kurangnya Pengawasan dan Penanganan Serius
Tidak semua pesantren memiliki sistem pengawasan yang ketat, terutama di area asrama yang menjadi tempat paling rawan terjadinya perundungan. Beberapa pengasuh atau ustaz mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi di antara para santri, apalagi jika korban tidak berani melapor karena diancam senior. Selain itu, belum semua pesantren memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, sehingga kasus bullying sering kali tertutup dan dibiarkan. Penanganan dan pemberian sanksi yang kurang tegas juga memperparah hal ini, sehingga penanganan yang diberikan kurang berdampak dan tidak menimbulkan efek jera.
3. Menormalisasi Kekerasan dan Dianggap Tradisi
Faktor budaya juga berperan besar dalam kasus pembullyan di pesantren. Dalam beberapa pesantren, kekerasan atau hukuman keras dianggap sebagai bagian dari pembelajaran hidup dan pembentukan karakter. Akibatnya, banyak santri yang menganggap bahwa dipukul, dicaci, atau diperintah seenaknya oleh senior adalah hal biasa dan sudah tradisi. Lebih parah lagi, ketika santri yang dulu menjadi korban justru mengulang perilaku itu dan membalas dendam kepada juniornya, sehingga menimbulkan sebuah siklus kekerasan yang terus berputar.
4. Kondisi Psikologis dan Latar Belakang Keluarga
Beberapa pelaku bullying sebenarnya menyimpan luka batin atau trauma yang belum terselesaikan. Santri yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras, kurang kasih sayang, atau terbiasa dengan kekerasan, cenderung meniru perilaku yang sama. Bullying menjadi salah satu cara mereka untuk melampiaskan emosi atau untuk mendapat validasi sehingga merasa berkuasa. Di sisi lain, korban yang tidak memiliki keberanian untuk melawan biasanya memilih diam karena takut dikucilkan atau dianggap lemah karena mengadu.
5. Kurangnya Pendidikan Empati dan Kesehatan Mental
Pesantren dikenal unggul dalam pendidikan agama dan moral, namun sering kali mengabaikan pendidikan emosional dan sosial. Padahal, membangun empati, kemampuan memahami perasaan orang lain, dan kesadaran terhadap dampak kekerasan sangat penting untuk mencegah bullying. Santri perlu dibimbing untuk memahami bahwa menghormati bukan berarti menindas, dan mendidik bukan berarti menyakiti.
Bullying di pesantren bukan hanya masalah antar-santri, namun juga cermin dari sistem pendidikan yang perlu dibenahi. Lembaga pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh kasih, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi seluruh alam). Pihak pesantren perlu membuka mata dan hati untuk membenahi sistem pengawasan, memberikan pendidikan anti-kekerasan, dan menyediakan ruang konseling bagi santri. Santri juga perlu dilatih untuk saling menghargai dan menumbuhkan empati. Karena pesantren yang ideal adalah pesantren yang dimana santrinya merasa aman dan nyaman untuk belajar, tumbuh, dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.