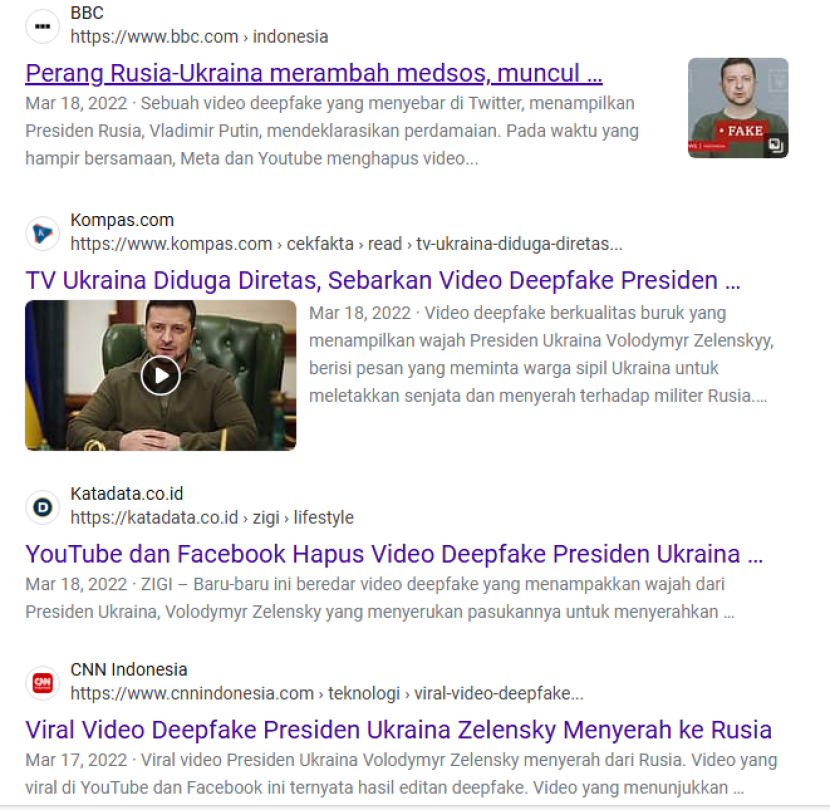M. Azra Ghiffari Athallah
M. Azra Ghiffari Athallah
ASEAN dan Tantangan Liberalisme di Laut Tiongkok Selatan
Politik | 2025-10-18 22:08:58
Di tengah riuhnya geopolitik global, Laut Tiongkok Selatan (LTS) kembali menjadi panggung pertarungan kepentingan. Jalur laut strategis yang menampung lebih dari sepertiga perdagangan dunia itu kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Di satu sisi, negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia menegaskan klaim kedaulatannya; di sisi lain, Tiongkok menunjukkan ekspansi maritim dengan membangun pulau buatan dan patroli militer. Namun di antara silang kepentingan itu, muncul satu pertanyaan penting: sejauh mana prinsip liberalisme dan kerja sama regional ASEAN masih relevan untuk menjaga stabilitas kawasan?
Dalam teori liberalisme, perdamaian dan stabilitas bisa dicapai melalui kerja sama antarnegara, bukan konfrontasi. Pandangan ini menolak asumsi realisme yang melihat dunia sebagai arena kompetisi kekuasaan. Bagi kaum liberal, institusi internasional seperti ASEAN berperan penting sebagai “penengah” yang memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan menurunkan risiko konflik.
Sejak berdirinya ASEAN Regional Forum (ARF) dan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada 2002, optimisme liberal sempat tumbuh. Negara-negara anggota percaya bahwa diplomasi bisa menggantikan dominasi kekuatan militer. Melalui confidence building measures dan dialog terbuka, ASEAN berusaha menjadikan LTS bukan sebagai “zona konflik,” melainkan “zona kerja sama.”
Namun dua dekade kemudian, optimisme itu mulai goyah. Aktivitas militer Tiongkok meningkat, pembangunan fasilitas di pulau buatan terus berjalan, dan insiden antara kapal penjaga pantai Filipina dan kapal Tiongkok makin sering terjadi. ASEAN, meski tetap mengedepankan diplomasi, terlihat terjebak dalam “ASEAN Way” yang cenderung lamban, kompromistis, dan menghindari konfrontasi terbuka.
Masalah mendasar ASEAN dalam menghadapi isu LTS adalah kurangnya kesatuan politik di antara negara anggotanya. Liberalisme menekankan pentingnya institusi untuk mendorong norma dan kepentingan bersama, tapi di ASEAN, solidaritas regional sering terkendala oleh kepentingan nasional yang beragam.
Filipina, misalnya, memilih jalur hukum dengan membawa sengketa ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 dan memenangkan gugatan terhadap klaim “nine-dash line” Tiongkok. Tapi negara lain, seperti Kamboja dan Laos, justru menolak mendukung langkah tersebut karena ketergantungan ekonomi yang besar pada Beijing. Akibatnya, ASEAN tidak mampu mengeluarkan satu sikap tegas Bersama sebuah kegagalan yang bertentangan dengan idealisme liberal tentang collective decision-making.
Keterbatasan ini menciptakan paradoks: ASEAN ingin memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas kawasan, tapi justru terperangkap dalam mekanisme internal yang menghambat efektivitasnya. Alih-alih menjadi motor integrasi, ASEAN terkesan menjadi “penonton elegan” di panggung perebutan pengaruh antara kekuatan besar.
Kegamangan ASEAN mencerminkan ujian berat bagi teori liberalisme itu sendiri. Konsep liberal menekankan bahwa melalui interdependensi ekonomi dan institusi multilateral, negara akan terdorong untuk bekerja sama daripada berkonflik. Dalam konteks ASEAN–Tiongkok, logika ini seolah masuk akal: perdagangan antar keduanya bernilai ratusan miliar dolar, dan Tiongkok menjadi mitra ekonomi terbesar kawasan. Tetapi, interdependensi ekonomi ternyata tidak otomatis menghapus kecurigaan strategis.
Justru sebaliknya, Beijing memanfaatkan kedekatan ekonomi untuk memperluas pengaruh politiknya. Dengan bantuan investasi melalui Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok berhasil “melunakkan” sebagian anggota ASEAN agar tidak mengkritik kebijakan maritimnya. Ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi tanpa transparansi dan kesetaraan bisa menjadi alat hegemoni barubukan jaminan perdamaian.
Meski begitu, liberalisme belum sepenuhnya gagal. Pendekatan ini masih menjadi satu-satunya jalan yang rasional di tengah ketegangan yang bisa memicu militerisasi kawasan. Upaya pembentukan Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok, misalnya, meski berjalan lambat, menunjukkan bahwa dialog multilateral tetap dianggap penting. Prinsip peaceful dispute settlement yang dijaga ASEAN adalah manifestasi dari nilai-nilai liberal yang menolak penggunaan kekuatan sebagai solusi utama.
Jika ASEAN ingin mempertahankan relevansinya, maka diperlukan reformasi cara pandang terhadap kerja sama regional. ASEAN harus berani melampaui “ASEAN Way” yang terlalu menekankan konsensus dan menghindari perbedaan. Konsensus tanpa arah hanya melahirkan stagnasi diplomatik. Dalam konteks liberalisme modern, justru perbedaan pandangan bisa menjadi sumber inovasi jika dikelola dengan mekanisme institusional yang kuat. Indonesia, sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN, memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai norm entrepreneur penggagas nilai dan arah baru kebijakan kawasan. Jakarta perlu mendorong pendekatan yang lebih proaktif dalam menyusun Code of Conduct yang mengikat secara hukum, bukan sekadar deklaratif. Selain itu, kerja sama maritim berbasis sains, keamanan non-tradisional, dan penegakan hukum laut bisa menjadi basis baru bagi solidaritas ASEAN yang lebih substantif.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.