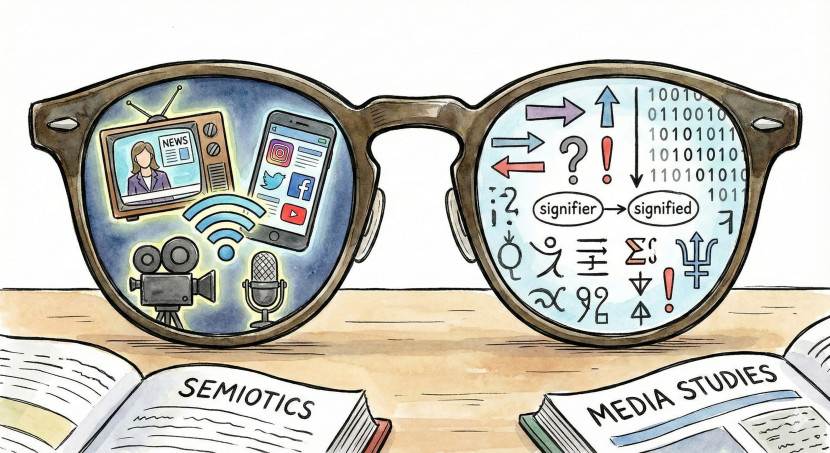Muhammad Arsa Wijaya
Muhammad Arsa Wijaya
Ketika Loyalitas dan Narasi Tak Lagi Berimbang
Rubrik | 2025-10-16 07:22:48
Menurut data Kementerian Agama tahun 2024/2025, terdapat sekitar 42.433 pondok pesantren aktif di seluruh Indonesia. Jumlah ini menunjukkan betapa besar peran pesantren dalam membentuk karakter bangsa. Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga wadah pendidikan moral, sosial, dan kebangsaan. Dari lembaga ini lahir ribuan ulama, guru, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, pesantren memiliki posisi istimewa dalam hati masyarakat, terutama di kalangan Nahdliyin. Namun, belakangan muncul peristiwa yang menimbulkan gejolak di ruang publik.
Program Xpose Uncensored yang tayang di Trans7 pada pertengahan Oktober 2025 menuai kecaman luas. Tayangan itu menampilkan potongan video yang menggambarkan santri sedang menyalami seorang kiai sepuh di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Narasi yang menyertai video tersebut dianggap menyinggung karena menyebut santri “rela ngesot” demi memberikan amplop kepada kiai.
Penggunaan diksi tersebut dinilai merendahkan martabat ulama dan menafsirkan secara keliru hubungan spiritual antara kiai dan santri. Tayangan itu memicu kemarahan publik. Ribuan warganet, terutama dari kalangan santri dan alumni pesantren, menyerukan tagar #BoikotTrans7 di media sosial. Mereka menilai program tersebut melecehkan tradisi pesantren yang dijaga turun-temurun. Trans7 kemudian menyampaikan permintaan maaf dan melakukan evaluasi internal. Namun, amarah publik terlanjur menyebar, menjadi simbol ketegangan antara dunia media dan komunitas pesantren.
Kasus ini memperlihatkan dua sisi yang sama-sama bermasalah. Pihak pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar tradisi penghormatan kepada kiai tetap berada dalam koridor syariat Islam. Sementara pihak media wajib berhati-hati agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi alat yang menyakiti keyakinan masyarakat. Dalam tradisi pesantren, santri memandang kiai sebagai guru dan pembimbing spiritual. Penghormatan terhadap kiai merupakan bagian dari adab dan keimanan. Santri belajar bukan hanya dari isi kitab, tetapi juga dari perilaku gurunya. Hubungan itu mengandung nilai pengabdian dan keikhlasan.
Namun, pada praktiknya, sebagian tradisi penghormatan mulai bergeser. Sebagian santri atau masyarakat sering memuja kiai secara berlebihan dan mengaitkan keberkahan hidup dengan figur manusia, bukan dengan Allah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna. Adab yang seharusnya menumbuhkan ketundukan spiritual berubah menjadi sikap yang mendekati pengkultusan. Tindakan seperti berebut air bekas minum kiai atau memberikan amplop bukan lagi sekadar simbol cinta, tetapi telah dipahami secara literal dan materialistik. Akibatnya, penghormatan kehilangan nilai tauhid yang menjadi landasannya. Di sisi lain, media juga perlu mawas diri.
Program Xpose Uncensored seharusnya menjadi contoh penting tentang bagaimana narasi dapat membentuk persepsi publik. Redaksi yang tidak memahami konteks sosial mudah tergelincir pada cara pandang yang sempit. Kritik terhadap fenomena sosial seharusnya disampaikan dengan empati dan akurasi, bukan dengan bahasa yang memancing emosi. Narasi yang mengandung bias atau ejekan terhadap simbol agama dapat menghapus kepercayaan publik terhadap media itu sendiri. Media memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial.
Kebebasan berekspresi tidak boleh menjadi alasan untuk menistakan nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, kepekaan terhadap budaya lokal menjadi bagian dari etika jurnalistik. Ketika media gagal memahami nilai kultural pesantren, dampaknya bukan hanya pada reputasi lembaga, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat. Gerakan boikot yang muncul di dunia maya juga menunjukkan dinamika baru dalam relasi masyarakat dan media. Publik kini tidak lagi menjadi penonton pasif.
Mereka berani menilai dan menuntut akuntabilitas. Akan tetapi, kemarahan massal di media sosial sering berkembang tanpa arah yang jelas. Boikot bisa berubah menjadi persekusi digital yang menyerang keseluruhan lembaga tanpa memisahkan antara kesalahan individu dan tanggung jawab institusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat digital masih belajar membedakan antara kritik yang membangun dan amarah yang destruktif. Kedua pihak, baik pesantren maupun media, memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki keadaan.
Pihak pesantren perlu memperkuat pemahaman tentang nilai adab dan mengembalikannya pada tujuan spiritual. Penghormatan kepada kiai harus tetap berakar pada keyakinan bahwa segala keberkahan hanya datang dari Allah. Sementara itu, pihak media perlu memperdalam literasi budaya agar mampu memahami konteks sosial secara utuh sebelum menayangkan sebuah konten. Kritik sosial yang bijak tidak menertawakan tradisi, tetapi menuntun publik untuk memahami esensinya. Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa Indonesia membutuhkan ruang dialog antara media dan masyarakat pesantren. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan menjaga nilai moral bangsa. Pesantren berperan menanamkan etika dan spiritualitas, sementara media bertugas menjaga keterbukaan dan kebenaran informasi. Ketika keduanya saling memahami, masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak hanya benar, tetapi juga bermartabat. Kasus Xpose Uncensored tidak seharusnya berhenti pada seruan boikot. Peristiwa ini perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali cara kita memandang tradisi dan perbedaan. Masyarakat modern perlu belajar menghargai nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip rasionalitas. Begitu pula, masyarakat pesantren perlu menimbang ulang praktik-praktik tradisi agar tidak terjebak dalam pengkultusan yang melanggar prinsip tauhid. Indonesia tumbuh dari keberagaman budaya dan keyakinan. Setiap kelompok memiliki nilai yang patut dihargai. Dalam masyarakat seperti ini, keseimbangan antara akal dan adab menjadi kunci. Media yang beretika akan memperkuat persatuan, sedangkan media yang gegabah akan menimbulkan perpecahan. Kita semua, baik santri, jurnalis, maupun masyarakat umum, perlu belajar bahwa kebebasan dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan. Menghormati orang lain tidak berarti kehilangan kebebasan berpikir. Mengkritik sesuatu tidak harus disampaikan dengan cara yang menyakiti. Dalam dunia yang dipenuhi informasi cepat, adab dan empati menjadi penuntun utama agar kebenaran tidak kehilangan arah. Kasus ini menjadi cermin bahwa tradisi dan modernitas tidak perlu saling meniadakan. Jika pesantren mampu menata kembali nilai adabnya, dan media mampu memperkuat empati dalam narasinya, maka keduanya akan berjalan berdampingan dalam membangun masyarakat yang berilmu, santun, dan beradab. Indonesia membutuhkan keseimbangan itu untuk menjaga ruh kebersamaan di tengah derasnya arus digital. Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari dua pihak. Pesantren perlu memperkuat pendidikan nilai agar tidak salah arah, sedangkan media perlu memastikan setiap kata yang disiarkan mencerminkan tanggung jawab moral. Dalam situasi seperti ini, menjaga kehormatan lebih penting daripada mengejar sensasi. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa kebenaran tidak hanya diukur dari seberapa keras seseorang bersuara, tetapi dari seberapa dalam ia memahami makna di balik setiap tindakan. Kita sedang diingatkan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, menjaga adab tetap menjadi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.