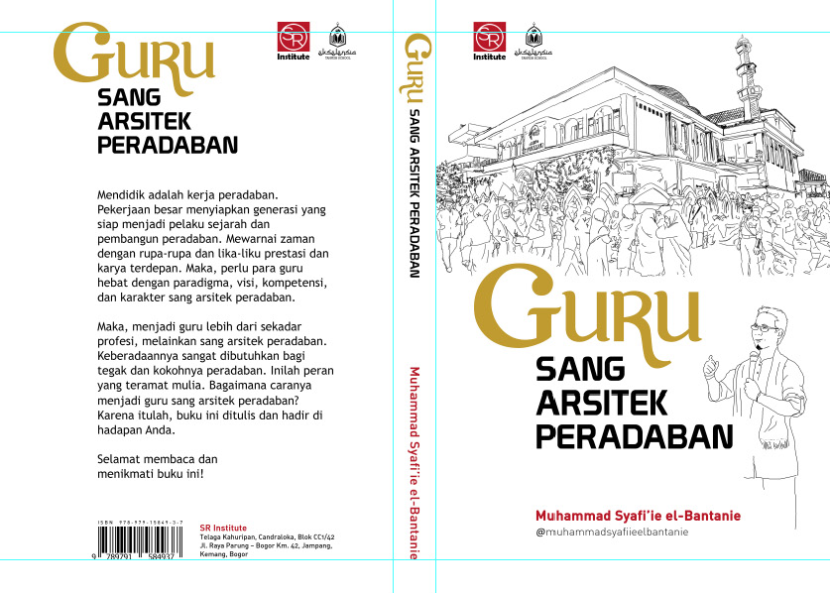Fikri Haekal Akbar
Fikri Haekal Akbar
Fenomena Wisuda Sekolah: Ketika Seremoni Kelulusan Justru Menjadi Ajang Kosmetik Pendidikan
Edukasi | 2025-05-19 13:47:21
Belakangan ini, dunia pendidikan kita dikejutkan oleh sebuah fenomena yang bisa dikatakan absurd sekaligus menggelikan: pelaksanaan Sidang Senat Terbuka sebagai acara kelulusan siswa SMK CBM Purwokerto. Istilah ini sejatinya adalah jargon perguruan tinggi bergengsi, digunakan untuk acara resmi di mana keputusan-keputusan penting akademik dan seremonial dijalankan oleh senat kampus yang memang ada secara formal dan sah. Namun di SMK CBM Purwokerto, Sidang Senat Terbuka ini dijadikan ajang kelulusan bertajuk wisuda dengan segala seremoninya, toga, gordon, bahkan guru-guru yang mengenakan gordon lengkap dengan tongkat pedel sebagai simbol kewibawaan, menciptakan pertunjukan dramatis bak pentas teater.
Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan bersama: Sejak kapan sebuah sekolah menengah kejuruan memiliki senat akademik? Jawabannya sederhana, tapi krusial: sekolah tingkat menengah tidak punya senat. Senat akademik adalah badan formal yang hanya ada di perguruan tinggi, terdiri dari pimpinan universitas dan dosen yang punya wewenang menentukan kebijakan akademik dan legitimasi pemberian gelar. Maka, penggunaan istilah “Sidang Senat Terbuka” dalam konteks SMK bukan hanya salah kaprah, tapi juga menunjukkan pemahaman yang kurang tentang struktur dan hierarki pendidikan di Indonesia.
Lebih jauh, mari kita bicara soal simbol-simbol seremonial yang digunakan dalam acara ini. Toga yang identik dengan wisuda perguruan tinggi, kini menjadi kostum pesta yang dipaksakan ke siswa SMK. Tidak hanya itu, guru-guru yang mestinya berperan sebagai pendidik dan pembimbing malah mengenakan gordon bak profesor di kampus elit, bahkan membawa tongkat pedel yang seakan menegaskan kewibawaan ala-ala akademisi tinggi. Ini bukan sekadar soal pakaian, tapi sebuah insiden yang mengaburkan batas antara jenjang pendidikan dan makna penghargaan yang sesungguhnya.
Perlu ditegaskan pula, dalam terminologi pendidikan yang tepat, acara kelulusan siswa SMA, SMK, atau jenjang pendidikan dasar menengah tidak pernah disebut wisuda. Istilah yang benar dan seharusnya digunakan adalah pengukuhan atau pelepasan siswa. Wisuda adalah terminologi resmi untuk perguruan tinggi karena di sanalah gelar akademik diberikan secara sah oleh otoritas senat. Menggunakan istilah “wisuda” untuk pelepasan siswa sekolah bukan hanya menyalahi tatanan akademik, tetapi juga memberi kesan seolah-olah siswa mendapatkan gelar, padahal tidak demikian.
Kalau dilihat dari sisi psikologis dan sosial, apa yang terjadi jelas membebani siswa dan orang tua. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan praktis, kini terkuras untuk menyewa toga, membeli gordon, mendekorasi lokasi, hingga membuat video dokumentasi yang glamor. Apakah ini investasi pendidikan yang benar? Atau justru menambah beban ekonomi dan tekanan sosial bagi keluarga yang mungkin sudah berjuang keras demi pendidikan anaknya?
Selain itu, fenomena ini mencerminkan perubahan makna simbol pendidikan yang semakin dangkal dan konsumtif. Wisuda, yang pada dasarnya adalah momen refleksi dan apresiasi terhadap pencapaian belajar, berubah menjadi ajang pamer gengsi dan pencitraan media sosial. Foto-foto indah penuh gaya dengan toga, gordon, dan tongkat pedel tersebar di media sosial seolah menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan, padahal sebenarnya kualitas dan hasil pembelajaran sejatinya tidak bisa diukur dari seberapa mewah pesta wisuda itu.
Apakah dengan mengadopsi prosesi Sidang Senat Terbuka dan atribut perguruan tinggi ini, siswa benar-benar lebih siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan? Ataukah kita hanya menciptakan generasi yang terjebak dalam ekspektasi formalitas yang kosong, mengedepankan simbol ketimbang substansi?
Lebih parahnya, kasus SMK CBM Purwokerto ini kemungkinan bukan satu-satunya. Ada indikasi bahwa banyak sekolah lain, baik SMK, SMA, maupun sederajat, mulai mengikuti tren wisuda berlebihan dengan tata cara ala perguruan tinggi, namun karena tidak terekspos media, praktik ini tersembunyi dan tidak mendapatkan perhatian yang layak. Ini menjadi tren berbahaya yang perlahan-lahan merasuk ke budaya pendidikan kita, tanpa disadari menggeser fokus dari pembelajaran bermutu menjadi sekadar ritual pencitraan.
Dalam merespons kritik publik, pihak SMK CBM Purwokerto menyampaikan klarifikasi bahwa pemakaian atribut tersebut hanyalah simbolik. Menurut pernyataan resmi yang beredar, “Tidak ada undang-undang yang melarang atau mengatur secara spesifik pemakaian toga, gordon, atau penyebutan istilah sidang senat terbuka oleh sekolah.”
Namun justru di situlah letak persoalannya. Fakta bahwa tidak ada aturan yang melarang bukan berarti hal tersebut etis atau pantas dilakukan. Pendidikan bukanlah ranah yang bisa dijalankan berdasarkan asas “asal tidak dilarang.” Ia menuntut nilai-nilai kepantasan, kejelasan jenjang, dan penghargaan terhadap struktur akademik yang benar. Pernyataan tersebut menunjukkan kecenderungan legalistik sempit, seolah-olah selama tidak ada pasal hukum yang mengekang, maka semua sah-sah saja dilakukan. Padahal, pendidikan bukan hanya persoalan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut etika, integritas, dan penghormatan terhadap nilai akademik yang tepat guna.
Bayangkan jika setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah berlomba-lomba mengadopsi simbol dan gaya akademik perguruan tinggi hanya karena tidak ada pasal yang melarangnya. Ini berisiko menurunkan makna dan otoritas simbol akademik itu sendiri. Di masa depan, masyarakat bisa kehilangan kepekaan dalam membedakan mana lulusan sarjana yang benar-benar melalui jenjang akademik yang sah, dan mana lulusan yang hanya “diwisuda” oleh sekolahnya sendiri dengan gaya dan istilah yang meniru-niru dunia kampus.
Sebagai bangsa yang sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam budaya formalitas yang keliru ini. Pendidikan bukan soal siapa paling heboh di prosesi wisuda atau siapa paling mewah pakaiannya, melainkan soal membangun karakter, keterampilan, dan pemahaman mendalam yang mampu membawa siswa siap hidup mandiri dan produktif.
Kita perlu mengembalikan pendidikan ke esensinya. Jangan biarkan istilah-istilah akademik seperti “Sidang Senat Terbuka” dipakai sembarangan. Jangan biarkan toga dan gordon menjadi simbol kosong yang hanya memperbanyak beban. Dan terutama, jangan biarkan wisuda menjadi pesta kosmetik yang menutupi kenyataan pendidikan yang sesungguhnya.
Akhir kata, mari kita renungkan: tidak semua orang bisa kuliah, itu memang kenyataan. Tapi tidak semua orang boleh seenaknya wisuda. Penghargaan atas proses belajar harus proporsional dengan jenjang pendidikan dan konteksnya. Jangan sampai obsesi pencitraan dan kesalahpahaman tentang simbol pendidikan membuat kita kehilangan makna dari pendidikan itu sendiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.