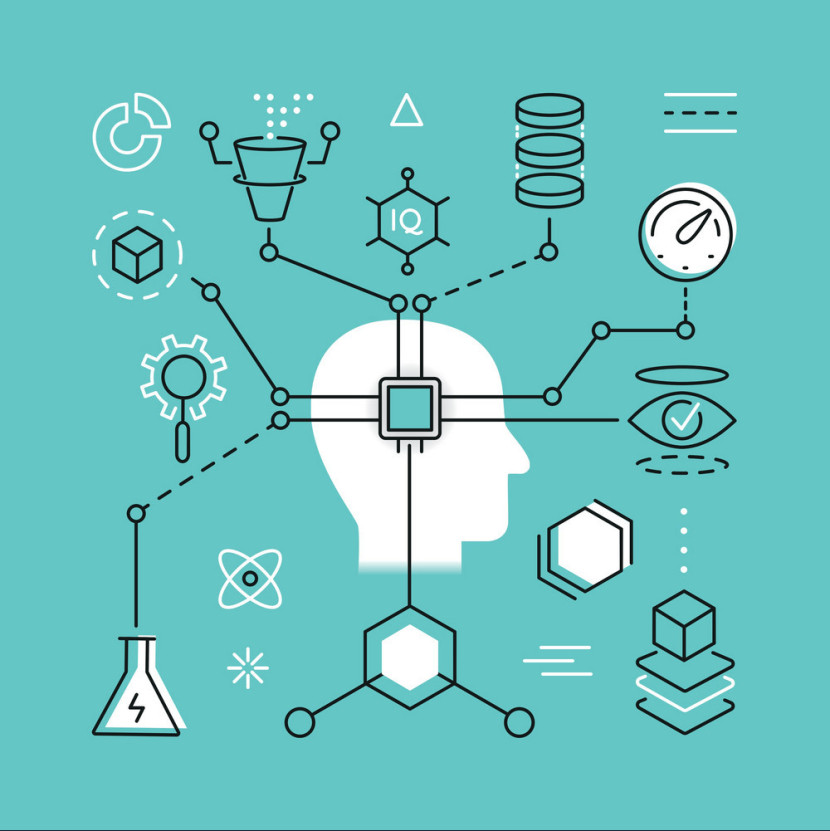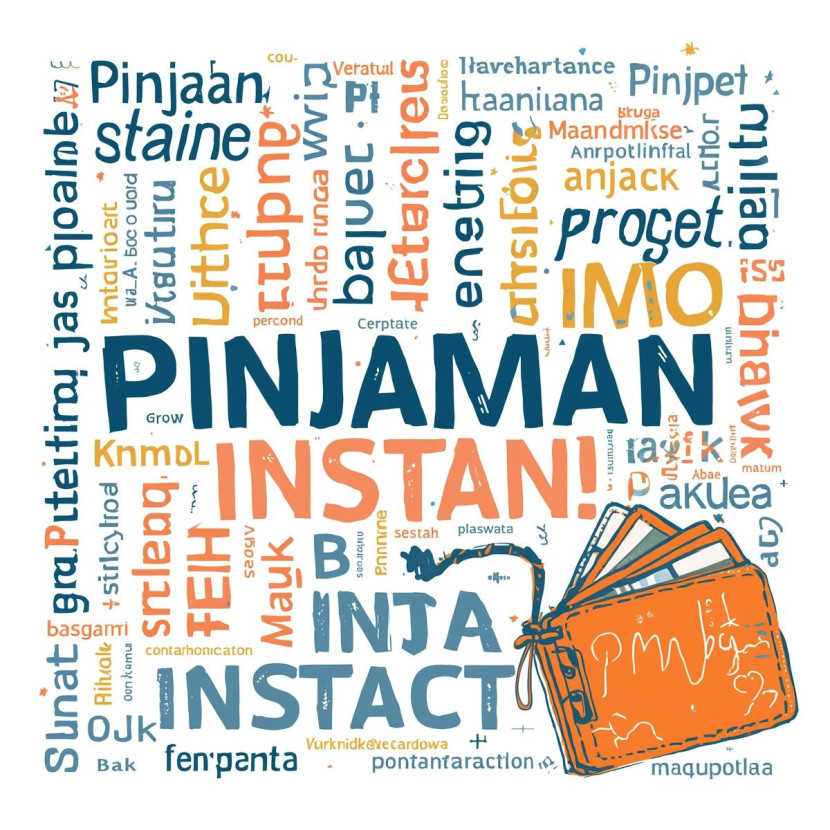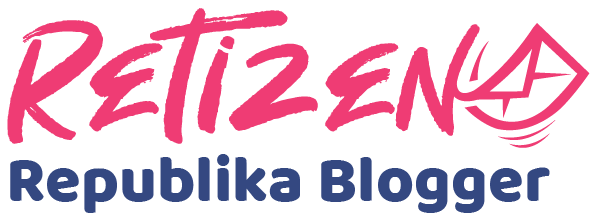Pertanian
Pertanian
Pengembangan Biofarmaka untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Bisnis | 2025-04-06 21:57:39Jakarta, 25 Juni 2024 – Di tengah ketergantungan Indonesia pada impor obat dan kerentanan sistem kesehatan global, Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan strategi penguatan kemandirian obat melalui optimalisasi tanaman biofarmaka. Kuntoro Boga Andri, Kepala Pusat Badan Riset dan Pengembangan (BRMP) Perkebunan Kementan, menegaskan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia harus menjadi tulang punggung ketahanan kesehatan dan ekonomi nasional.

“Pandemi COVID-19 membuka mata kita: ketergantungan pada impor obat dan alat kesehatan adalah ancaman serius. Saatnya kita bertumpu pada kekuatan sendiri, dan tanaman biofarmaka adalah jawabannya,” tegas Kuntoro dalam paparannya di Jakarta, Selasa (25/6).
Berdasarkan data WHO, 80% populasi global menggunakan obat herbal, dengan nilai perdagangan enam kelompok tanaman obat mencapai USD 4,3 miliar (Rp67,3 triliun) pada 2015. Namun, Indonesia yang memiliki 9.600 spesies tanaman obat dan 22.000 ramuan tradisional masih tertinggal dari Tiongkok, India, dan Brasil. Ekspor tanaman obat Indonesia hanya tumbuh dari USD 222,8 juta (2012) menjadi USD 291,8 juta (2023), jauh di bawah potensi sesungguhnya.
“Kita punya varietas unggul seperti nilam Patchoulina 1-2 dengan kadar PA di atas 30%, jahe merah Jahira, dan kunyit Curdonia yang kualitasnya bersaing global. Tapi industri dalam negeri masih bergantung impor karena pasokan lokal belum stabil,” ujar Kuntoro.
Petani Butuh Dukungan Teknis dan Pembiayaan karena Produktivitas tanaman obat lokal masih rendah. Contohnya, produktivitas jahe nasional hanya 8–10 ton/hektare, sementara India mencapai 25 ton/hektare. Petani juga menghadapi keterbatasan lahan, akses pembiayaan, dan pengetahuan budidaya. Untuk itu, Kementan mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah dan pelatihan Good Agricultural Practices (GAP).
Kabupaten Temanggung menjadi contoh keberhasilan diversifikasi: 3.000 petani beralih dari tembakau ke purwoceng (tanaman obat khas Pegunungan Dieng) berkat pendampingan akademisi dan pemerintah daerah.
Kuntoro menekankan pentingnya industrialisasi produk herbal. Minyak nilam mentah yang dihargai USD 15/kg bisa naik 33 kali lipat menjadi USD 500/kg jika diolah menjadi isolat patchouli alcohol. “Kami mendorong pembangunan pabrik ekstraksi berteknologi tinggi di sentra produksi dan kolaborasi BUMN-UMKM,” tambahnya.
Model quadruple helix (petani-pemerintah-akademisi-industri) juga diadopsi, mengikuti kesuksesan India dengan Agri-Export Zones. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) saat ini menggandeng UMKM untuk produksi sediaan farmasi modern berbasis herbal.
Selain aspek ekonomi, pengembangan biofarmaka juga menjadi benteng pelestarian budaya. Lebih dari 300 etnis di Indonesia memiliki kearifan pengobatan tradisional, namun baru 152 paten tanaman obat yang dimiliki Indonesia, jauh di bawah Tiongkok (14.000 paten). “Kami perkuat dokumentasi pengetahuan tradisional untuk mencegah biopiracy,” tegas Kuntoro.
Peluang pasar global terbuka lebar karena nilai pasar obat herbal organik diproyeksikan tumbuh dari USD 14,8 miliar (2023) menjadi USD 24,5 miliar (2030). Untuk itu, Kementan menyiapkan peta jalan terintegrasi dengan SDGs dan Industri Hijau, termasuk integrasi herbal dalam JKN dan pelatihan herbalis bersertifikat.
“Dengan kekayaan alam, budaya, dan SDM, Indonesia bisa menjadi raksasa biofarmaka dunia. Ini momentum untuk berdaulat di bidang kesehatan,” pungkas Kuntoro.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.