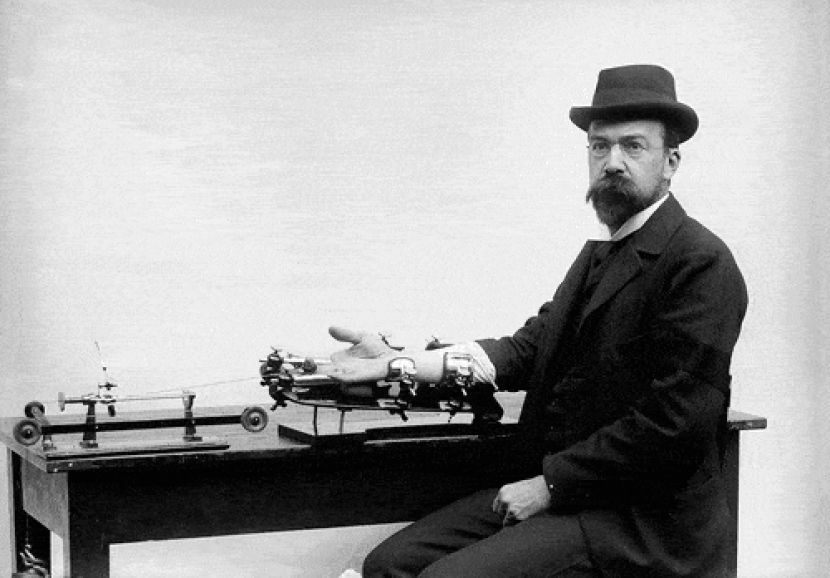Imam Indratno
Imam Indratno
Krisis Etika Pendidikan
Pendidikan dan Literasi | 2024-10-20 21:59:28Belakangan ini, sepertinya mengejar gelar akademis bagi kalangan elit sudah menjadi semacam ritual wajib—tanpa gelar, mereka seakan-akan tidak cukup dianggap "berpendidikan." Mulai dari gelar doktor yang diperoleh dalam waktu yang mencengangkan hingga profesor yang tiba-tiba muncul, fenomena ini menjadi tontonan menarik yang memancing rasa ingin tahu: apakah mereka benar-benar mengejar ilmu atau sekadar menambahkan deretan huruf di depan dan belakang nama untuk memperkuat citra pribadi?
Fenomena Elit Gila Gelar
Kalau kita bicara soal elit dan gelar akademis, banyak faktor yang bisa menjelaskan mengapa fenomena ini semakin menjamur. Pertama, gelar akademis secara otomatis meningkatkan legitimasi dan kredibilitas. Publik cenderung melihat pemimpin bergelar sebagai sosok pintar, kompeten, dan layak diandalkan. Semakin panjang gelarnya, semakin tinggi juga anggapan akan kemampuannya. Padahal, yang panjang belum tentu berkualitas, bukan?
Selain itu, gelar akademis juga menjadi senjata ampuh dalam persaingan politik. Di antara lautan elit, siapa yang berhasil meraih gelar lebih tinggi bisa mendapatkan nilai tambah di mata publik. Gelar bukan lagi soal keilmuan, tetapi soal branding. Bagi politisi yang merasa posisi mereka goyah, gelar adalah kartu AS. Bayangkan, "Saya sudah S3, Anda masih S1? Tenang, saya lebih kompeten." Persaingan di panggung politik ini lebih sering terasa seperti perlombaan penghargaan akademis ketimbang pertempuran gagasan.
Ada juga yang mengejar gelar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri. Beberapa mungkin benar-benar ingin memahami hukum, ekonomi, atau administrasi publik agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak sedikit juga yang bersembunyi di balik kursi kelas eksekutif, memperoleh gelar tanpa harus mengorbankan agenda politik harian. Akses pendidikan yang semakin mudah, terutama melalui program khusus bagi profesional, memungkinkan mereka mendapatkan gelar tanpa harus terlalu repot.
Jangan lupakan juga faktor ekspektasi publik. Masyarakat kita sering kali menilai kualitas pemimpin dari gelar akademisnya. Banyak yang berpikir, "Pemimpin bergelar doktor pasti lebih tahu segala hal." Harapan inilah yang mendorong elit untuk mengejar gelar demi memenuhi ekspektasi konstituen mereka. Gelar seolah menjadi syarat tak tertulis untuk memenangkan hati rakyat.
Dan, tentu saja, tak kalah penting adalah status sosial. Gelar akademis, terutama di tingkat pascasarjana, sering dilihat sebagai simbol status. Elit yang ingin memperkuat citranya di mata publik sering kali menjadikan gelar sebagai penanda "kemewahan" intelektual. Kembali ke logika sederhana: "Gelar lebih banyak, kedudukan lebih terhormat." Ironisnya, gelar tanpa kompetensi justru bisa menjadi bumerang yang berbahaya.
Proses atau Sekadar Formalitas?
Bagi akademisi sejati, melihat elit memperoleh gelar dengan cepat ibarat menyaksikan trik sulap yang ajaib. Bukan karena mengagumkan, tapi karena mengherankan bagaimana gelar yang seharusnya dicapai melalui proses panjang bisa diperoleh tanpa keringat dan air mata.
Akademisi paham bahwa gelar akademis bukan sekadar selembar kertas penghargaan. Gelar itu adalah simbol dari dedikasi, pemikiran kritis, penelitian yang melelahkan, serta jam-jam panjang yang dihabiskan di perpustakaan untuk menguji teori dan mencari kebenaran. Seorang akademisi mengorbankan banyak hal—waktu bersama keluarga, kesehatan mental, dan ketahanan fisik—untuk meraih gelar tersebut. Jadi, ketika elit tiba-tiba muncul dengan gelar yang didapat melalui jalur cepat, reaksi yang paling wajar dari akademisi adalah, "Seriusan, nih?"
Gelar akademis adalah bukti kerja keras, bukan sekadar aksesori untuk mempermanis kartu nama. Jika ada elit yang mendapatkannya dengan cara mudah, akademisi pasti merasakan sedikit getaran skeptis, dan muncul pertanyaan: "Apakah mereka benar-benar belajar?" Bagi akademisi, tanggung jawab moral dan intelektual adalah hal yang utama, bukan sekadar mengejar gelar untuk citra. Ini perbedaan mendasar: akademisi mengejar pengetahuan, sementara beberapa elit hanya mengejar penampilan.
Apa Kata Neurosains?
Mari kita lihat dari perspektif neurosains. Otak manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan, tidak hanya berkembang melalui penerimaan informasi, tetapi juga melalui proses belajar yang mendalam dan menantang. Jika gelar akademis hanya dijadikan formalitas, maka elit tersebut bukan hanya merusak proses pendidikan, tetapi juga melewatkan kesempatan penting untuk mengembangkan otaknya.
Dr. Michael Merzenich, seorang ahli dalam bidang neuroplastisitas, menjelaskan bahwa otak kita terus berubah melalui pengalaman baru dan pembelajaran yang sulit. Saat seseorang benar-benar terlibat dalam proses belajar yang menantang, otaknya membentuk jalur saraf baru yang lebih kuat. Ini adalah cara alami otak kita untuk beradaptasi dan berkembang. Jadi, ketika seorang elit hanya mendapatkan gelar tanpa benar-benar mempelajari sesuatu secara mendalam, mereka tidak memaksimalkan potensi otaknya.
Ilmuwan lain, Dr. Stanislas Dehaene (2020) menjelaskan bahwa otak manusia membutuhkan waktu dan kesulitan untuk memproses informasi baru. Belajar itu sulit, penuh dengan trial and error, dan inilah yang membuat pengetahuan terpatri dalam otak kita. Jika proses belajar ini dilompati, otak tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan penyerapan pengetahuan.
Jadi dari perspektif neurosains, pendidikan yang hanya dijalani untuk formalitas bukanlah pendidikan yang sejati. Proses belajar yang sesungguhnya adalah tentang membangun otak yang lebih baik, bukan hanya tentang menambah angka di belakang nama. Elit yang mengejar gelar tanpa proses belajar yang sesungguhnya bisa jadi melewatkan manfaat utama dari pendidikan itu sendiri: meningkatkan kemampuan berpikir dan analisis yang kritis.
Krisis Etika Pendidikan
Kita telah melihat betapa gelar akademis kini berubah menjadi sekadar alat untuk mendapatkan legitimasi politik. Dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi benteng pengetahuan, justru sering dipermainkan demi status dan citra pribadi. Gelar akademis, yang seharusnya melambangkan pencapaian intelektual, kini mudah diperjualbelikan. Inilah yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai krisis etika pendidikan.
Fenomena ini bukan sekadar lelucon, tetapi ancaman serius bagi kredibilitas institusi akademik. Dunia akademik yang seharusnya menjadi wadah pendidikan bermutu kini rusak oleh tren "gelar instan."
Langkah pertama yang harus diambil adalah institusi pendidikan, seperti Universitas Indonesia (UI), harus serius meninjau ulang fenomena pemberian gelar doktor yang dicapai dalam waktu sangat singkat, seperti gelar yang diperoleh hanya dalam 1 tahun 8 bulan. Kasus-kasus semacam ini seharusnya menjadi titik balik bagi lembaga pendidikan untuk mempertanyakan kembali standar mereka. Bagaimana mungkin sebuah gelar doktor—yang biasanya membutuhkan penelitian mendalam dan bertahun-tahun kerja keras—diberikan begitu cepat, bahkan dengan bantuan jurnal predator?
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, juga harus bertindak. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari manipulasi dunia akademik. Pemberian gelar harus diawasi dengan standar yang jelas dan transparan. Pemerintah harus menetapkan audit atau inspeksi untuk memastikan bahwa gelar yang diberikan mencerminkan kualitas dan dedikasi akademik. Tanpa langkah ini, gelar akademis hanya akan menjadi simbol yang kehilangan nilai.
Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga standar akademis. Pertama, mereka harus memperketat standar tanpa pandang bulu. Pintu khusus untuk tokoh berpengaruh yang tidak memenuhi persyaratan akademik harus ditutup. Jika institusi pendidikan terus melonggarkan standar demi keuntungan finansial atau reputasi, mereka secara langsung berkontribusi pada krisis etika pendidikan ini.
Kedua, penting bagi institusi pendidikan untuk mengembalikan makna gelar akademis sebagai hasil dari proses panjang, yang berorientasi pada pengembangan intelektual dan etika. Jika tidak, gelar akademis akan semakin kehilangan nilainya, dan dunia pendidikan akan terperosok lebih jauh dalam krisis ini.
Semoga di masa depan, gelar yang disandang sejalan dengan pembangunan otak yang memakainya...

Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.