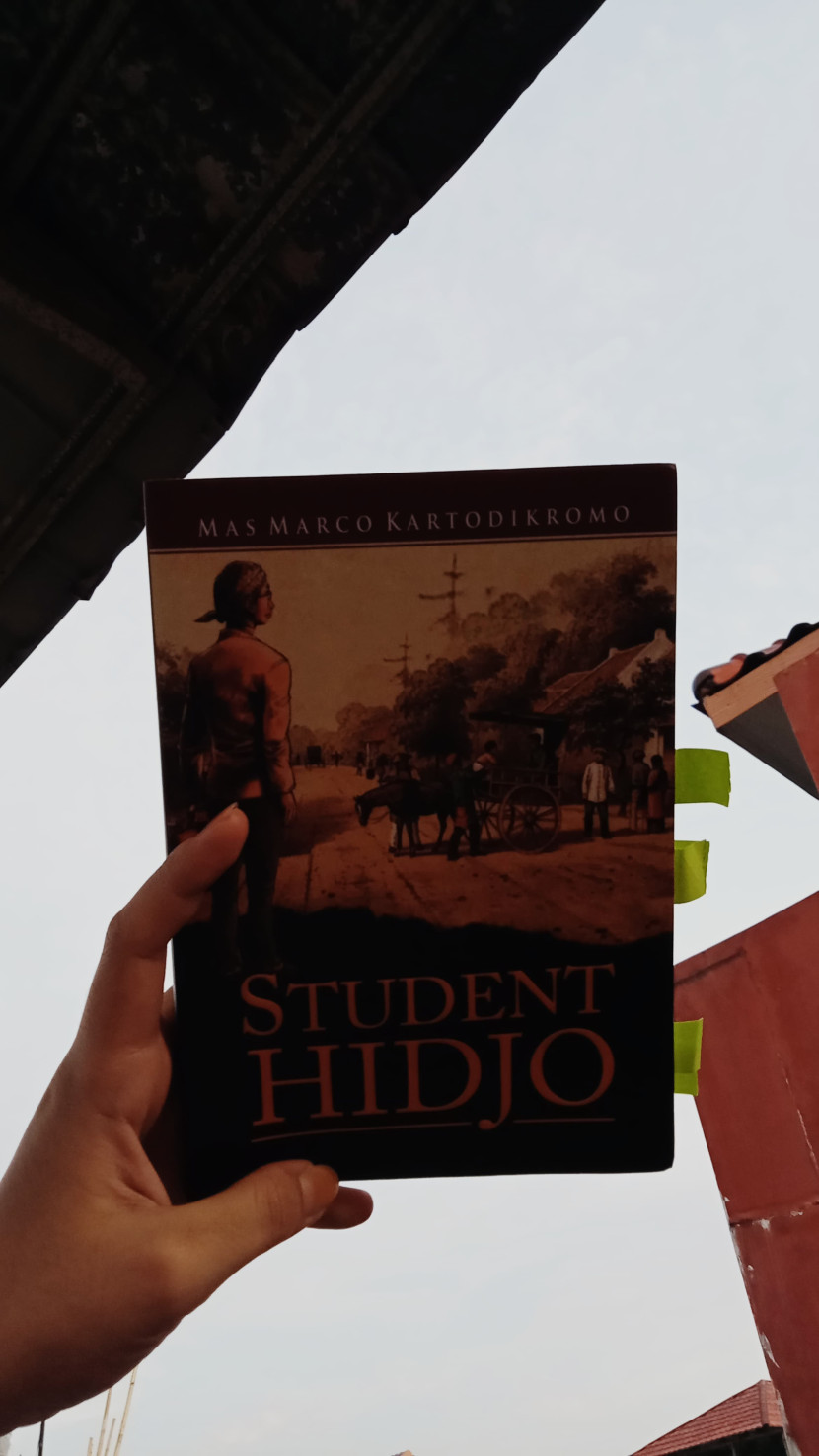Amalia Ardina
Amalia Ardina
Culture Shock Komunikasi Antar Budaya: Mengenal Low-Context Culture dan High-Context Culture
Gaya Hidup | 2024-06-09 01:21:20Microsoft Word - artikel kota.docx
Digitalisasi pesat yang terjadi saat ini membuka akses global, dimana manusia akan semakin terpapar dengan informasi, budaya, dan pandangan dari seluruh dunia. Hal ini membawa pengaruh baik secara positif dan negatif terhadap pertukaran budaya, pertumbuhan seseorang, dan pemahamannya akan lintas budaya. Namun kemudian masyarakat dihadapkan dengan tantangan berupa kompleksitas pada komunikasi antar budaya.
Jika mengacu pada konteks gaya komunikasi dilihat dari budaya suatu negara, hal ini dikategorisasikan menjadi dua bentuk, high-context culture dan low-contex culture. Singkatnya, budaya high-context gaya penyampaian pesan antara satu individu dengan lawan bicaranya secara implisti. Yang dimaksud implisit di sini adalah pesan di sampaikan tidak secara langsung, melainkan dengan penggunaan tanda-tanda non-verbal dan bergantung pada konteks pembicaraan serta setting seperti situasi, suasana, tensi, dan kecepatan interaksi. Sementara budaya low-context menekankan pada gaya komunikasi eksplisit, verbal, langsung pada inti dari pesan yang ingin disampaikan. (Samovar dkk, 2014, hal. 23
 Lihat karya qiesnusantara26 yang lain dari pixabay" />
Lihat karya qiesnusantara26 yang lain dari pixabay" />
Menurut E.T Hall (2020) dalam bukunya, negara-negara dengan latar belakang budaya kolektivisme umumnya menerapkan budaya high-context. Hal ini dikarenakan masyarakatnya terbiasa untuk memahami suatu pesan tanpa harus diucapkan atau diterima secara eksplisit (gamblang) dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dinamika bermasyarakat. Bukan berarti masyarakat di negara budaya kolektivisme tidak menggunakan komunikasi verbal, perbedaannya adalah terletak pada penekanan dan memaksimalkan penggunaan tanda. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Sementara negara yang menerapkan budaya low- context seperti Amerika dan Australia.
Perbedaan gaya komunikasi yang cukup kontras ini kerap menimbulkan kesenjangan. Mayoritas masyarakat penganut budaya low-context akan kesulitan dalam memahami pesan individu dengan budaya high-context yang dianggap berbelit dan berpotensi berujung pada miskomunikasi. Di lain sisi, bagi individu dari budaya high-context tidak terbiasa dengan cara penyampaian pesan individu budaya low-context. Hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya persepsi tertentu seperti ketus dan cenderung kasar.
Contoh dari fenomena persinggungan ini dapat dilihat melalui pengalaman langsung mahasiswa Indonesia yang pernah menjalani studi di luar negeri yang mengalami gegar budaya atau yang populer dengan istilah culture shock. Seorang mahasiswa asal Indonesia yang mengenyam pendidikan di University of Washington bernama Leonardo Edwin. Melalui konten kolaborasinya dengan Youtuber Jerome Polin, Leo menceritakan culture shock yang dialaminya ketika menjalani studi di salah satu provinsi di Amerika tersebut. Leo mengatakan bahwa dinamika pertemanan antar sesama mahasiswa di Amerika sangat berbeda dengan Indonesia yang cenderung berkelompok.
Kalo di US itu, kita tuh kenalan Cuma di kelas dan karena ada tugas aja, habis itu udah. Kalau di luar kelas, kayak nggak kenal aja. Jadi biasanya, aku yang selalu nyapa deluan, tapi dianya nggak nyapa balik. (Edwin, 2019)
Culture shock akibat perbedaan gaya komunikasi tersebut dapat dijabarkan dengan sejumlah faktor seperti gaya komunikasi antar negara, bahasa, latar belakang budaya, pola asuh orang tua, kebiasaan, perilaku, dan lain sebagainya. Bila ditarik benang merah, terdapat hubungan yang mengaitkan budaya dengan pola asuh orangtua. Menurut John W. Berry (2012) dalam bukunya yang berjudul Cross-cultural Psychology, hal ini dijelaskan melalui teori cultural variation in infant development.
Disebutkan bahwa perkembangan individu ketika lahir bergantung pada proses adaptasinya dengan relung ekologi tertentu. Perkembangan neurologis yang berlanjut setelah lahir memungkinkan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu menjadi signifikan. Barulah dilanjutkan dengan perkembangan lainnya yang dilatarbelakangi oleh pola interaksi orang tua dan bayinya. Salah satunya penggunaan pola intonasi bicara khusus yang digunakan ibu dengan bayinya berbeda dengan yang dilakukan ayahnya. Umumnya, ibu menyapa bayi dengan nada yang lebih tinggi dan variasi nada yang lebih besar, ini disebut dengan “motherese”. Penjelasan ini membantu kita memahami bagaimana gaya komunikasi orang tua (keluarga) menurun kepada anak-anaknya. Orang tua degan gaya komunikasi high-context berkemungkinan besar mewariskan budaya tersebut kepada anaknya.
Dengan melakukan wawancara oleh Kansa yaitu warga Indonesia yang sudah menetap lama di Jepang, kansa mengatakan bahwa Pola asuh di Indonesia cenderung lebih menjerumus pada high context contohnya, orang tua di Indonesia sering kali menggunakan kode non verbal, ekspresi wajah dalam situasi tertentu untuk menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, Norma- norma Budaya, seperti hormat kepada orang tua dan kelompok, sering kali ditekankan, dan Komunikasi cenderung lebih tidak langsung dan bergantung pada hubungan interpersonal yang kuat. Pola asuh di Jepang juga cenderung pada high context tetapi ada yang membedakannya yaitu Komunikasi antara orang tua dan anak cenderung tidak langsung, dengan penekanan pada, ekspresi emosi dan pemahamannya terhadap konteks sosial, Norma-norma budaya, seperti rasa hormat kepada orang tua dan otoritas, sangat ditekankan, lalu Hubungan keluarga dan nilai-nilai tradisional sering kali menjadi fokus utama dalam pola asuh.
kita dapat melihat bagaimana hubungan awal individu dengan figur pengasuhnya mempengaruhi cara mereka merespons dan beradaptasi dengan lingkungan budaya yang baru. Individu yang memiliki ikatan aman dengan figur pengasuhnya mungkin lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan budaya baru karena mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat dan kepercayaan diri yang stabil. Di sisi lain, individu yang memiliki pola attachment yang tidak aman, seperti pola attachment yang ambivalen atau menghindar, mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan budaya baru karena mereka lebih rentan terhadap perasaan ketidaknyamanan atau kecemasan, Menurut (Bowlby, 1968), perilaku bayi manusia, seperti menangis dan tersenyum, tidak hanya merupakan respons fisiologis biasa, tetapi juga merupakan cara komunikasi yang penting dengan orang dewasa di sekitarnya, terutama dengan ibu atau figur pengasuh utama lainnya. Bayi menggunakan perilaku ini untuk mengungkapkan kebutuhan, keinginan, atau emosi mereka. di jelaskan melalui teori attachment pattern.
Baik Jepang maupun Indonesia memiliki budaya yang sangat menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Namun, di Jepang, organisasi sosial dan penghargaan terhadap otoritas cenderung lebih kuat dari pada di Indonesia. Komunikasi dalam budaya Jepang sering kali lebih formal, dengan penekanan pada bahasa kehormatan dan penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Contohnya Dalam percakapan sehari-hari di Jepang, penggunaan bahasa kehormatan (keigo) sangat umum. Contohnya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, orang Jepang
akan menggunakan kata-kata yang menunjukkan rasa hormat, seperti menggunakan akhiran -san atau -sama setelah nama mereka. Misalnya, seorang karyawan mungkin akan menggunakan bahasa kehormatan saat berbicara dengan atasannya di tempat kerja. Penelusuran lebih jauh pola keterikatan pada kehidupan dewasa diperkirakan tercermin dalam perawatan orang tua lanjut usia yang membutuhkan bantuan (misalnya, Ho, 1996; Marcoen, 1995; Marcoen, Grommen dan Van Ranst, 2006).
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.