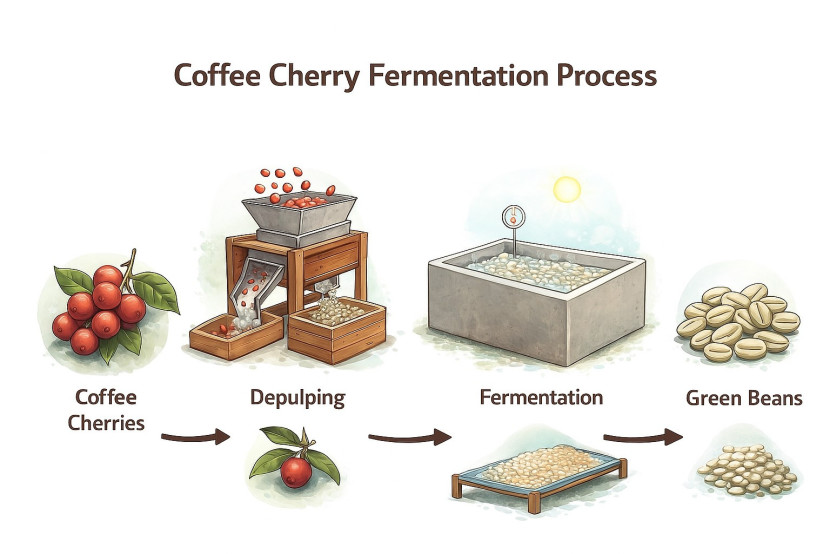RESNASARI ANDINI
RESNASARI ANDINI
Gak Usah Ngopi Kalau Masih Gengsi
Gaya Hidup | 2022-01-08 10:45:01
Sejak munculnya film yang berjudul Filosofi Kopi pada tahun 2015, industri kedai kopi di Indonesia mulai menjamur dimana mana, hal ini ditandai dengan munculnya banyak pengusaha lokal yang membangun bisnis kopi. Sehingga membuat kedai kopi menjadi salah satu destinasi tongkrongan anak muda kekinian sehingga menjadi tren.
Kopi banyak dikaitkan dengan musik indie, buku bahkan hingga muncul ciri khas “anak kopi, anak senja” karena terdapat sensasi yang berbeda jika minum kopi dan diiringi lagu beraliran indie.
Namun tentu disetiap industri ada naik dan turunnya, sama seperti bisnis kopi, sejak pandemi Covid-19 ternyata mengalami penurunan yang cukup drastis namun saat ini kembali pulih karena orang sudah boleh melakukan aktivitasnya di luar rumah, salah satunya nongkrong di tempat kopi. Menurut riset Kementerian Pertanian RI menjelaskan, konsumsi kopi nasional hanya 370 ton di tahun 2021,hal ini tak sebanding dengan pasokan kopi nya yang hampir 790 ribu ton, terdapat surplus 425 ribu ton yang terbengkalai.
Jika melihat dari data tersebut, yang jadi pertanyaan, mengapa pasokan kopi menurun sedangkan bisnis kedai kopi saat ini menjamur?
Hal ini berkaitan dengan gaya hidup setiap orang saat ini. Banyak orang yang nongkrong di tempat kopi namun mereka hanya ingin mengejar gengsi, ditambah dengan media sosial yang berkembang pesat membuat orang bisa dengan mudahnya mengetahui apa yang orang lain lakukan. Dari sinilah muncul FoMo atau Fear of Missing Out.
Menurut Departemen of Psychology of School of Social Sciences, Nottingham Trent University Inggris, FoMO adalah suatu kondisi yang bisa menyebabkan orang berlaku diluar batas kewajarannya. FoMO ini menimbulkan depresi, kecemasan bahkan stress.
Dengan orang melihat sesuatu hal yang menarik di instagram, orang itu menjadi terinspirasi atau tertarik dan merasa tidak ingin tertinggal dari orang sekitarnya. Tak jarang orang berpikir pendek dan langsung mengunjungi tempat kopi tersebut. Padahal mereka tak tau esensi dari kopi itu apa bagaimana dan seperti apa. Bahkan tak jarang pula sebenarnya mereka yang datang tidak menyukai kopi. Mereka hanya ingin mendapat gelar anak hits yang mampu dan bisa nongkrong di kedai kopi.
Didukung dengan sudah menjadi “tren” bahkan menjadi gaya hidup kelas menengah karena tentu harga secangkir kopi cukup menguras kantong bagi pelajar atau mahasiswa. Bisa kita lihat saja, harga kopi pun beragam. Bahkan orang berani merogoh kocek yang cukup besar hanya untuk sekedar ngopi. Hal ini tentu dapat berpengaruh kepada gaya hidup lainnya.
Bahkan saya pernah mendengar ada seseorang berkata "gak nongkrong, gak happy". Seolah menggeneralisasi bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai ketika nongkrong. Saya pernah bertanya pada seorang anak, dirinya menabung bukan untuk masa depan, tetapi untuk sekedar nongkrong di tempat kopi.
Kini, kedai kopi tak hanya menawarkan varian menu kopi atau makanan dan minuman tambahan, tetapi menawarkan tempat yang nyaman dan instagramable atau suasana yang estetik sehingga jika orang berfoto di tempat kopi tersebut, berharap bisa menghasilkan foto yang bagus dan menarik.
Dengan begitu, semakin berkembangnya media sosial semakin banyak pula orang dapat melihat apa yang orang lain lakukan, tak jarang hal ini memunculkan rasa iri bahkan tak bersyukur dengan keadaan karena terlalu banyak melihat orang lain.
Dilihat dari jurnal Harmoni Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, menyebutkan bahwa ritual potret makanan pada media sosial berfungsi untuk mendelegasikan image tertentu yang berguna untuk menampilkan status sosial dan meraih prestige dari sesama pengguna platform tersebut.
Selain itu, karena ini merupakan sebuah industri tentu berhubungan dengan branded. Akan berbeda rasanya orang yang nongkrong di Starbucks dengan orang yang hanya nongkrong di kedai kopi biasa yang brand nya belum terlalu terdengar. Disini pun bisa memunculkan strata kelas kelas karena harga kopi di Starbucks dengan lainnya berbeda, namun sebenarnya secara kualitas banyak yang bisa menandingi
Namun jika kita lihat di sisi lain, FoMO ini dari sisi bisnis tentu menjadi sangat menguntungkan. Dengan adanya sikap tak ingin tertinggal membuat orang orang menjadi ingin terus membeli produk mereka. Namun jika dilihat dari aspek psikis manusia tentu hal ini berdampak buruk pada kesehatan karena menimbulkan kecemasan, stress, bahkan depresi.
Dengan media sosial pula, jika dilihat dari segi bisnis pembeli bukan lagi sebagai raja, namun pembeli merupakan ambasador karena dengan gratisnya orang mereview sendiri tempat bahkan makanan yang mereka nikmati dan disebar di media sosialnya. Jika kita lihat ini merupakan perpindahan tren, yang mana biasanya untuk mempromosikan tentu harus ada talent yang harus dibayar mahal. Namun ini tidak, mereka justru dengan sukarela menjadi ambasador tempat kopi itu. Namun, apakah benar mereka rela melakukan hal itu? Atau agar mendapat validasi dari orang sekitarnya agar bisa terpandang menjadi kaum elit?
Tentu jika ini hanya karena gengsi, apa esensi itu menjadi tak berfungsi?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.