 Assist. Prof. Dr. Hisam Ahyani.
Assist. Prof. Dr. Hisam Ahyani.
Hukum Islam dan Pranata Sosial
Agama | 2023-05-02 15:09:54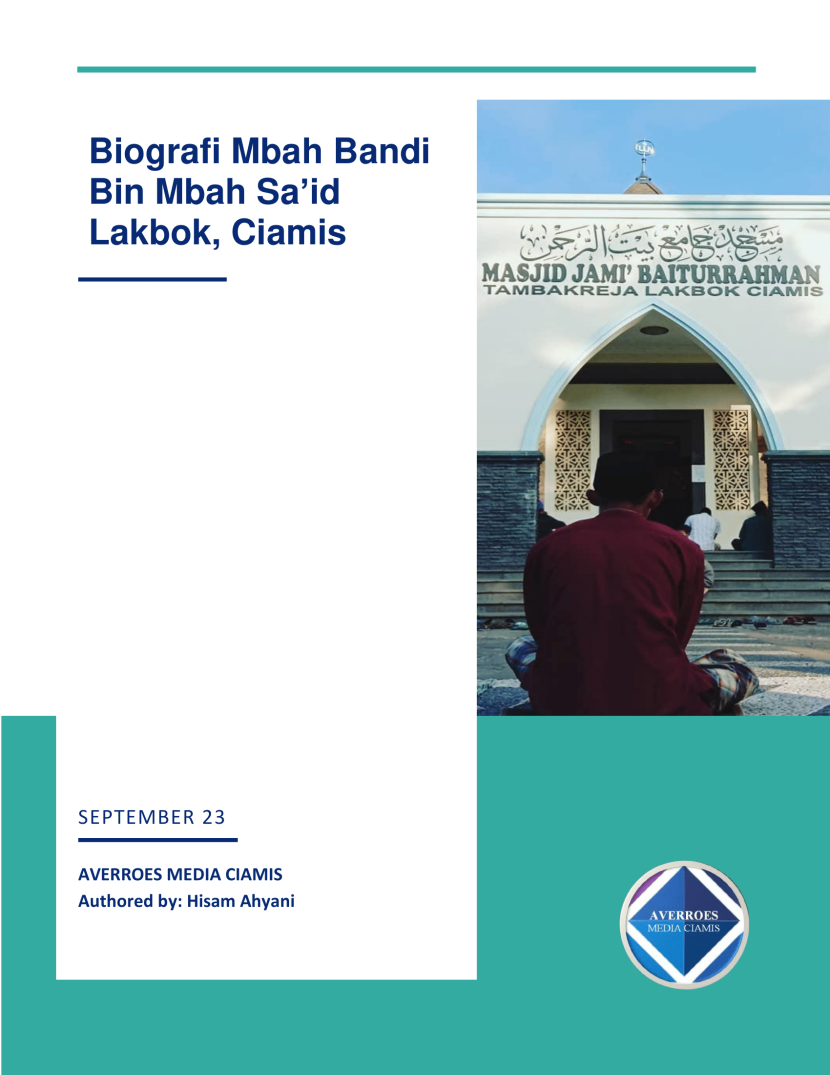
HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL
Oleh : Hisam Ahyani
STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat
Hukum Islam dan pranata sosial mengandung arti normatif dalam penataan kehidupan bermasyarakat yang berpangkal dan penerimaan terhadap sumber ajaran Islam. Hukum deduksi dari pra penataan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam suatu komunitas (Naskur 2016). Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya yang berjudul Pranata Sosial Hukum Islam menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib ditunaikan apabila sudah mencapai batas nishab dan wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syari’at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mukhlas 2015, 23). Selanjutnya Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil menegaskan bahwa zakat merupakan bukti keimanan dan wujud rasa syukur, menghilangkan kemiskinan, menggugah etos kerja, dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT (Ridwan 2013, 144).
Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan (Ali, Amalia, dan El Ayyubi 2016, 19–32). Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata sosial dari yang terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki). Dalam hal ini, muzakki dapat meminta bantuan kepada Bendahara Satker atau Unit pengumpul distribusi Zakat Profesi dilingkungan Polda dan Polres jajaran.
Idealnya, dalam pengumpulan zakat profesi menyediakan panduan dalam menghimpun dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat (Wiradifa dan Saharuddin 2017, 1–18). Distribusi zakat profesi sama dengan zakat mal lainnya, sebab ia termasuk dalam kelompok zakat mal. Berdasarkan dalil-dalil yang ada zakat dapat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu bentuk komsumtif dan produktif. Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59): 7 yang berbunyi :
مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ
Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia 2018, 546).
Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya yang berjudul Pranata Sosial Hukum Islam menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib ditunaikan apabila sudah mencapai batas nishab dan wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syari’at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mukhlas 2015, 23). Selanjutnya Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil menegaskan bahwa zakat merupakan bukti keimanan dan wujud rasa syukur, menghilangkan kemiskinan, menggugah etos kerja, dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT (Ridwan 2013, 144).
Dalam hukum dan sosiologi sebagai disiplin pemikiran dan bentuk praktik profesional memiliki ruang lingkup yang sama. Namun, mereka sangat berbeda dalam tujuan dan metode mereka. Hukum sebagai disiplin ilmu berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah wajib dan teknis, sedangkan sosiologi berfokus pada studi ilmiah tentang fenomena sosial (Cotterrel 2012, 6). Sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang menggunakan teknik empiris. Hal ini berkaitan dengan instrumen hukum dengan tugasnya, ia melihat hukum sebagai produk dari sistem sosial dan instrumen untuk mengontrol dan mengubah sistem (Shalihah 2017, 6). Soejono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Artinya, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan hukum (Tebba 2003, 1).
Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Mariani 2019). Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Efektivitas atau berfungsinya hukum sangat bergantung pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tadi. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum rakyat banyak sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai dan di taati (Soekanto dan Abdullah 1987, 216).
Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Pranata sosial sering disebut sebagai lembaga sosial. Contoh pranata sosial antara lain pranata keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, sejatinya manusia memiliki kesempatan untuk berpindah dari satu pranata ke pranata lain. Setidaknya di dalam masyarakat terdapat lima pranata atau lembaga sosial yang pokok, yaitu: (1) keluarga, (2) pendidikan, (3) ekonomi, (4) politik, dan (5) agama. Tujuan dan fungsi pranata sosial adalah memberi pedoman pada anggota masyarakat mengenai cara bertingkah laku atau bersikap dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya; Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman disintegrasi atau perpecahan; Memberikan pedoman dalam melakukan pengedalian sosial. Fungsi pranata sosial adalah sebagai: (1) pedoman masyarakat dalam ber-tingkah laku dan bersikap, (2) upaya untuk menjaga keutuhan masyarakat, (3) pegangan masyarakat untuk mengendalian sosial/social control. Menurut (Rosyada 1999)Persoalan Hukum Islam dan Pranata Sosial yang mengacu pada pemikiran dan tradisi masa lalu dan pemikiran sekarang dengan cakupan Pengertian syariah, fiqh, hukum islam dan pembagiannya, sumbe hukum islam, Ushul Fiqih, Ijtihad yang rasionalis dan tradisional. Dalam hukum islam misalnya (Ahyani, Slamet, dan Tobroni 2021) dalam risetnya mengatakan bahwa tujuan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat (falah) serta konsep triangle antara filsafat Tuhan, manusia dan alam, misalnya, memungkinkan tertutupinya kekurangan dalam sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam.
Daftar Pustaka
Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Tobroni. 2021. “Building the Values of Rahmatan Lil ’Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law.” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 16 (1): 111–36. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550.
Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi. 2016. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” Al-Muzara’ah 4 (1): 19–32. https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32.
Cotterrel, Roger. 2012. Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law) penerjemah, Narulita Yusron; penyunting, Nurainun Mangunsong. Bandung: Nusa Media.
Mariani, Mariani. 2019. “Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas.” Phinisi Integration Review 2 (2): 281. https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006.
Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2015. Pranata Sosial Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama.
Naskur, Naskur. 2016. “Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Sebuah Kajian Makna Teks Nash).” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 1 (2). https://doi.org/10.30984/as.v1i2.195.
Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Bandung: Pustaka Setia.
Rosyada, Dede. 1999. Hukum Islam Dan Pranata Sosial : Dirasah Islamiyah III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Shalihah, Fithriatus. 2017. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soejono, dan Mustafa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.
Tebba, Sudirman. 2003. Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. Al-Qur’an, Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi. Jakarta: Beras Alfath.
Wiradifa, Riyantama, dan Desmadi Saharuddin. 2017. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3 (1).
Lihat Artikel Selengkapnya Klik Disini
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.


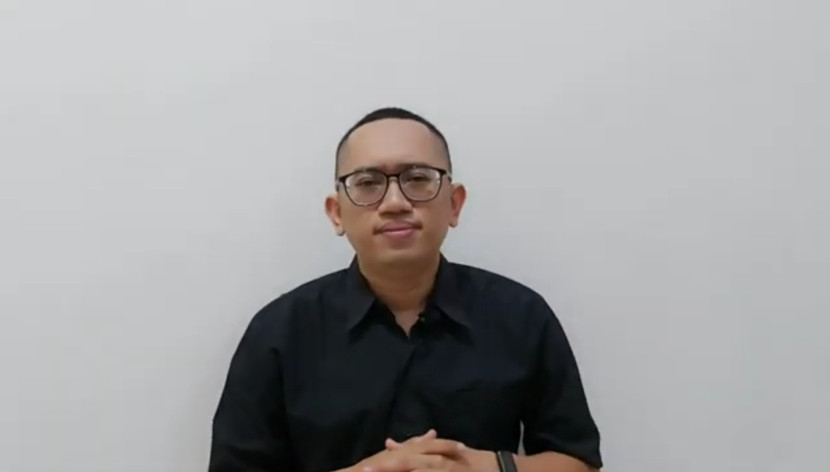






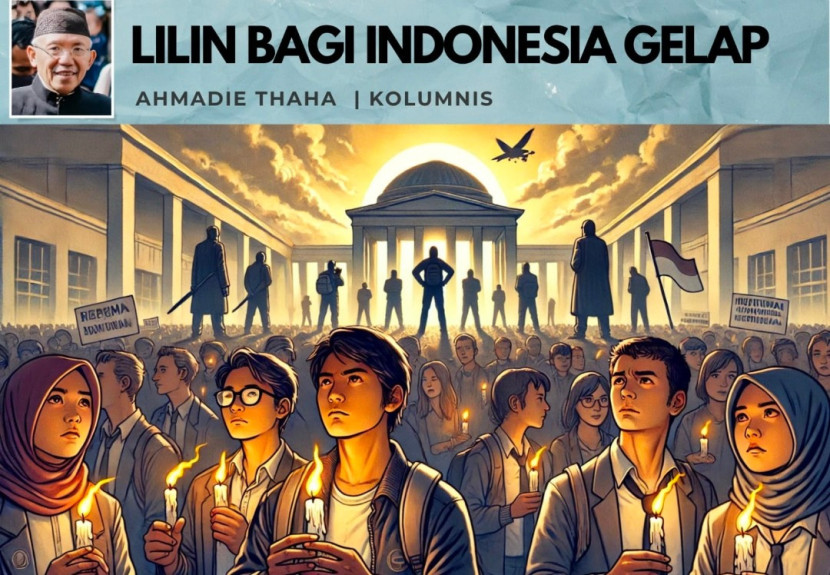

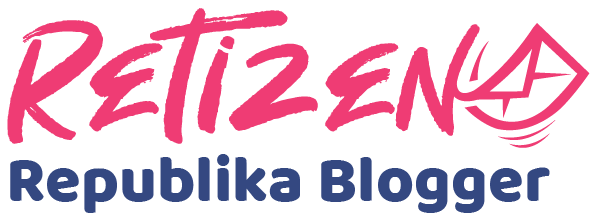
Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook