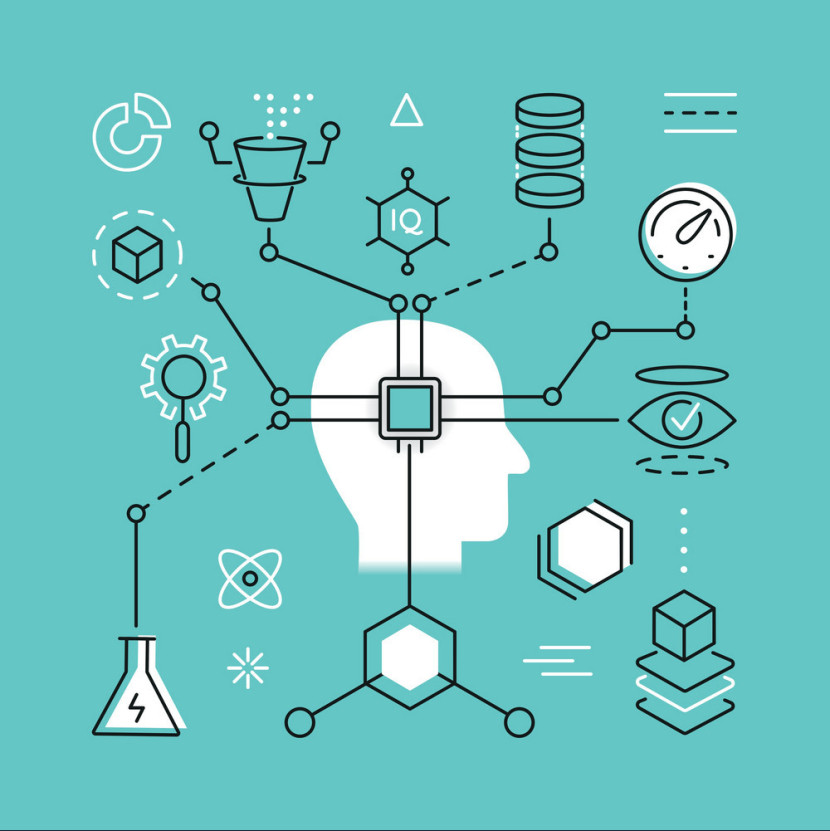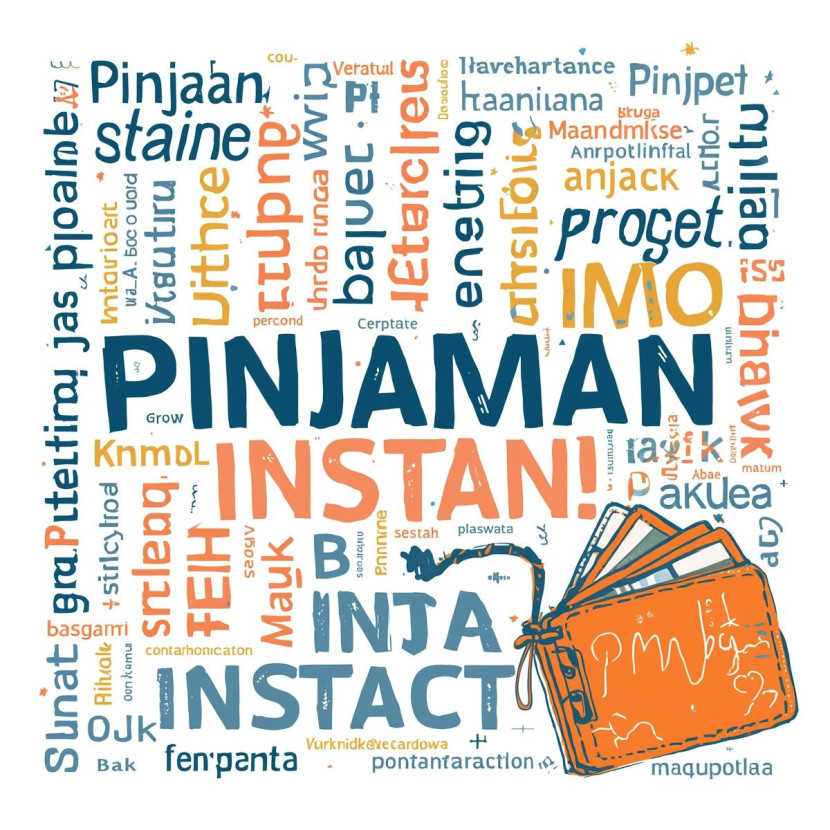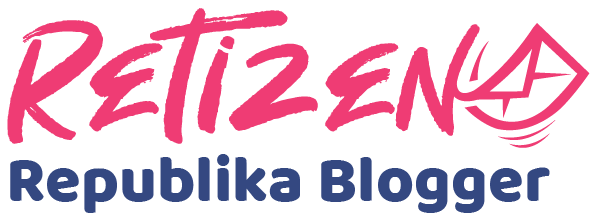Sirilus Aristo Mbombo_Pengamat Realitas
Sirilus Aristo Mbombo_Pengamat Realitas
Menelaah Filsafat Politik
Politik | 2024-06-28 13:49:35
Filsafat adalah bidang studi yang mendalami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, alasan, pikiran, dan bahasa. Secara etimologis, istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua kata, yaitu "philia" dan "sophia." Kata "philia" dapat diterjemahkan sebagai "cinta," sedangkan "sophia" berarti "kebijaksanaan." Jadi secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.
Dalam konteks ini, cinta akan kebijaksanaan bukan hanya sekadar memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang sudah mapan, melainkan lebih kepada sebuah dorongan dan semangat untuk terus-menerus mencari, memahami, dan mendalami kebijaksanaan tersebut. Seorang filsuf atau orang yang berfilsafat adalah individu yang memiliki kecintaan mendalam terhadap kebijaksanaan. Ia bukanlah seseorang yang mengklaim telah mencapai puncak kebijaksanaan, melainkan seseorang yang selalu berada dalam perjalanan intelektual untuk menemukan dan memahami kebenaran dan kebijaksanaan secara lebih mendalam. Dengan demikian, filsafat adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan, di mana pencarian dan pemahaman kebijaksanaan tidak pernah benar-benar berakhir, melainkan selalu berkembang seiring dengan perjalanan intelektual dan refleksi mendalam yang dilakukan oleh para filsuf.
Menurut pandangan saya, filsafat lebih dari sekadar mata kuliah yang diajarkan di institusi pendidikan. Filsafat adalah sebuah aktivitas intelektual yang melibatkan proses berpikir yang mendalam dan reflektif tentang berbagai aspek realitas. Meskipun filsafat secara formal diakui sebagai salah satu disiplin akademik, esensinya melampaui batasan-batasan ruang kelas dan kurikulum.
Secara lebih mendetail, filsafat dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir manusia yang mencakup pemahaman terhadap segala sesuatu yang ada di dalam realitas. Aktivitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang yang paling mendasar dan esensial dari berbagai fenomena yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam filsafat bersifat terbuka, artinya siap untuk menerima berbagai perspektif dan pandangan baru. Pendekatan ini juga bersifat kritis yang berarti selalu siap untuk menguji dan mengevaluasi asumsi-asumsi yang ada. Selain itu, filsafat dilakukan secara sistematis dengan mengikuti metode dan langkah-langkah yang terstruktur. Akhirnya, filsafat bersifat rasional mengandalkan logika dan pemikiran yang sehat dalam proses pencariannya.
Dalam ranah filsafat, tidak ada batasan topik yang dibahas. Filsafat mencakup berbagai bidang, mulai dari tata sosial, sistem ekonomi, dan budaya hingga seni, kemanusiaan, alam semesta, dan bahkan konsep tentang Tuhan. Setiap aspek kehidupan dan realitas dapat menjadi objek kajian filsafat. Dengan demikian, filsafat tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga membentuk cara berpikir yang kritis dan analitis yang berguna dalam memahami dan merespons kompleksitas dunia di sekitar kita.
Namun, tidak seperti ilmu-ilmu empiris yang cenderung fokus pada aspek-aspek teknis dalam disiplin masing-masing dan sering kali kurang memperhatikan interaksi dengan disiplin ilmu lain, filsafat mengambil pendekatan yang berbeda dalam memahami berbagai fenomena. Filsafat berusaha untuk menguraikan dan mengeksplorasi aspek-aspek dasar dari berbagai fenomena tersebut. Proses penguraian ini dilakukan dengan cara yang terbuka, kritis, rasional, dan sistematis.
Sebagai contoh, jika saya ingin memahami manusia melalui lensa filsafat, pendekatan ini akan berbeda dari pendekatan yang digunakan dalam psikologi atau antropologi. Dalam psikologi, manusia dipahami sebagai agen yang menunjukkan perilaku tertentu. Pendekatan dalam psikologi sering kali melibatkan pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, pengolahan data tersebut menggunakan metode statistik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis empiris. Penelitian dalam psikologi sebagian besar berfokus pada dimensi empiris dari perilaku manusia, seperti reaksi terhadap stimulus tertentu, pola pikir, dan emosi yang dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif.
Di sisi lain, filsafat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan analisis data empiris. Filsafat mencoba untuk memahami manusia dari perspektif yang lebih mendasar dan menyeluruh. Pendekatan filosofis mempertanyakan dan mengeksplorasi konsep-konsep dasar seperti eksistensi, identitas, kesadaran, dan moralitas. Misalnya, filsafat mungkin bertanya apa artinya menjadi manusia, apa hakikat kesadaran, bagaimana kita memahami identitas diri, atau apa dasar-dasar etika dan moralitas. Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui pengamatan empiris dan mengharuskan refleksi yang mendalam dan analisis kritis.
Dengan demikian, pendekatan filosofis terhadap pemahaman manusia melibatkan penguraian dan eksplorasi konsep-konsep fundamental yang sering kali tidak tersentuh oleh pendekatan empiris. Filsafat menggunakan metode yang sistematis dan rasional untuk membongkar dan menganalisis aspek-aspek dasar dari berbagai fenomena, menawarkan wawasan yang lebih luas dan mendalam yang melengkapi pemahaman yang diperoleh dari disiplin ilmu empiris.
Pendekatan filsafat tidak dilakukan dengan cara empiris, seperti yang sering dilakukan dalam ilmu-ilmu lain yang melibatkan pengumpulan data, pengolahan statistik, dan penarikan kesimpulan sementara berdasarkan data tersebut. Sebaliknya, filsafat mendekati manusia dengan cara reflektif dan analitis. Data empiris hanya digunakan sebagai titik awal untuk menggali dan memahami apa yang menjadi esensi paling mendasar dari manusia.
Dalam filsafat, data empiris berfungsi sebagai pijakan awal, tetapi tujuan utamanya adalah menembus dan melampaui data tersebut untuk menemukan hakikat terdalam dari eksistensi manusia. Oleh karena itu, filsafat sering dianggap lebih radikal dibandingkan dengan psikologi dalam upayanya memahami manusia, karena filsafat tidak hanya berhenti pada analisis data empiris tetapi juga mempertanyakan dan mengeksplorasi makna dan dasar-dasar eksistensial manusia.
Ellias Canetti, seorang filsuf-antropolog asal Eropa Timur, pernah menyatakan bahwa di balik semua lapisan peradaban, manusia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hewan. Menurut Canetti, perilaku dan sifat-sifat manusia sering kali menunjukkan gejala yang mirip dengan hewan. Misalnya, manusia bisa berkumpul dan bertindak seperti kawanan tawon ketika menyerang musuh, sebuah fenomena yang dapat dilihat dalam perkelahian massal. Manusia juga bisa melakukan tipu muslihat dengan mudah, seperti rubah yang menipu manusia dengan gerak-geriknya.
Psikolog dan antropolog umumnya tidak akan berani menarik kesimpulan sejauh itu tanpa melibatkan perspektif filosofis. Namun, pendekatan filsafat memungkinkan eksplorasi dan penarikan kesimpulan yang lebih mendalam dan mendasar tentang hakikat manusia. Di era sekarang, pendekatan interdisipliner mulai menjadi acuan untuk memahami berbagai fenomena di dunia, menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, dan antropologi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh.
Tujuannya adalah agar data yang diperoleh dapat diolah dari berbagai perspektif, menghasilkan pemahaman baru yang inovatif. Filsafat, oleh karena itu, merupakan pendekatan terhadap realitas dengan berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, dan rasional.
Terbuka berarti proses filsafat tidak pernah mencapai akhir. Kritis berarti filsafat mampu mempertanyakan segala hal, termasuk dirinya sendiri. Sistematis berarti filsafat harus menarik kesimpulan berdasarkan prinsip koherensi tanpa melanggar logika. Rasional berarti filsafat tidak mengacu pada iman, sentimen, atau perasaan, tetapi pada kemampuan akal budi manusia untuk memahami realitas.
Pendekatan Filsafat
Dalam pendekatan filosofis, Filsafat mendekati manusia dengan cara reflektif dan analitis, menggunakan data empiris sebagai titik awal untuk menggali dan memahami apa yang menjadi esensi paling mendasar dari manusia.
Filsafat tidak hanya memanfaatkan data sebagai titik awal, tetapi juga melampaui data tersebut untuk menemukan hakikat terdalam dari eksistensi manusia. Oleh karena itu, filsafat sering dianggap lebih radikal dibandingkan dengan psikologi dalam upayanya memahami manusia. Dalam filsafat, proses berpikir dilakukan secara terbuka, kritis, sistematis, dan rasional. Terbuka berarti filsafat merupakan proses yang tidak pernah mencapai titik akhir selalu siap menerima perspektif baru. Kritis berarti filsafat mempertanyakan segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Sistematis berarti filsafat didasarkan pada kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip koherensi tanpa menyalahi aturan logika. Rasional berarti filsafat tidak mengacu pada iman, sentimen, atau perasaan, tetapi sepenuhnya mengandalkan kemampuan akal budi manusia untuk memahami realitas.
Filsafat Politik
Filsafat politik adalah refleksi filosofis tentang bagaimana kehidupan bersama diatur. Hal ini mencakup tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, tata ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan bersama lainnya. Menurut Routledge Encyclopedia of Philosophy seorang filsuf politik berusaha merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi suatu bentuk negara tertentu. Mereka juga sering menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa ditolak keberadaannya.
Di bidang ekonomi, banyak filsuf politik mengajukan ide dasar tentang pembagian kekayaan ekonomi yang adil kepada seluruh warga negara. Refleksi filosofis dalam bidang ini melibatkan penafsiran ulang prinsip-prinsip hidup sosial seperti keadilan, kebebasan, dan kekuasaan serta mengaplikasikannya secara kritis pada kondisi sosial politik yang sedang terjadi. Beberapa filsuf politik mencoba memberikan justifikasi bagi berdirinya suatu pemerintahan tertentu, sementara yang lain memberikan kritik tajam terhadap kondisi sosial politik yang ada dan merumuskan bentuk negara ideal yang mungkin berbeda dengan pengalaman empiris yang ada.
Filsafat politik lahir sejak manusia mulai menyadari bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang alami, tetapi sesuatu yang bisa diubah. Tata social, ekonomi, politik merupakan produk budaya yang memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya. Refleksi filsafat politik sangat dipengaruhi oleh konteks epistemologi dan metafisika zamannya, dan pada gilirannya, juga mempengaruhi zamannya. Lingkaran dialektis ini berlangsung terus menerus dalam sejarah.
Perkembangan Filsafat Politik
Perkembangan dalam epistemologi dan metafisika mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan oleh para filsuf politik untuk merumuskan pemikirannya. Pada abad pertengahan, banyak filsuf politik menggabungkan refleksi teologi Kristiani dengan filsafat Yunani Kuno untuk merumuskan refleksi filsafat politik mereka. Filsafat politik sering kali muncul sebagai tanggapan terhadap situasi krisis zamannya. Misalnya, pada era abad pertengahan, relasi antara negara dan agama menjadi tema utama filsafat politik. Pada era modern, tema pertentangan antara kekuasaan absolut dan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi menjadi tema utama refleksi filsafat politik. Pada abad ke-19, pertanyaan tentang bagaimana masyarakat industri harus menata ekonominya menjadi tema utama filsafat politik.
Dalam sejarah filsafat politik, beberapa pertanyaan abadi selalu menjadi pergulatan para filsuf. Misalnya, bagaimana seseorang bisa mendaku otoritas untuk memerintah orang lain? Apakah suatu prinsip yang dirumuskan oleh seorang filsuf politik memiliki keabsahan universal yang berlaku lintas zaman dan tempat atau hanya merupakan ekspresi dari nilai-nilai partikular suatu komunitas tertentu?
Aspek Antropologis dalam Filsafat Politik
Suatu rumusan filsafat politik haruslah didasarkan pada konsep tentang manusia, kebutuhan-kebutuhannya, kemampuan-kemampuannya, dan sifat-sifat dasariahnya. Apakah manusia pada dasarnya egois atau mampu menjadi makhluk altruis? Apakah konsep itu berlaku universal atau hanya merupakan ciri khas dari suatu kultur partikular komunitas tertentu?
Secara garis besar, ada dua tipe filsafat politik yang berkembang dalam sejarah. Pertama, filsafat politik yang terintegrasi secara koheren dengan suatu sistem filsafat yang lebih besar, seperti dalam filsafat Thomas Aquinas, Hegel, dan Plato. Sistem pemikiran filsafat secara menyeluruh biasanya membentuk suatu sistem metafisika, dan filsafat politik hanya satu aspek di dalamnya. Kedua, ada filsuf politik yang tidak mengajukan suatu sistem metafisika tertentu tetapi memberikan kontribusi besar dalam filsafat politik secara spesifik seperti Cicero, Machiavelli, Rousseau, dan Marx. Pada abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Hannah Arendt, Foucault, Habermas, dan Charles Taylor dikenal karena kontribusinya dalam filsafat politik.
Filsafat Politik untuk Indonesia
Apa peran filsafat politik bagi Indonesia? Menurut saya, ada tiga peran utama filsafat politik untuk Indonesia: mendefinisikan ulang konsep dan praktek politik secara jernih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap praktek sosial yang sedang berlangsung, dan mengusulkan bentuk tata sosial yang lebih baik.
Pertama, filsafat politik dapat digunakan untuk mendefinisikan ulang konsep-konsep dan praktek politik yang telah lama diterapkan di Indonesia, seperti konsep negara, kekuasaan, otoritas, peran hukum, dan aspek keadilan dalam hukum. Misalnya, dalam bidang hukum, banyak pelaku korupsi yang lolos dari jeratan hukum karena tidak ada undang-undang yang pas untuk menjerat mereka. Filsafat hukum mengajukan proposisi bahwa hukum harus mengacu pada rasa keadilan yang sudah ada di masyarakat. Tanpa keadilan, hukum adalah penindasan. Proses mendefinisikan ulang sesuatu membutuhkan kerangka normatif, dan filsafat menyediakan itu.
Kedua, filsafat politik mampu menjadi alat untuk melakukan kritik ideologi. Setiap bangsa hidup dalam ideologi tertentu yang mencerminkan pandangan dasar yang dianut secara naif dan tidak dipertanyakan. Filsafat politik sebagai aktivitas berpikir yang terbuka, rasional, sistematis, dan kritis mampu membongkar kesesatan berpikir dalam ideologi tersebut. Misalnya, filsafat politik dapat mempertanyakan konsep manusia dalam ideologi Islamisme dan kesesuaiannya dengan kondisi yang ada. Filsafat politik dapat membongkar kesesatan berpikir dalam berbagai ideologi seperti liberalisme, amerikanisme, marxisme, dan komunisme.
Ketiga, filsafat politik tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga mengajukan model tata sosial politik alternatif yang mungkin. Tata sosial politik tersebut harus berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan solidaritas. Contoh yang relevan untuk Indonesia adalah konsep multikulturalisme, yang mengakui dan menghormati keberagaman cara hidup, cara berpikir, dan cara berkomunitas dalam masyarakat. Filsafat dapat memberikan kontribusi dalam proses bangsa ini untuk menjadi semakin beradab dan makmur, dengan menciptakan tata sosial politik yang adil dan harmonis.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.