 SAIFUL ANWAR
SAIFUL ANWAR
AIR MATA MINAH
Sastra | 2021-12-22 10:37:45
Sebuah Cerpen
Cahaya rembulan menghujani desa, masuk melalui jendela dan celah-celah dinding rumah penduduk. Di sebuah rumah terbaring jenazah. Orang itu meninggal tadi sore setelah kalah melawan penyakit stroke yang mennggerogoti tubuhnya sejak tiga tahun lalu. Beberapa orang bertakziah. Ada yang singgah, ada pula yang sekadar datang lalu pergi.
Jenazah itu aneh, mengeluarkan bau busuk dan lendir yang tak berkesudahan. Kata orang itu adalah azab.
“Kerno kena azab. Sudah pasti, sudah jelas,” kata Puji, tetangga Kerno.
“Hush, jangan asal ngomong. Kamu tidak tahu bagaimana Pak Kerno semasa hidup, kan? timpal Bambang salah satu menantu Kerno yang kebetulan mendengar perkataan Puji.
“Aku tahu betul bagiamana mertuamu itu. Aku sudah bertetangga dengannya puluhan tahun.”
“Oh ya?”
“Kau mungkin tidak mengenal dia. Kapan kau mulai tinggal di sini?” tanya Puji. Dan Bambang menyebut angka tahun. “Hm, pantas kau tidak tahu bagaimana masa lalu maertuamu. Baiklah sini kuberitahu,” Puji mendekatkan tubuhnya pada Bambang. Ia mulai bekata dengan nada yang lirih seperti berbisik.
“Semasa hidup mertuamu itu mandor bus. Ia adalah mandor yang disegani orang-orang pasar. Tapi bukan pekerjaan itu yang membuatnya terkenal. Ia dikenal orang karena dia adalah pengurus partai. Kau tahu, dia pernah menjabat ketua tim sukses salah satu calon bupati dan calon bupati itulah yang menjadi bupati kita sekarang. Orang-orang yakin keahlian Kerno itu menurun dari bapaknya.”
Cahaya lampu mera Dahulu bapaknya adalah mantan lurah di desa itu. Menurut yang sering ia ceritakan ke orang-orang bapaknya adalah lurah yang baik dan disegani oleh penduduk. Sayangnya sang bapak salah memilih partai. Yang dipilihnya bukan PNI atau Masyumi, tapi PKI. Alhasil setelah perstiwa G30S meletus sang bapak ditangkap dan dieksekusi tentara.
Anehnya Kerno tidak pernah mendapat stigma sebagai anak PKI. Hal itu terjadi karena Kerno menampilkan diri sebagai orang saleh. Ia juga sering bercerita dan meyakinkan orang-orang bahwa bapaknya bukan anggota PKI, hanya terkena tipu muslihat kader-kader partai itu.
Itulah Kerno, seorang mandor bus cum politisi di desa.
Suatu kali Kerno mendapat proyek besar; menjadi mandor pembangunan pasar desa. Nilai proyek itu mencapai milyaran. Dalam sekejap Kerno menjadi OKB alias orang kaya baru.
Adalah rahasia umum bahwa Kerno memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Mabuk, berjudi, dan sabung ayam adalah rutinitasnya. Dan yang paling buruk, bagi penduduk desa, adalah berselingkuh. Entah sudah berapa perempuan desa yang masuk ke buaian Kerno. Anehnya walau berkali-kali ketahuan selingkuh ia mendapatkan kembali kepercayaan istrinya. Sang istri, Minah yakin bahwa Kerno akan berubah setelah meminta maaf.
Kebaikan hati Minah nyatanya tak membuat Kerno insyaf. Ia makin menjadi-jadi. Pada akhirnya, kali ini, Kerno memilih selingkuhannya. Ia menceraikan Minah dan meninggalkan kedua anaknya demi menikahi si selingkuhan. Kerno jual rumah dan tanah hasil gunakaya-nya dengan Minah dan uang hasilnya ia gunakan untuk kawin. Minah dan anak-anaknya tak mendapat apapun, mereka lalu hidup dalam keadaan serba kekurangan.
Bulan menghilang di balik awan, namun cahaya bintang masih nampak, walau sedikit. Orang-orang masih mengerubungi rumah itu sambil menutup hidung. “Sudah jelas ia dilaknat” kata seseorang, “itu karena dulu ia berbuat jahat pada istri dan anak-anaknya,” sambungnya. Kalimat itu kemudian disambung dengan kalimat-kalimat lain. Bisik-bisikpun tercipta. Kian riuh.
Beberapa saat kemudian datang perempuan baya bersama dua anaknya, seorang laki-laki dan seorang perempuan.
“Ssst, itu Minah, mantan istri Kerno” bisik seseorang. Dan memang itu Minah. Ia bergegas masuk ke rumah bersama kedua anaknya. “Bapaaak!” tiba-tiba anak perempuan Minah berteriak histeris setelah melihat jenazah bapaknya, teriakan itu disusul tangis keras yang seperti lolongan ajak. Si anak laki-laki juga menangis tersedu-sedu, tak kalah keras dari sang kakak.
Minah hanya diam, tenang, dan sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. “Sabar, Nok, Dik” ucap Minah. Kedatangan mereka menarik perhatian orang-orang. Bisik-bisik pun lambat laun menghilang.
“Syukurlah kalian datang,” seorang lelaki baya berpeci hitam tiba-tiba mendekati Minah dan kedua anak itu.
“Iya Pak, bagaimana?” tanya Minah.
“Dengan datangnya kedua anak ibu, jenazah Pak Kerno bisa segera dimandikan”
“Loh, istri almarhum kan ada?”
“Nah itu masalahnya, Bu. Istri almarhum tidak mau memandikan jenazah. Dengan demikian maka hanya anak-anak ibulah yang bisa dan boleh. Itupun jika mereka mau.”
Sejenak Minah memandang kedua anaknya. Lalu ia dekati mereka dan mengatakan dengan penuh kelembutan bahwa jenazah harus segera dimandikan. Mereka menangis di depan jenazah sang bapak. Minah merangkul keduanya sambil berbisik “anak-anakku, kalian harus ikhlas. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Sekarang, mandikanlah jenazah bapak kalian.” Dengan air mara yang meleleh keduanya mengangguk lalu bangkit mempersiapkan diri.
Jenazah di tempatkan di tempat pemandian. Sebuah keranda dan berember-ember air telah menunggu. Dengan bimbingan laki-laki baya berpeci hitam kedua anak Minah memandikan jenazah Kerno. Gerakannya perlahan dan sangat hati-hati. Mereka percaya orang mati masih bisa merasakan sakit, bahkan setetes airpun bisa membuat arwah jenazah menjerit-jerit.
Minah menyaksikan proses itu dari jarak yang tak jauh. Ia saksikan tubuh Kerno yang kini basah dan kaku. Itulah tubuh orang yang dahulu memberinya kepedihan, tubuh yang pernah bersetubuhnya lalu melahirkan anak-anak. Dan tangan itu, ah, Minah masih ingat betul setiap permukaannya. Itulah tangan yang dahulu pernah melingkarkan cincin di jari manisnya, tangan yang pada suatu waktu pernah membelainya penuh kasih sayang dan pada waktu lain memberi tamparan keras.
Perpisahan dengan Kerno menyisakan luka yang teramat perih. Peristiwa itu terjadi limabelas tahun lalu itu, waktu si bungsu masih berumur dua tahun. Itulah hari ketika tangan-tangan kuat Kerno menerjangi pipi Minah, dan kaki-kaki kuatnya menendangi tubuh Minah hingga perempuan itu menderita lebam di sekujur tubuh. Kaca-kaca rumah pecah, serpihannya berserakan. Penyiksaan itu terjadi di malam hari saat semua orang tengah istirahat.
“Kamu pikir aku tidak tahu, Mas?”
“Kamu termakan omongan orang. Dasar goblok!”
“Kamu sudah keterlaluan, Mas!”
“Dasar istri goblok!” Pok!
Pukulan itu mendarat lagi di wajah Minah, entah untuk yang ke berapa kali. Kerno yang semakin terbakar emosi pergi ke dapur, mengambil sebilah pisau dan hendak menusukkannya ke perut Minah. Minah lari ketakutan. Kerno sudah berubah menjadi setan yang kerasukan iblis, pikirnya. Minah keluar, lari sambil menggendong si bungsu yang sedari tadi menangis di pelukannya. Untunglah waktu itu si sulung sedang di rumah saudara sehingga tak melihat penyiksaan itu. Tetangga yang melihat peristiwa itu diam dan hanya berani mengintip dari jendela.
Enam tahun berlalu tetapi bayang-bayang peristiwa itu masih belum hilang dari kepala MInah. Ia hanyut dalam lamunan masa lalu ketika tanpa ia sadari proses pemandian jenazah sudah selesai dan si bungsu mendekatinya dan bertanya “Ibu, kau menangis?”
*Cerpen ini saya persembahkan untuk Ibu saya, Siti Aminah
Semarang, 18 Januari 2021
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.



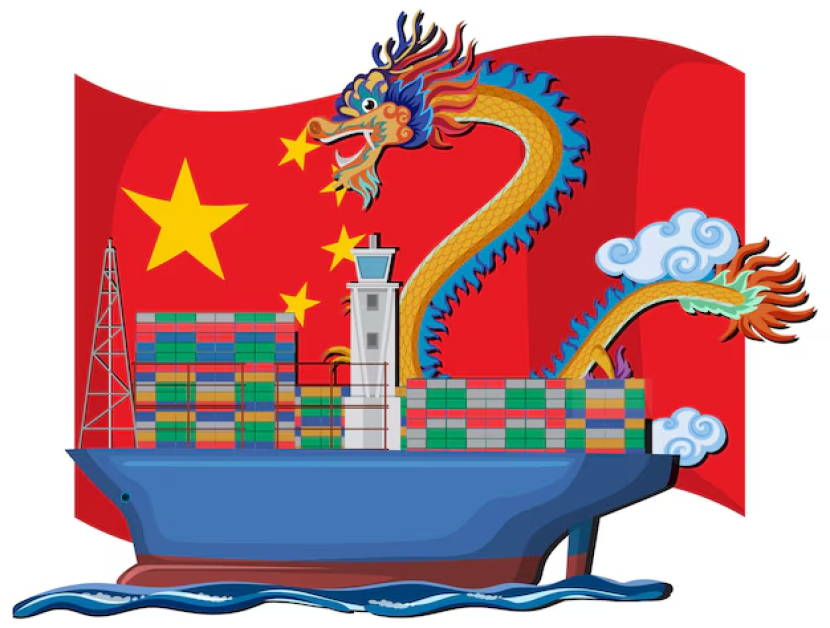





Komentar
Gunakan Google Gunakan Facebook