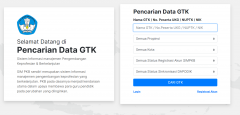Anicetus Windarto
Anicetus Windarto
Wajah Pendidikan Kala Pandemi
Guru Menulis | Thursday, 23 Sep 2021, 12:52 WIB
A. Windarto
Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta
Menarik sesungguhnya untuk mengkaji ulang wajah pendidikan yang selama ini telah membentuk generasi muda di Indonesia, khususnya di kala pandemi. Bukan kabar burung belaka bahwa dunia pendidikan selama ini masih terperangkap dalam sebuah model sekolah yang melelahkan dan seperti sebuah penjara. Dalam sekolah itu, baik siswa maupun guru, sekadar ditempatkan sebagai mesin aplikasi yang digunakan untuk memenuhi beragam tuntutan akademis. Lebih parahnya lagi, yang kerap dituntut umumnya adalah kuantitas administratifnya daripada kualitas edukatifnya. Akibatnya, terjadilah apa yang disebut dengan gejala intoleransi dan agresi yang mengebiri nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam hal imajinasi anak-anak sekolah.
Dalam konteks ini, menarik untuk membandingkan dengan sebuah pengalaman yang ditulis Benedict Anderson dalam buku otobigrafinya berjudul Hidup di Luar Tempurung (Marjin Kiri, 2016). Pengalaman itu berkait dengan masalah di sebuah jurusan yang menolak memberikan jabatan pengajar tetap bagi seorang dosen. Masalah ini telah berlangsung selama 10 tahun dan tak seorang pun yang mampu mengatasinya, bahkan pejabat sekelas dekan. Usut punya usut, demikian Ben menulis pengalamannya, masalah itu terletak pada ketidaksamaan di antara staf pengajar di jurusan tersebut, selain karena alasan tidak suka dan tidak mau saling memahami.
Ironisnya, di jurusan yang secara disipliner mempelajari ilmu kejiwaan, justru menjadi indisipliner dalam menghadapi masalah yang hanya memfungsikan jurusan sebagai wadah administrasi dan anggaran belaka. Cukup jelas bahwa dari tiga kelompok yang ada di jurusan itu, masing-masing para psikolog behavioris, psikoanalisis, dan sosial, sama-sama tidak memahami, apalagi mencoba memahami, apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh tiap-tiap kelompok. Maka tak heran jika terbangunlah blok-blok yang saling membatasi di antara ketiganya hingga akibatnya kandidat mana pun yang mau diangkat sebagai profesor misalnya, akan dengan mudah diveto atau dianggap hina karena memiliki kedekatan dengan salah satu blok.
Pada titik inilah aura akademis dalam pendidikan telah kehilangan kontak secara disipliner. Bahkan tak jarang justru berubah menjadi sebuah ideologi baru bernama âprofesionalismeâ. Hal itulah yang membuat pendidikan tinggi hanya berpretensi menghasilkan âtikus teoriâ atau âteoritikusâ sebagaimana ditulis Ben sebagai âKata Pengantarâ dalam buku berjudul Indonesia dalem Api dan Bara karya Tjamboek Berdoeri (Elkasa, 2004). Bahkan pretensi macam itu distandarkan sedemikian rupa sehingga dalam setiap kuliah para mahasiswa diberi daftar bacaan yang âsecara profesionalâ sangat menekankan pada âteori terkiniâ. Jadi, para mahasiswa yang telah âdilatihâ, bukan dididik, dalam kelas-kelas itu secara ideal siap bersaing dalam apa yang mulai dikenal sebagai âbursa kerja akademikâ. Gelar akademis mereka, bahkan PhD sekali pun, hanya menjadi sebuah kualifikasi profesi setara dengan dokter, pengacara atau guru yang wajib lulus ujian profesi untuk bisa diberi izin praktik atau mengajar.
Di bawah iklim seperti itu, bukan kebetulan jika kultur profesionalisasi dan ekspansi besar-besaran akademik ke bursa kerja menjadi pilihan yang tak tertandingi. âNama-nama besarâ dari dunia pendidikan tinggi menjadi semacam jimat atau mantra untuk membantu dalam pencarian kerja. Apalagi jika nama-nama itu berasal dari jurusan atau program studi yang sesuai dengan kepentingan di bursa kerja seperti programming, broadcasting, atau bahasa asing. Itu artinya, hanya disiplin ilmu yang cocok dengan bursa kerja sajalah yang begitu diminati dan dijadikan sebuah keahlian. Hal ini bukan perkara malas atau bahkan egois, melainkan atas dasar pengamatan terhadap para staf pengajar, terutama para profesor, yang sudah terbiasa dengan profesionalisme.
Maka masuk akal jika semakin langka intensi yang kuat dalam kelas-kelas yang menawarkan mata kuliah dari disiplin-disiplin ilmu lain. Selain tak lagi banyak gunanya dalam meningkatkan peluang di bursa kerja, juga malah bisa membuat segalanya menjadi tampak âamatiranâ. Hal inilah yang mengakibatkan sterilnya kajian dalam program studi/jurusan yang bersifat lintas ilmu (cross disciplinary). Padahal dengan kajian seperti itu, dimungkinkan adanya suatu jaringan kontak/koneksi antar dosen dan mahasiswa dari berbagai latar disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dengan demikian, baik publikasi ilmiah maupun mata kuliah, dapat diproduksi dengan lebih kaya dan beragam. Bahkan yang tak kalah penting adalah meruntuhkan pagar-pagar disipliner agar dunia pendidikan tinggi tidak terkurung dalam tembok-tembok intelektual yang memberi batasan dan definisi terhadap keilmuannya belaka.
Penting untuk dicatat bahwa kreatifitas akademis hanya akan tumbuh dan berkembang jika paduan antara egoisme kebangsaan dan rabun jauh disiplin ilmu mampu diatasi dengan diskusi dan adu pendapat yang sepenuhnya sadar dan jeli terhadap asal-usul dan perkembangan zigzag berbagai ilmu. Dari pengalaman Ben di atas, kata âdisiplinâ yang diikuti dengan kata âilmuâ mempunyai sejarah yang terentang panjang di balik ketaatan para rahib Abad Pertengahan. Mereka tampak begitu kaku dan beku dalam menghukum diri sendiri dengan maksud menaklukkan raga sebagai musuh jiwa hingga tak memberi sedikit pun celah bagi âkelancanganâ dan lanturan-lanturan tak relevan. Hasilnya, seperti nasib para perempuan Tionghoa dalam tradisi lama, kaki-kaki mereka menjadi semakin mengecil dan sulit untuk digunakan lantaran harus dibebat erat-erat sepanjang hidupnya.
Dunia pendidikan yang masih dibebani dengan berjubel hal-hal âterlarangâ niscaya akan mengalami nasib serupa. Maka, poin yang jelas dan mendesak untuk dikerjakan adalah merobohkan tembok-tembok disipliner di kelas-kelas agar mutu dari peserta didik menjadi semakin meningkat sekaligus mengurangi kejemuan dan membuka jalan bagi mereka yang potensial untuk berkarya lebih jauh dan luas. Dan inilah saat dan tempat yang tepat untuk mewujudkan pesan Ben berikut ini bagi generasi (terdidik) masa kini: âKatak-katak dalam perjuangan mereka untuk emansipasi hanya akan kalah dengan mendekam dalam tempurungnya yang suram. Katak sedunia, bersatulah!â
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.